Graha dan Vigraha
 By I Putu Suweka Oka Sugiharta
By I Putu Suweka Oka Sugiharta- 28 Maret 2021

Rumah (graha) menjadi tempat yang sakral bagi Manusia Bali. Pembangunan suatu rumah mesti melalui proses panjang sebelum benar-benar layak untuk ditempati. Mulai dari ritual nyukat karang (mengukur tanah yang akan dibanguni) dan disesuaikan dengan ukuran organ-organ tubuh tertentu dari calon penghuninya. Diyakini bila suatu rumah memakai ukuran orang lain atau tidak diukur dengan cermat maka akan mendatangkan keburukan-keburukan. Setelah rumah berhasil dibangun pun berlanjut dengan perhatian terhadap berbagai hal yang berada di sekitarnya seperti keberadaan tembok pembatas (panyengker), pepohonan yang tidak menjulur melewati panyengker, hingga atap rumah serta air cucurannya yang tidak melewati area panyengker. Semuanya tentu bukanlah sewujud fanatisme yang mengada-ada. Secara sosiologis rumah yang dibangun Orang Bali mengindikasikan jika dari tempat itulah kelak penghuninya akan mempertanggungjawabkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat luas. Sekaligus secara rohani menjadi tempat melakukan sadhana. Dalam pandangan teologi tubuh, rumah malahan merupakan simbol tubuh pemiliknya karenanya tidak dapat diubah sekehendak hati. Berbagai penyakit yang menghampiri kehidupan Orang Bali sering kali dipandang bersumber dari tata letak maupun perubahan bangunan rumah yang telah diupacarai.
Orang Bali yang beragama Hindu telah demikian terlatih merumahkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Sesuatu yang sakral ditempatkan di ruang sakral demikian pula hal-hal profan dipisahkan dari dimensi kesakralan. Barangkali hanya Orang Bali yang demikian taat menjaga supaya keutamaan sesuatu yang luhur tidak dicemari oleh benda-benda non sakral di atasnya (kaungkulin). Seperti seseorang tidak diperkenankan memegang kepala maupun duduk di posisi yang lebih tinggi dari orang yang lebih tua atau kedudukannya lebih tinggi. Demikian pula ketika arca para dewa (vigraha) diarak berkeliling (malancaran) maka akan dicarikan rute yang tidak ternaung oleh bangunan-bangunan buatan manusia seperti saluran air yang melintang di atas jalan, terowongan, jembatan, dan semacamnya. Sementara dalam tata perumahan, posisi yang lebih di hulu digunakan sebagai tempat suci dan yang lebih hilir menjadi ruang yang semakin profan. Manakala Orang Bali misalnya akan menjemur pakaian maka sebisa mungkin menghindari posisi atas. Mereka yang berjalan di bawah jemuran bahkan tali bekas jemuran diyakini dapat luntur kesucian dirinya.
Ketaatan Orang Bali sering kali dipandang berlebihan oleh orang luar yang tidak memiliki kepercayaan serta kebiasaan serupa. Sementara Orang Bali sendiri banyak yang melupakan makna esensial dari kebiasaan-kebiasaan tersebut sehingga lahirlah fanatisme tanpa dasar dan arah. Padahal sejatinya tentu jembatan tidak semudah itu melunturkan kekuatan Tuhan yang disimbolkan oleh arca-arca. Demikian halnya dengan tali jemuran tidak serta-merta melunturkan potensi kesucian yang bersemayam dalam diri seseorang. Pemandangan yang terjadi tiap-tiap menjelang Nyepi semakin menguatkan argumen ini. Ketika itu arca-arca sakral yang sebelumnya dipuja di tempat-tempat luhur tiba-tiba diarak menuju tempat terendah bernama lautan. Sebuah tempat di mana air-air kotor yang berasal dari daratan bermuara. Kini lautan juga menjadi penampungan sampah yang hanyut dari daratan. Fenomena tersebut sangat mungkin menjadi penanda adanya batas tak terlihat antara sakral-profan, tinggi-rendah, bersih-kotor, mulia-hina, dan semacamnya.
Tampaknya Orang Bali telah demikian disiplin menjaga batas-batas maya semacam itu yang tentunya memiliki implikasi serius, meski tidak selalu pragmatis. Memang terlihat tanda-tanda kegamangan hati sebagian Orang Bali ketika Nyepi tiba: tak ada bahaya yang mengancam namun tidak diperbolehkan keluar rumah. Barangkali keraguan semacam itu telah menginap pada pikiran sebagian Manusia Bali semenjak puluhan bahkan ratusan pelaksanaan Nyepi. Kini pertanyaan itu telah dijawab tuntas, tidak hanya dalam scope Bali tetapi dunia. Orang-orang menjadi paham makna latihan merumahkan diri dalam situasi yang secara visual tampak tidak mengancam maupun menakutkan. Gejala semacam itu mirip dengan kecenderungan dasar pada pemuja-pemuja kekuatan adikodrati semenjak periode purba: takut dan tunduk kepada sesuatu yang tidak kasat mata. Jauh sebelum teleskop ditemukan dan para ilmuwan mampu membuat wahana antariksa seperti yang dikenal sekarang, orang-orang masa lampau telah mempelajari seni merumahkan diri dari benda-benda langit. Menariknya nama lain dari planet-planet dalam bahasa Sanskerta adalah graha. Nama-nama planet misalnya ditemukan dalam Yajnavalkya-Smrti 295 yang terdiri atas Matahari (Surya), Bulan (Soma), Mars (Mahiputra), Merkurius (Somaputra), Jupiter (Bhraspati), Venus (Sukra), Saturnus (Saniscara), Rahu dan Ketu (suryah somo mahiputrah somaputro bhraspatih sukrah saniscaro rahuketus ceti grahah smrtah). Planet-planet tersebut diyakini memiliki penguasa yang mengatur geraknya pada garis edarnya masing-masing, jika tidak tentu tabrakan antarbenda langit akan terjadi.
Manusia yang menyadari dirinya sangat kecil kemudian tahu diri untuk tidak melanggar batas-batas kewenangannya. Termasuk memberikan ruang kepada hal-hal tidak terlihat yang diyakini menjadi dasar sekaligus penyebab dari segala yang ada. Dalam Lontar Tutur Angkusprana 1b ruang ini disimbolkan dengan penciptaan Bapa Akasa dan Ibu Pertiwi yang memiliki batas kekosongan pada bagian tengahnya (embang ring tngah). Lewat bagian kosong inilah kehidupan dapat berlangsung. Selanjutnya bentuk turunannya di bumi berlaku pada terowongan, aliran sungai, pancuran, dan semacamnya. Dalam Kebudayaan Bali terdapat pantangan untuk menutup (ngempetin) saluran-saluran seperti terowongan, pancuran, sungai, termasuk jalan. Pelakunya diancam dengan berbagai macam bencana dan kesialan. Demikan pula pada kanal-kanal vital dalam tubuh manusia seperti saluran pencernaan, urin, darah, nafas, dan sebagainya tidak boleh terganggu oleh sumbatan apa pun. Secara ibadati melalui Nyepilah diciptakan ruang kosong yang menjadi pembatas antara keramaian sebelum dan setelahnya. Memang seolah tidak ada perbedaan yang signifikan antara keriuhan sebelum dan sesudah Nyepi bila dilihat dengan pikiran dangkal. Selain itu fokusnya memang bukan pada keramaian keduanya, namun pada manajemen kesunyian yang sengaja diciptakan di tengahnya.
Dalam beberapa naskah dikisahkan tentang malapetaka yang menimpa para pelanggar batasan-batasan tertentu yang telah ditentukan bagi mereka. Teks Kidung Tantri Kediri memuat cerita tentang seorang penjahat bernama Batur Taskara yang menjadi buronan di Negeri Padaliputra. Mengetahui dirinya menjadi buronan negara Batur Taskara kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Di sanalah ia bertemu dengan seorang guru kerohanian yang kemudian mengajarkan kepadanya aspek-aspek kegaiban. Batur Taskara diperintahkan oleh gurunya melakukan latihan rohani di kuburan. Dalam semedinya Batur Taskara mendapat wahyu gaib dari penguasa kuburan. Setelah ditanyakan kepada sang guru dijelaskanlah bila makna dari wahyu yang diterimanya adalah larangan untuk pergi ke Desa Bhadrawada. Beberapa lama kemudian Batur Taskara di tempat pertapaannya kedatangan seorang wanita cantik yang selanjutnya diperistri olehnya. Batur Taskara lalu mendapatkan seorang putera tampan dari istri misteriusnya itu. Pada suatu hari sang anak merengek-rengek kepada ayahnya untuk diantar menjenguk kakeknya. Betapa terkejutnya Batur Taskara ketika mengetahui bila istrinya berasal dari Desa Bhadrawada. Mulanya Batur Taskara berterus terang jika dirinya tidak mungkin menginjakkan kaki di tempat tersebut. Penjelasan Batur Taskara membuat istrinya jengkel yang selanjutnya meninggalkan rumah dengan membawa serta sang anak. Batur Taskara mau tidak mau harus mengikuti kepergian istri dan anaknya yang sama-sama dicintainya. Perjalanan yang jauh menyebabkan sang istri kelelahan, terlebih karena menggendong anak. Batur Taskara lalu berinisiatif menaikkan anak dan istrinya ke atas gerobak. Ketika tiba di Padaliputra, sang raja secara kebetulan kehilangan kambing dan anak kambing kesayangannya. Para prajurit diperintahkan untuk mencarinya. Hingga ditemukanlah dua anak kambing raja di gerobak milik Batur Taskara yang merupakan penjelmaan anak dan istrinya. Batur Taskarapun menemui ajal di tangan para prajurit kerajaan.
Pelanggaran yang serupa dilakukan oleh Sita dalam salah satu versi kisah Ramayana. Ketika hendak meninggalkan Sita untuk menyelamatkan Rama, Laksmana berpesan kepada kakak iparnya itu agar tidak meninggalkan garis perlindungan yang telah dibuatnya. Sayangnya Sita melanggarnya sehingga berhasil diculik oleh Rahwana yang tengah menyamar. Melalui kesadaran untuk merumahkan diri saat Nyepi setiap orang dapat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang berpotensi terjadi padanya. Rumah adalah sesuatu yang istimewa karenanya tidak sembarang orang bisa memasukinya tanpa izin dari pemiliknya. Terlebih badan sebagai rumah dari atman semestinya dijaga dengan kehati-hatian yang lebih murni. Tatkala dalam sadhana Nyepi seseorang mampu merumahkan badannya sekaligus merumahkan indria-indrianya pada tempatnya maka saat itu juga vigraha telah tercapai. Vigraha dalam proses ini berarti keterpusatan pada perwujudan Tuhan yang hakiki.





.jpg)
.jpg)
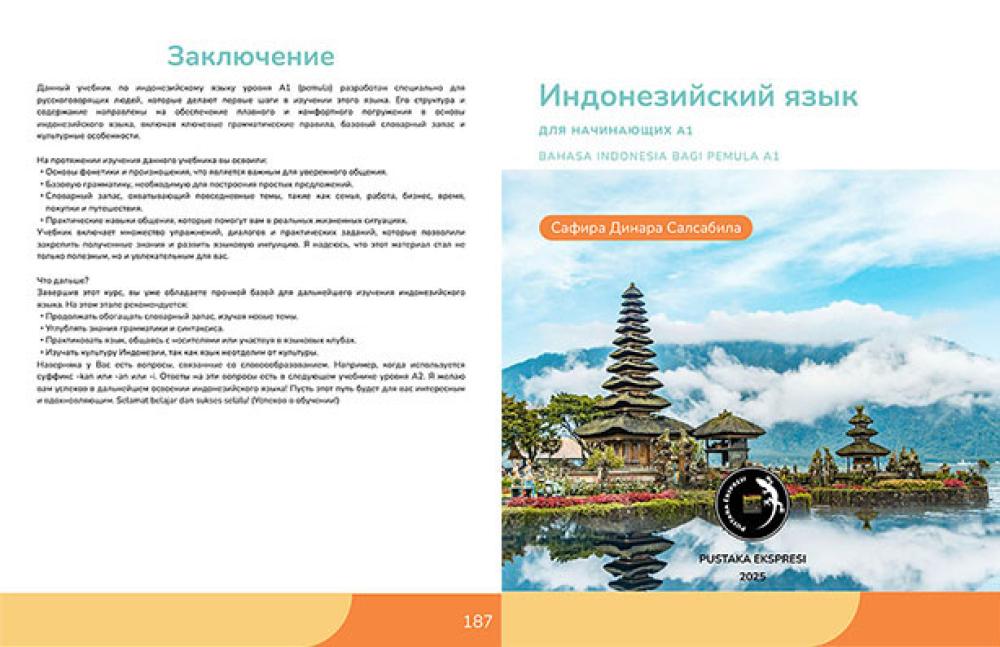
.jpg)
.jpg)

.jpg)

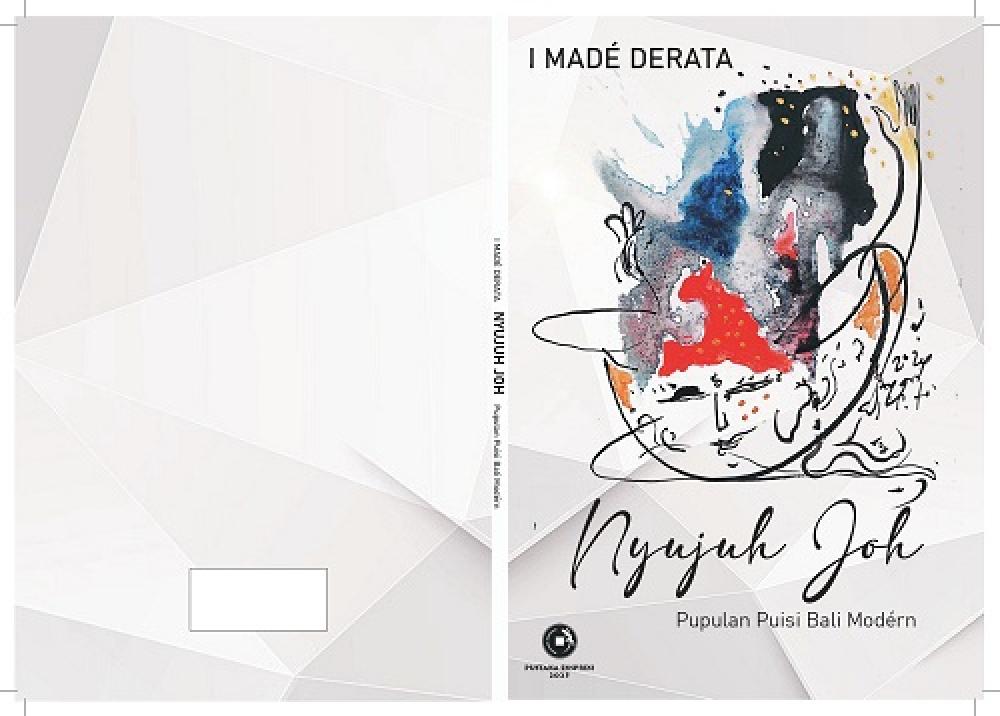


Komentar