Saraswati dan Perjalanan ke ‘Dalam’ Pendidikan Kita
By
- 14 Desember 2019

Metode pengajaran jadi mirip mode pakaian yang didikte oleh trend. Begitu ada metode baru yang sedang jadi trend para pengambil kebijakan di bidang pendidikan turut gelisah.
I Putu Suweka Oka Sugiharta*
Saraswati dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat mengalir sebagaimana jalannya ilmu pengetahuan yang mengalir dari yang lebih berpengetahuan kepada yang kurang berpengetahuan. Selain itu, Saraswati yang rutin dirayakan saban 210 hari sekali mengajak kita untuk secara rutin pula memeriksa ‘aliran’ pendidikan kita dari hulu ke hilir. Jangan sampai pencemaran atau malah pengecilan debit air yang terjadi di hulu tidak kita sadari.
Penulis berkesempatan mendengar cerita dari beberapa akademisi yang baru saja datang dari berlawat mengamati model pendidikan di dunia barat. Tema ceritanya mengandung kemiripan, tentang betapa egaliternya hubungan guru dan murid di sana. Katanya, murid dengan riang hati menyisir rambut gurunya seolah tanpa jarak sama sekali. Murid tidak dilarang duduk di atas meja, mengenakan pakaian bebas, berambut gondrong, dan semacamnya. Menurutnya sisi feodal yang masih dipertahankan dalam dunia pendidikan Indonesialah yang menghambat kreativitas siswa sehingga kemajuan yang diharapkan gagal diraih.
Anggapan semacam itu tentu masih sangat debatabel mengingat landasan budaya yang masih ‘disegani’ dalam pendidikan kita. Kendatipun keseganan itu tidak lantas menggambarkan kepatuhan dan penghayatan yang sungguh-sungguh.Pada pratiknya justru ketidakpercayaan terhadap unsur-unsur lokal itu lebih nyata. Akibatnya sampai hari ini pendidikan kita tampak semakin gontai, tidak kunjung menemukan titik perhentian yang nyaman. Berbagai metode yang berasal dari luar, hasil-hasil pemikiran para ahli kesohor diujicobakan bergiliran namun belum juga membuahkan hasil yang memuaskan. Aulia (2011:24) menyebut salah satu permasalahan pokok dalam pendidikan Indonesia adalah kurikulum yang selalu ada perubahan serta ketiadaan goal yang jelas ketika pergantian antar kurikulum.
Keranjingan untuk gonta-ganti kurikulum itu dimulai dari Rencana pelajaran 1947 yang jelas masih berbau Belanda dengan berfokus pada pembentukan watak, kesadaran bermasyarakat dan bernegara, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, penekanan pada bidang kesenian, serta pendidikan jasmani. Tahun 1952 muncul kurikulum Rencana Pelajaran Terurai yang terkonsentrasi pada pengembangan lima aspek (Pancawardhana) yang terdiri atas cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pancawardhana diperkuat lagi dengan kemunculan Kurikulum 1968. Walaupun kurikulum ini kemudian banyak dikritik karena sifat teoretisnya yang jauh darikenyataan di lapangan. Selanjutnya lahir kurikulum Satuan Pelajaran (1975) yang membuat guru lebih sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis sehingga kurang memiliki kesempatan memenuhi hal-hal yang lebih esensial. Tahun 1984 dicetuskan kurikulum CBSA yang sedianya difungsikan untuk memberi seluas-luasnya ruang pada keaktifan siswa. Sayangnya pada kenyataannya suasana belajar menjadi gaduh sebab aktifnya siswa bukan semata bersungguh-sungguh belajar. Setelahnya diberlakukan Kurikulum 1994 dan Suplemen 1999 yang menjadi semakin tidak efektif akibat padatnya materi karena merupakan gabungan dua kurikulum sebelumnya (Kurikulum 1975 dan 1984).
Pasca reformasi, kurikulum berbasis kompetensi yang berbayang Taksonomi Bloom diberlakukan tahun 2004. Secara teknis kurikulum ini sangat integral, sebab disebut-sebut mampu mewadahi aspek kognitf, afektif, dan psikomotorik. Realitanya tidak saja orangtua yang kebingungan membaca rapport anaknya, para guru juga masih kelimpungan dalam memberikan penilaian. Dua tahun kemudian muncul kurikulum KTSP yang menuntut agar pembelajaran lebih membumi, materi pelajaran disesuaikan dengan karakteristik lingkungan peserta didik. Terakhir, keperkasaan KTSP dikandaskan oleh Kurikulum 2013 yang hingga kini masih menjadi tumpuan harapan dunia pendidikan kita.Meski berbagai kelemahan mulai nyata menganga seperti pada tingkat pendidikan dasar para guru masih kebingungan mengaplikasikan pembelajaran tematik. Selain itu permasalahan administratif yang menjelimet mengurangi porsi waktu guru untuk menemai murid di kelas.
Metode pengajaran jadi mirip mode pakaian yang didikte oleh trend. Begitu ada metode baru yang sedang jadi trend para pengambil kebijakan di bidang pendidikan turut gelisah. Ingin cepat-cepat mengadopsinya di tanah air tercinta. Praktis, metode lama yang dipandang telah ketinggalan zaman ditinggalkan begitu saja. Tentu kemudian timbul kecurigaan jika fenomena tersebut merupakan bentuk lain dari merkantilisme pendidikan. Bagaimana tidak, jelang perubahan kebijakan pendidikan pastilah didahului kajian-kajian beranggaran selangit. Belum lagi setelahnya diikuti dengan proyek pencetakan buku pelajaran baru yang mengatasnamakan revolusi pengajaran. Dapat dipahami bila ketidakmenentuan pendidikan di negara-negara berkembang merupakan akibat dari campur tangan negara-negara maju yang concern memperluas jemaring kapitalis.
Effendi (dalam Putra 2016:3) menyatakan para ekonom dunia membagi usahanya ke dalam tiga sektor seperti sektor primer (pertambangan dan minyak), sektor sekunder (mengubah bahan dasar menjadi barang), dan sektor tersier yang berfokus pada pelayanan. Pendidikan termasuk dalam bidang usaha yang ketiga yakni human services. Oleh karena pendidikan sudah mejadi komoditi bisnis maka tempat usahanya juga harus dibuat semenarik mungkin beserta promosi-promosi yang menggiurkan. Termasuk juga penciptaan pengkelasan-pengkelasan sosial yang berkaitan dengan sekolah, orang yang tidak sekolah dipandang kurang berkelas dibandingkan mereka yang bersekolah. Demikian juga mereka yang bersekolah di sekolah biasa dianggap kurang berkelas jika dibandingkan dengan individu-indvidu yang bersekolah mahal berstandar internasional. Program-program beasiwa ditawarkan oleh negara-neraga maju bagi orang-orang cerdas di negara-negara berkembang dengan harapan mereka yang terjaring ke dalamnya nantinya akan menjadi tandem yang produktif dalam menyebarluaskan ide-ide kapitalis. Dengan melihat Gestur pendidikan kita yang tampak semakin bersenang hati untuk dibaratkan, sudah dapat ditebak siapa pemenang dari permaian ini. Model-model pembelajaran lokal dan literatur-literaturtradisional hanya menjadi acuan sekunder. Penelitan-penelitian bernuansa etnopedagogi atau kajian terhadap manuskrip-manuskrip lokal memang semakin intens dilakukan, namun pendiktenya tetaplah teori-teori barat.
Para pengambil kebijakan maupun pelaku pendidikan di negeri ini mestinya kembali eling pada sikap hidup Ki Hajar Dewantara yang meskipun sempat mendalami pendidikan barat namun akhirnya berkeyakinan bila nilai-nilai pendidikan dari bumi Indonesialah yang terbaik. Taman Siswa yang dirintisnya diilhami oleh model pesantren yang sesungguhnya telah berembrio semenjak masa pra Islam. Taman Siswa dan Saraswati secara prinsip memiliki banyak kesamaan. Taman adalah tempat bertabur keindahan dengan bunga-bunga, pepohonan, dan penataan-penataan estetis lainnya. Saraswati juga serupa, disimbolkan berwajah cantik jelita ditambah dengan keahlian memetik Vina (gitar) dengan merdu. Dari dua kosep yang sejatinya in line tersebut terefleksi bahwa sebenarnya pendidikan Indonesia tidak sedang memerlukan kurikulum baru secara mendesak. Sebab merehabilitasi indvidu-individu yang menjadi korban kurikulum tidaklah sesederhana mengobras pakaian. Dunia pendidikan kita sesungguhnya bisa ‘sehat tanpa obat’ sebab segala potensi penyembuhan sejatinya telah ada pada dirinya. Dengan demikian pendidikan kita tidak perlu menuju kemana-mana, selain menuju dirinya sendiri. Perjalanan ke dalam ini di Bali dikenal dengan mulat sarira.
Selepas bertamasya ke ‘dalam’ akan disadari bila satu-satunya hal mendesak dalam pendidikan kita adalah menciptakan suasana belajar yang dipenuhi keindahan. Kondisi masyarakat dewasa ini yang dibanjiri ujaran kebencian hingga hoax menandakan bila pendidikan Indonesia gagal menyajikan harmoni. Saraswati dikenal dengan sebutan Vag Devi (Dewi yang menguasai kata-kata). Konsistensi dan kehalusan kata-kata merupakan indikasi keterpelajaran, tidak butuh sekolah mahal, gelar akademis tinggi, atau sertifikasi-sertifikasi bonafide untuk membuktikan keterpelajaran. Cara berkomunikasi yang membawa kedamaian dan kesetiaan terhadap kata-kata sendiri kiranya telah lebih dari cukup. Dalam rapat terbatas diIstana Presiden tanggal 31 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo secara khusus berpesan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim agar mengusahakan perbaikan kurikulum yang harus dilakukan searah dengan kemajuan teknologi. Semoga melalui perbaikan kurikulum tersebut nantinya dapat tergali kembali nilai-nilai yang menceriminkan jati diri bangsa sekaligus membuktikan jika Pendidikan Indonesia mampu berpendirian teguh di atas kakinya sendiri.
*Dosen STKIP Amlapura dan penulis buku, berdomisili di Karangasem




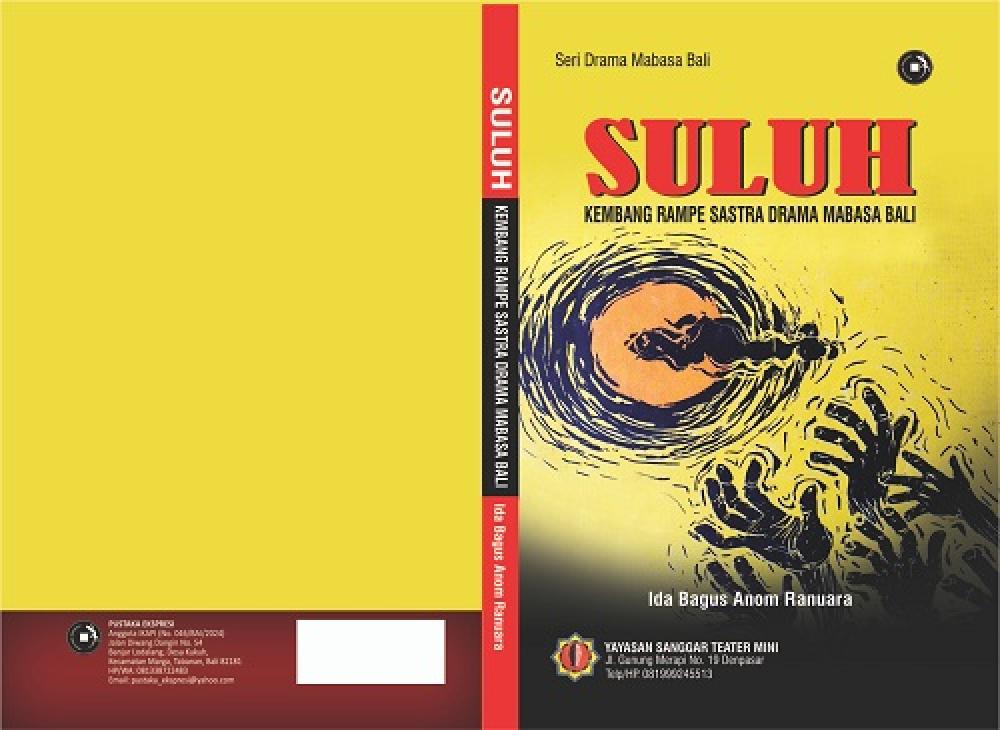





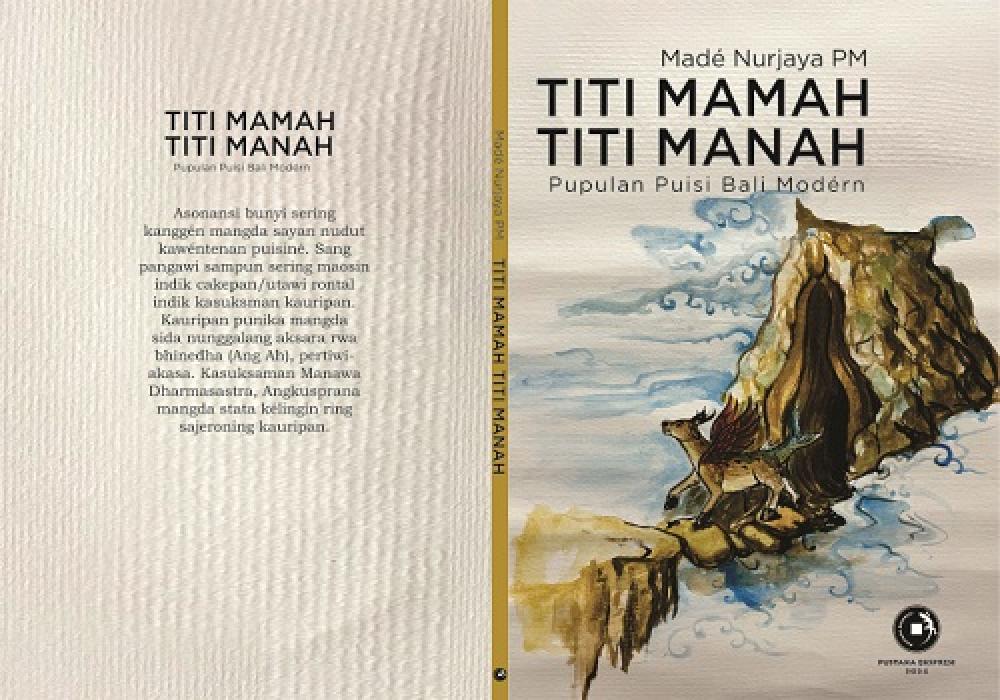

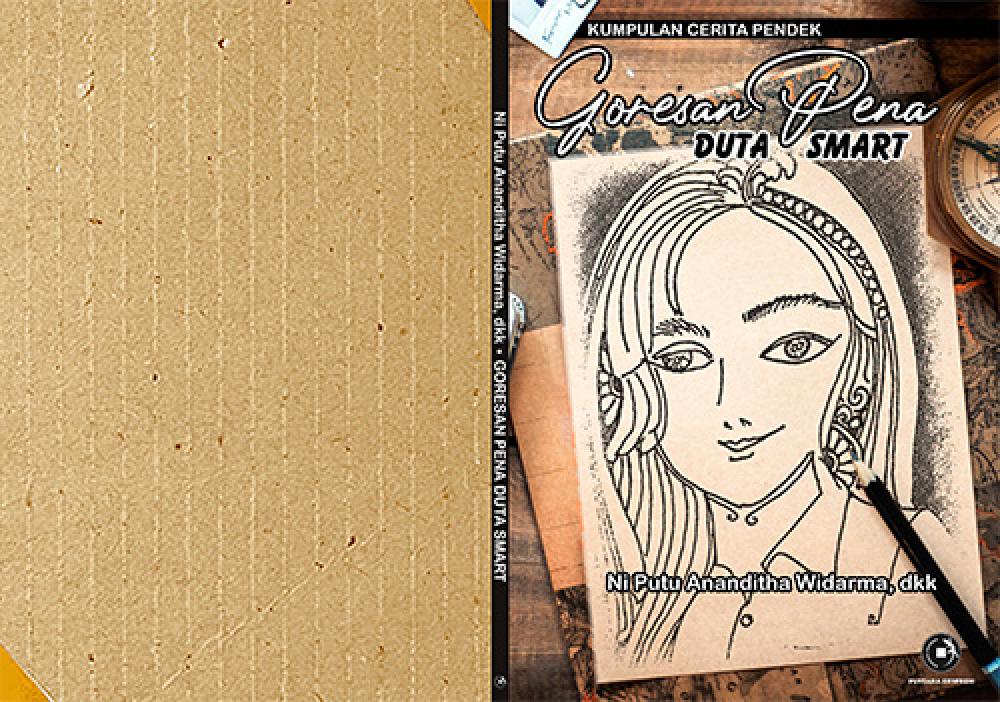


Komentar