Hujan Senja Hari
By IBW Widiasa Keniten
- 04 November 2022

HUJAN di senja ini tampaknya tak mengenal pilih kasih. Deras dan teramat deras seperti memuntahkan kemarahan yang telah lama dipendamnya. Angin kencang dengan deruannya yang menciutkan nyali. Petir, guruh, kilat saling beradu. Ia bagaikan monster yang siap melumat tubuh ini. Tak ada kekuatan yang melebihi kekuatan alam. Manusia hanya setitik baginya. Nyaliku semakin ciut lebih-lebih pohon kelapa yang berdiri dekat rumahku meliuk-liuk diterpa angin disertai angin kencang yang tanpa arah itu. Pohon kelapa itu biasanya tersenyum memperlihatkan kesejukannya sekarang berubah seperti mau mencabut kehidupan. WA dari temanku mewartakan banjir bandang, tanah longsor. Jembatan putus. Duh.
Aku melihat atap rumahku. Bersiap-siap dengan segala peralatan menampung air hujan. Ember-ember kudekatkan. Irama air hujan bergantian, “Tiktoktiktok!” Semakin lama semakin ramai suaranya. Hujan tak mau bersahabat denganku. Ia marah kepaada yang tak bisa merawat kehidupan ini.
Deru air kudengar. Aku yakin tanggul air itu tak akan mampu menampung gemuruh hujan senja ini. Hujan pemberi kesejukan berubah menjadi monster yang mengintai kehidupan. Teriakan tetangga sebelah rumah terdengar amat memilukan. “Duh Hyang Widhi tempat suciku digerus longsor. Kenapa harus terjadi seperti ini? Ratuuuuuuuuu! Hyang Widhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tolonglah kami. Kami selalu memujamu. Kenapa tempat suci kami digerus?” Aku hanya bisa mengelus dada. Beginilah kemarahan alam tak ada yang bisa meredakannya. Ia berubah menjadi Durga yang mengerikan melebur segalanya.
Aku ingat cerita tetua dulu bahwa di hulu sana ada alas kekeran (hutan suci). Siapa pun tak berani mengusiknya. Masyarakat desa mempercayai jika mengusik alas itu akan terjadi sesuatu. Apa ini kutukan darinya?
“Itu di sana ada alas kekeran,” kata tetuaku.
“Alas itu dijaga oleh seekor ular naga. Tak ada yang berani memasukinya hingga hijau. Di pinggirnya tumbuh beragam bambu seperti benteng pertahanan. Sederas apa pun hujan, tak akan terjadi sesuatu. Tapi kau lihat sekarang ini, telah rata. Tak ada lagi alas kekeran yang mejadi penyangga air hujan. Lihat juga sumber-sumber mata air mengecil saat kemarau. Jangan menyalahkan alam. Alam kasih kepada kita. Kita yang tak mengasihi alam. Kita ini tamu. Bukan pemilik alam ini. Syukur diberikan kesempatan mendiaminya. Tapi itulah, mengasihi saja tak bisa apalagi mau merawatnya. Sudahlah kita terima saja bencana ini.”
Aku tersenyum tipis. Alas kekeran yang menjadi pelindung desa kami hanya tinggal kenangan saja. Ia tumbuh bersama beragam mitos di dalamnya. Mitos yang kudengar bahwa seorang laki-laki dengan janji tidak menikah selamanya dianugerahi menjaga alas itu. Aku sempat bertanya dari mana asal-usul laki-laki itu. Satu pun tak ada jawaban yang pasti. Ada yang mengatakan bahwa orang tuanya tak mengakuinya karena ibunya berganti-ganti pasangan. Ada yang mengatakan bahwa laki-laki dari negeri asing lantas bersedia mempertaruhkan dirinya demi alas kekeran itu. Ia bertapa dan berubah menjadi pelindung alas kekeran itu. Itulah mitos, selama diyakini akan selalu hidup di hati pendukungnya.
Semenjak beredar isu bahwa di alas kekeran itu ada harta karun, ramailah para bromocorah memperebutkannya. Beragam caranya. Mulai dari mengiming-imingi para tetua sampai dengan pendekatan beragam gepok rupiah. Kekuatan rupiah membutakan hati. Mulailah dikeruk alas kekeran kami. Pohon-pohon tua satu pun tak berdiri tegak. Tanahnya diperjualbelikan. Diangkut truk entah akan dibawa ke mana. Tak ada belas kasihan kulihat. Udara semakin lama semakin memanas. Saling menyalahkan muncul. Ada yang menyalahkan Sang Pemberi Hidup. “Kenapa bencana ini datang silih berganti? Setahun lalu juga terjadi bencana? Apa yang kurang?”
Air menderu seperti desauan angin, terus memburu desa kami. Hujan sore itu tidak bersahabat. Alam benar-benar murka seperti jenuh melihat tingkah polah kepura-puraan. Ucapan menjaga alas hanya sebuah pemanis saja. Kudengar jeritan seorang ibu minta tolong.
“Tolong, tolooooooooooooong! Anak kami terbawa arus.” Perempuan itu menjerit. Warga desa menyisir tukad sampai ke hilir. Sampai petang tak juga ada beritanya. Upaya niskala dilakukan. Penghubung ruh mengatakan anak gadisnya bisa ditemukan jika dihaturkan sesajen pengulap. Digelarlah sesajen sampai beberapa hari belum juga ditemukan.
Berita berseliweran di media sosial, koran tak pernah berhenti mewartakan banjir yang menimpa desa kami. Desa yang dulunya dikenal bersahabat dengan alam, sekarang ini seperti menjauhi semesta.
“Bencana banjir tak pernah berhenti?”
“Ya, karena kita mengubah alas kekeran di hulu desa kita. Coba kau lihat di sana. Rata dan sudah dikapling-kapling. Ini baru segini. Nanti, bisa lebih besar lagi.”
“Semoga tak lebih parah lagi.”
“Aku juga berharap seperti itu. Tapi, kita harus jujur dengan kenyataan. Alas kekeran yang dikawal oleh ular naga itu hanya tinggal kisah saja. Kita hanya bisa bercerita pada anak-anak kita bahwa di hulu itu dulunya ada alas kekeran yang menyangga derasnya hujan. Kita sudah tak bisa merawat alas kekeran yang diwariskan oleh kawitan kita. Rupiah itu melenakan dan membutakan hati.”
Aku terus menyusuri tukad di desa kami. Gong baleganjur milik desa tiada pernah berhenti bersuara. Dengan harapan, Putu anak perempuan itu segera ditemukan, hingga menyentuh bibir pantai.
Perempuan yang kehilangan anak gadisnya itu terus menangis. “Ratu, tunjukkan di mana anak kami berada?” Ia anak satu-satunya di keluarganya itu. Ayahnya sudah pergi mendahului. Meskipun masih muda, tak mau menikah lagi. Kesetiaan lebih utama dibandingkan dengan sebuah pernikahan.
“Meme. Memeeeeeeeeeeeeeeee! Putu sudah ditemukan. Ini buktinya. Di dompetnya tertera namanya.”
Ibunya membacanya lamat-lamat matanya melihat tanggal kelahirannya. “Hari ini ulang tahunmu, Nak.”







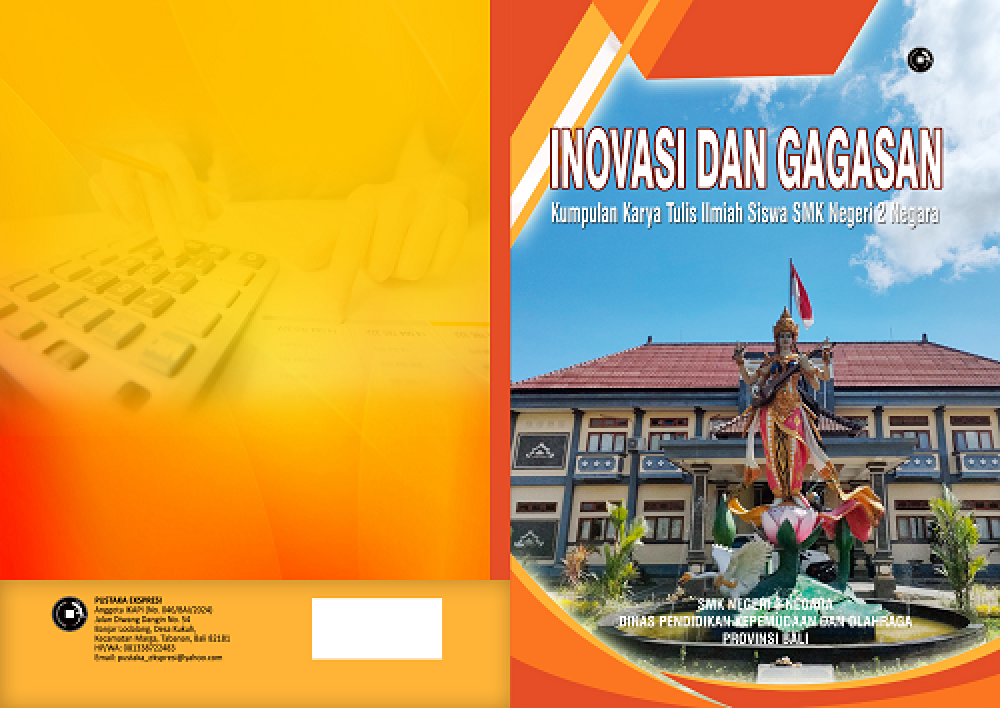
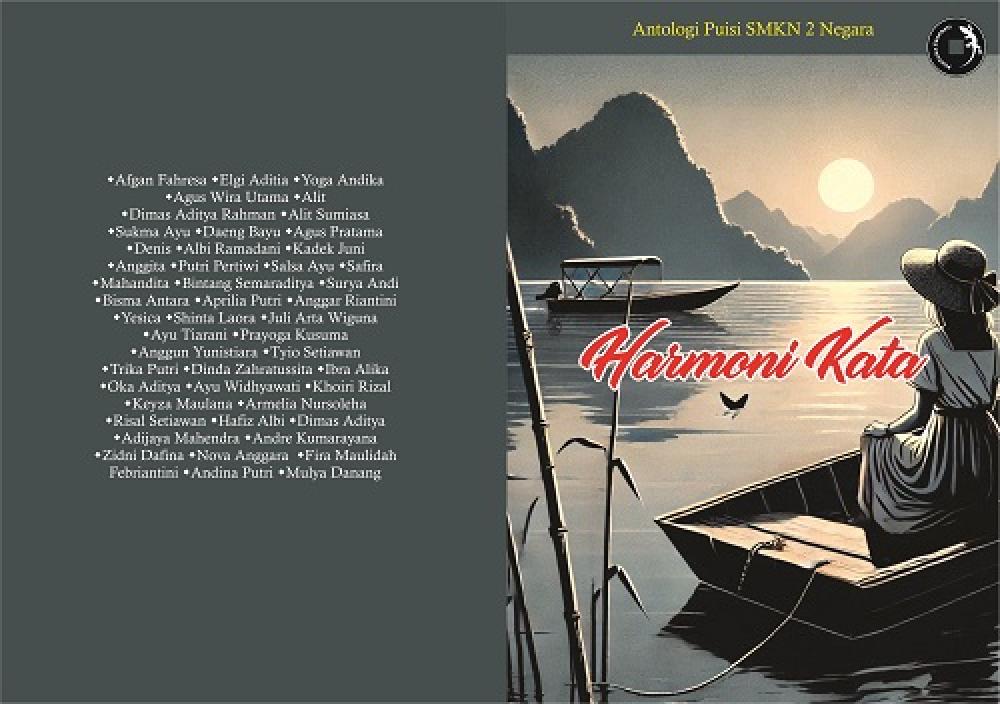



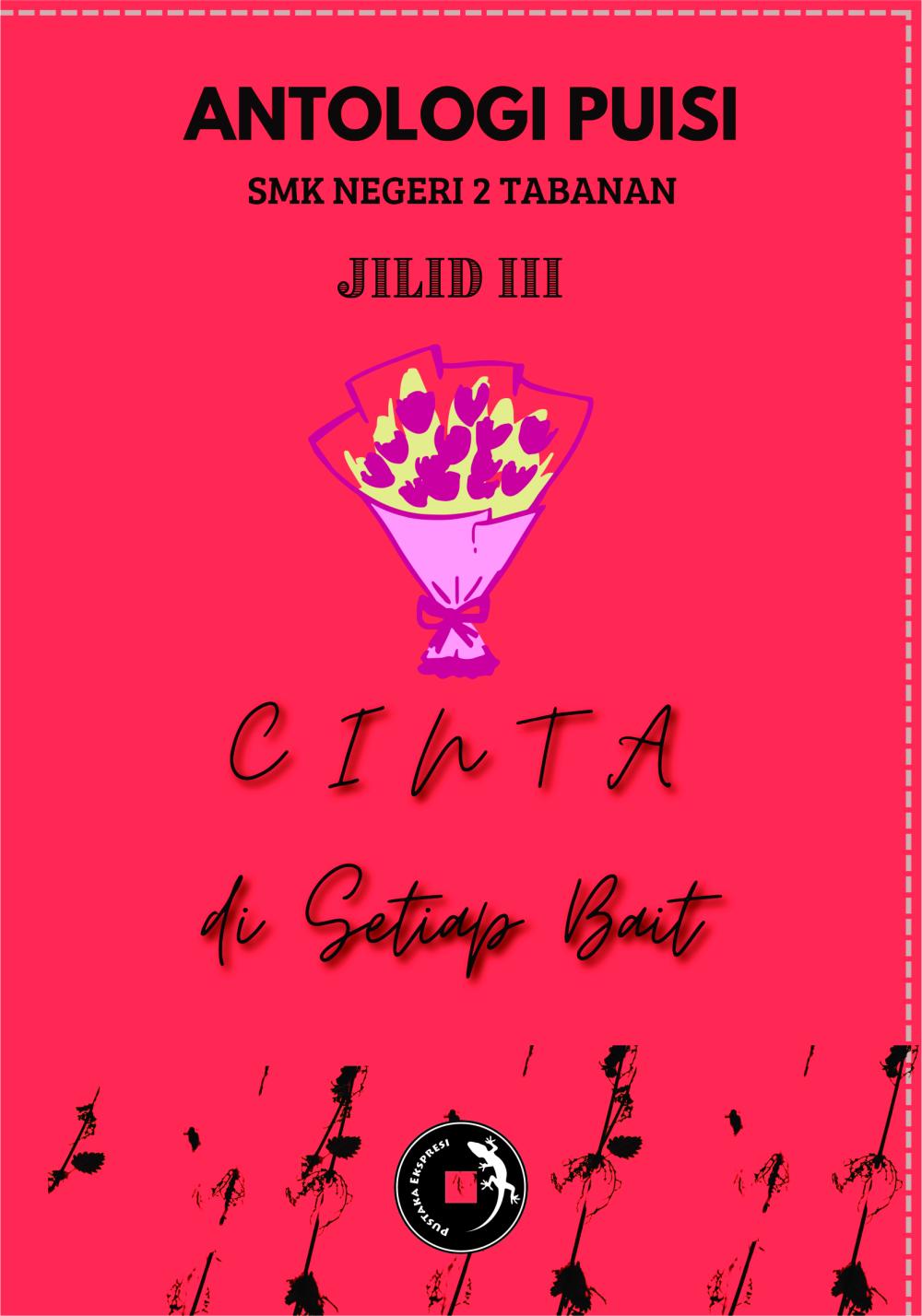



Komentar