Rembulan Setengah Lilin
By IBW Widiasa Keniten
- 30 Mei 2021

Malam ini, rembulan sepertinya kurang bersahabat denganku. Ia malu-malu menampakkan keindahannya. Awan hitam mengusap wajahnya yang rada memutih itu. Sesekali aku berharap bisa menikmati rembulan penuh seperti indahnya saat purnama raya. Tapi, entah beberapa hari ini aku melihat rembulan tak mau menjawab permintaanku. Ia semakin menjauh dan semakin menjauh menuju langit ketujuh. Aku berdoa bisakah rembulan itu kuajak bercengkerama? Akau yakin sesuatu yang musykil terjadi. Permohonan yang tak akan pernah terpenuhi, permohonan yang mengada-ada. Aku tatap setiap pergerakan rembulan. Setiap geraknya pasti akan ada kaitannya dengan kehidupanku di semesta ini. Rembulan bagian dari semesta dan aku hidup di semesta.
Aku menuju ketinggian agar bisa lebih menikmati rembulan, tapi ia justru semakin menjauh. Kapankah ia akan mau mendekat? Tentu tak akan mau mendekat, apalagi manusia sepertiku yang selalu berbangga dengan kemunafikan dan jarang menyadari bahwa diriku manusia. Hidupku berlepotan beragam warna lumpur dan beragam noda yang tak mungkin bersedekat dengan rembulan. Wajar saja ia menjauhiku. Ia teramat malu karena aku masih berbau amis. Sesuatu yang tidak diharapkan olehnya. “Majauhlah dariku,” begitulah yang kurasakan setiap aku berupaya mendekatinya. “Mandilah dulu dengan api kesadaran hingga kau terbakar menjadi debu putih.” Aku terkaget saat ia mengatakan seperti itu.
“Membakar tubuh ini?” Mana mungkin?” Aku menjadi manusia yang tidak tahu menemukan hakikat diriku sendiri. Aku tak mengenal siapa diriku ini. Dasar manusia yang berbangga dengan ketidaksadaran. Aku menjauhi rembulan malam itu. Ia seakan menyuruhku agar menjauh karena belum sesuai dengan harapannya. Sudah beberapa bulan ini aku menjauhi rembulan, biarpun orang ramai-ramai mengatakan akan ada gerhana bulan, akan ada super moon aku tak peduli.
Kunikmati perjalanan kisahku seperti sebelumnya. Kukubangkan tubuhku seperti kerbau yang berbangga berlepotan lumpur. Aku merasa lumpur itu membuatku nyaman. Bahkan aku berteriak-teriak. ”Inilah tubuhku yang berlepotan lumpur. Lihat aku semakin menikmati lumpur ini.” Aku yakin orang-orang yang melihat gelagatku akan merasakan dan mengatakan bahwa kegilaan telah bersemayan dalam jiwaku. Aku cuek saja. Toh kehidupanku adalah pilihanku. Aku juga menghargai pilihan hidupnya. Berulang-ulang aku memelototi tubuhku yang berhiaskan beragam warna lumpur, hitam, merah, putih, kuning dan beragam warnanya menyatu dalam tubuhku. Kuperlihatkan juga kepada teman-teman dekatku. Kuceritakan lumpur-limpur yang mengikat tubuh dan jiwaku.
Liukkan dedaunan menandakan bahwa kesejukan mendekati tubuhku. Aku pura-pura tak merasakan. Ia berusaha mengeringkan lumpurku. Ia berharap lumpurku semakin menebal dan mengental, mencengkeram tubuh dan jiwaku ini.
“Bangunlah sebentar dan duduklah sebentar. Tidaklah kau melihat rembulan sedang menangis? Ia teramat sayang pada tubuh dan jiwamu, tapi kau merasa menikmati kemelekatan itu.”
“Siapa rembulan? Oh tidak. Aku tak mau lagi bersemuka dengan rembulan itu. Ia sudah menjauhiku berkali-kali. Ia semakin sombong saja. Wajah ayunya tak mau ditampakkan padaku barang sebentar saja. Beragam alasan yang ia katakan. Tubuhku berlepotan lumpur. Jiwaku terlalu melekat. Pokoknya beragam alasan untuk menolak kehadiranku. Aku tak mau lagi. Biar dia menangis sendiri. Memangnya ia sendiri yang mau dipuja-puja. Oh nanti dulu.”
Suara-suara itu kudengar. Ia menertawakan kebodohanku yang menurutnya pantas ditertawakan. “Kau bukannya berusaha mencari dirimu sendiri, tapi justru semakin menjauhi dirimu sendiri. Mana mungkin bisa mendekati rembulan jika kau sendiri tak mengenal dirimu. Lantas siapa yang disuruh mengenali dirimu kalau bukan dirimu sendiri? Aku. Tak mungkin. Hanya kau. Kuliti saja itu lumpurmu. Jangan biarkan ia mengikat dirimu.”
“Hahahahaha!” Aku tertawa. Menertawakan diri sendiri. Mirip seperti orang gila yang sering kutemui di jalan raya. Ia terkadang tertawa karena kegilaannya. Berarti, aku ini juga gila? Dasar manusia tak bisa membedakan mana gila dan mana waras. Ah, aku muak dengan suara-suara itu. Aku mau menikmati duniaku.
“Itu rembulan sudah muncul. Apa kau bisa lihat?”
“Mana?”
“Ituuuuuuuuu! Ia berjalan ke sini? Itu lihat ia sudah semakin benderang. Kasihan ia kemarin sempat dicaplok Kalarau. Wajahnya kurang mulus sekarang. Ia bersedih.”
“Biarin.”
“Kok biarin? Bukankah kau ingin bersemuka dengan rembulan?”
“Habis setiap mau bersemuka ia menjauh. Mentang-mentang dipuji banyak orang sombongnya minta ampun.”
“Kau saja yang bilang begitu. Nyatanya denganku baik-baik saja. Artinya, kau senang juga melihat rembulan dilumat oleh Kalarau. Senang melihat kesedihan.”
“Bukan begitu maksudku?”
“Terus? Apa.”
“Aku cuma protes pada egonya. Ia pura-pura suci saja. Akhirnya apa, dicaplok oleh Kalarau. Hahahahaha.”
“Kau semestinya ikut bersedih karena rembulan termakan oleh sumpah Kalarau. Kalarau menepati sumpahnya. Sumpah itu mestinya ditepati bukan hanya diucapkan. Kalaurau setia dengan sumpahnya.”
“Ah, kau pintar mengalihkan pikiranku saja. Pokoknya aku tak mau lagi mendekati rembulan. Ia sudah berani mengolok-olokku dengan sebutan bau amis. Penuh kubangan lumpur. Segala tetek-bengek yang tak kupahami lagi.”
“Baiklah! Kalau begitu. Itu hakmu berbeda denganku.”
Aku tak lagi dijkejar-kejar oleh suara yang memburu hatiku. Kubiarkan ke mana kaki ini melangkah. Malam ini memang malam pekat bagiku. Aku merasakan tubuhku penuh lelehan lumpur yang menghitam. Ia melumuri seluruh tubuh ini. Ujung rambut sampai ujung kaki kurasakan seperti dikafani dengan lumpur. Kulihat di kanan-kiri penuh dengan warna pekat amat. Kucoba membuka kepingan-kepingan lumpur yang mengental dan mengering. Kubuka perlahan-lahan satu demi satu. Aku mulai membuka kepingan lumpur yang menempel di mata. Kukejap-kejapkan mataku berulang-ulang. Samar-samar kulihat rembulan muncul di dalam diri hanya setengah lilin. Ia amat samar seperti memendam kesedihan yang teramat dalam.
“Bukalah mata hatimu. Mata fisikmu terlalu sering jelalatan.”






.jpg)
.jpg)
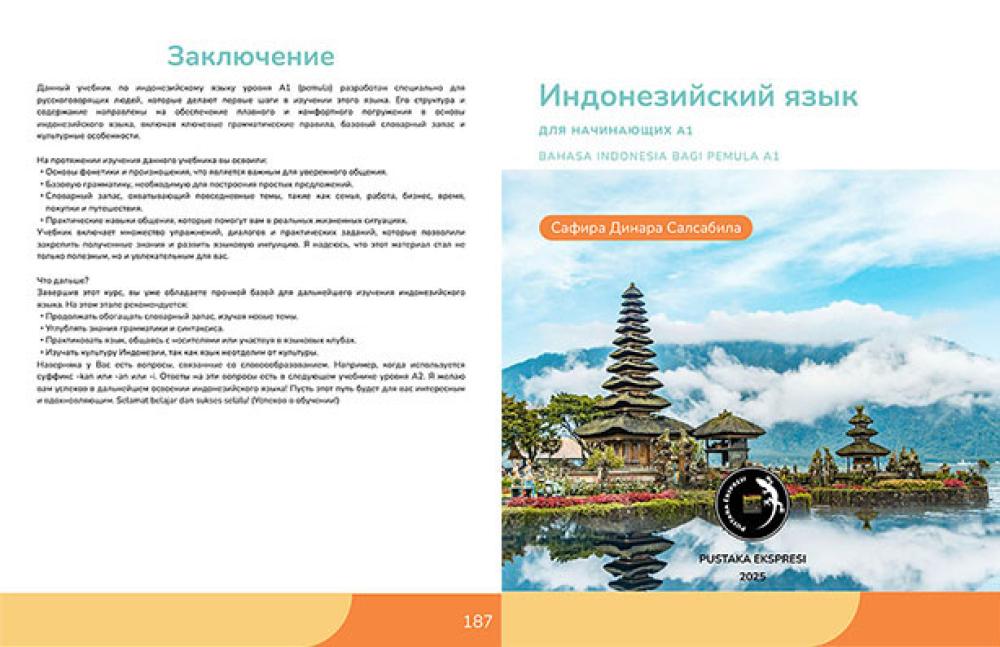
.jpg)
.jpg)

.jpg)

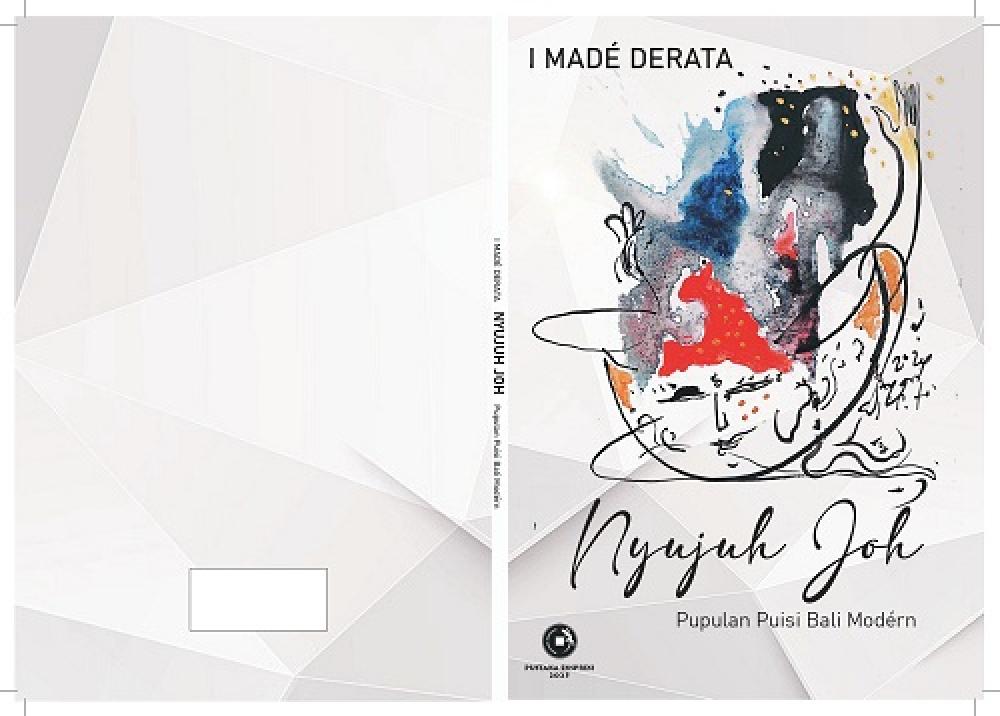
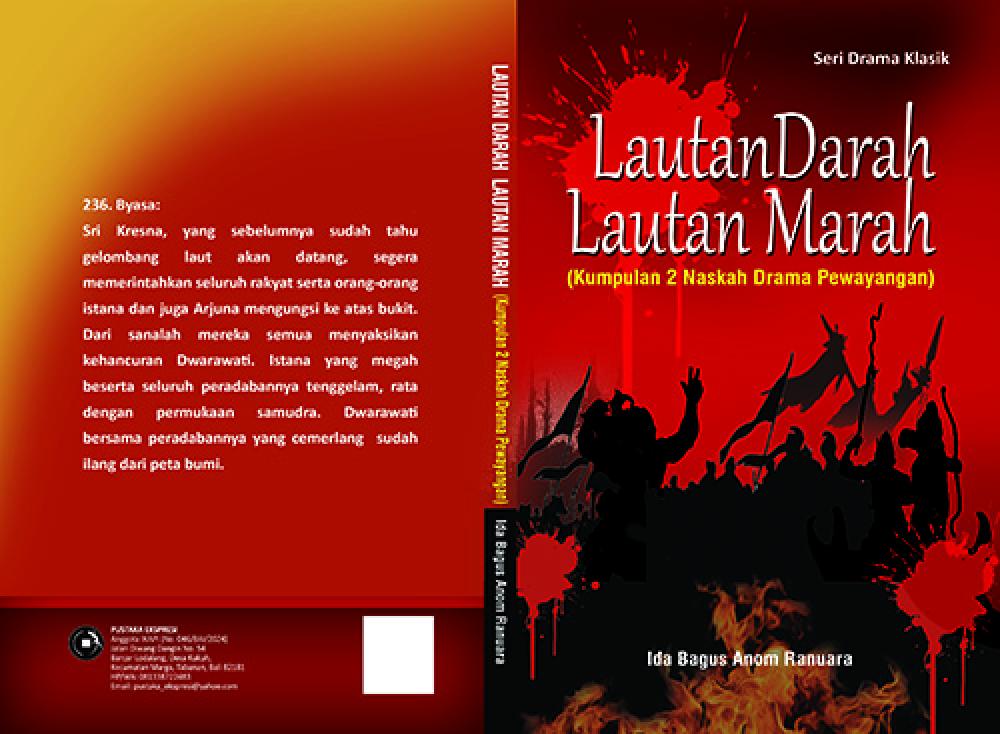


Komentar