Rembulan di Ujung Monas
By IBW Widiasa Keniten
- 02 Januari 2020

Senja luruh. Kelakson kendaraan berlomba. Beragam warna menghiasi mobil angkutan Jakarta. Kemacetan bukan barang baru bagi Jakarta. Kalau tidak macet bukan Jakarta namanya. Jalan layang tak cukup mengurai kemacetan. Berapa pun jalan dibuat selalu dipenuhi. Kelabu menghiasi langit, entahlah itu kepulan asap pabrik atau memang mendung. Sulit membedakan antara mendung dengan polusi.
Aku mematung melihat orang-orang pinggiran mulai mempersiapkan hidupnya. Gerobak mulai bergerak. Kuperhatikan seorang laki-laki paruh baya. Ia lakoni hidup dengan cinta. “Hidup mesti dirawat. Cinta anugerah Tuhan,” bisiknya. Peluhnya mulai merembes. Ia lap dengan handuk kecil yang setia menemaninya. Tak ada rasa sedih hidup di kota metropolitan. Di manapun hidup hendaknya dijalani dengan cinta karena cintalah yang mengikatkan.
Anak-anak mulai berebut mendatangi dagangannya. Senyumnya mengembang. Cerah wajahnya semakin tampak. Ucapan syukur kepada pemilik ruh tiada henti-hentinya dipanjatkannya dalam hati. “Tuhan terima kasih sudah memberi rezeki hari ini.” Tipat tahunya laris manis. Laki-laki penjual tipat tahu itu memang dikenal pintar meracik bumbu. Tipat tahu makanan anak-anak pinggiran itu penjaga hidupnya di Jakarta. Ia mengais hidup di tugu Monas. Ia tatap tugu Monas karya anak bangsa Soekarno. “Syukur masih ada tugu Monas, jika tidak, hidupku pasti sudah berakhir dilindas kota Jakarta. Jakarta memang menyilaukan, tapi juga harus siap dimenangkan. Jika tidak, siap-siaplah menjadi pecundang.”
Jualannya mulai menipis. Beberapa lembar uang kertas telah masuk di kotak di samping jualannya. Satu per satu dihitungnya. Senyumnya sumeringah. Ia teringat akan keluarganya yang mesti dihidupinya. Istrinya dan kedua anaknya yang masih membuntuhkan kasih sayang darinya. Jalan hidupnya memang panjang. Dulu, ia pernah sebagai supir angkot, pernah juga sebagai supir bajaj. Semenjak bajaj mulai dilarang beroperasi ia mengalihkan hidupnya menjadi penjual makanan keliling. Ia tak menyerah pada kehidupan. Dan untuk apa menyerah? Hidup mesti dimenangkan. Hidup bukan tempatnya untuk bersantai. Tapi, hidup untuk bekerja. Bekerja demi keluarga, anak, dan masa depan kehidupan.
Ia teringat awal-awalnya ke Jakarta. Tak ada sanak keluarga di sana. Ia lewati beberapa provinsi, Surabaya, Jawa Tengah, juga Jawa Barat demi menyelamatkan hidupnya. Ia tak tahu mengapa harus memilih Jakarta sebagai tempat menyelamatkan dirinya. Ia memang dikejar-kejar saat Gerakan 30 September 1965. Ia tinggalkan tanah Bali yang menghidupinya saat itu. Usianya saat meninggalkan Bali tidaklah terlalu muda. Kira-kira 20 tahunan. Entah kenapa orang-orang di desanya ingin menghabisi dirinya hanya karena berbeda paham? Padahal, saat itu ia hanya ikut-ikutan saja. Tidak tahu yang sebenarnya. Di desa, ia memang pekerja ulet. Ia warisi beberapa lahan tanah. Hidupnya cukup bagus dan sebagai pewaris satu-satunya di keluarganya. Entah siapa yang menyebarkan cerita bahwa ia sebagai tokoh partai terlarang? Ia pun kaget saat melihat di tembok rumahnya ada gambar palu arit. Malam itu, ia mesti mempertaruhkan hidupnya. Sorak kegembiraan beberapa orang yang mengaku sebagai tameng mengepung rumahnya. Ia intip wajah-wajah tameng itu. Ia kenal wajahnya dalam temaran rembulan. “Kenapa sepupuku ikut orang-orang itu? Ada apa ini? Apa ia ingin mewarisi tanah leluhur?” Ia tak habis pikir. Memang semenjak ramai partai di desanya, terjadi perselisihan dengan keluarganya. Tanah warisannya mau dikuasainya lagi. Padahal, sudah sama-sama diberikan bagian yang sama. Keinginan menguasai terus menggelora di hati sepupunya. Ia tak bisa terima karena bagian yang diterima sama rata.
“Bakar! Bakaaaaaaaaaaaaaaaaaar! Bunuuuuuuuuuuuuh!” Teriakan itu berulang-ulang ia dengar. Ia berlari melewati jalan setapak di bawah remang-remang rembulan. Ia terus berlari hingga nafasnya terasa hampir berhenti. “Hyang Widhi lindungi saya.” Ia menuju arah barat. Kakinya terus melangkah sepanjang hari. Ia lihat ada truk lewat. Ia setop dan mau mengajaknya sampai Gilimanuk. Ia cepat-cepat naik kapal menuju Ketapang. Selat Bali menyelematkan jiwanya. Ia duduk di dek kapal sambil memandang laut lepas. Selat Bali menjauhkan dirinya dengan tanah Bali. Hatinya terasa berat meninggalkan kenangannya di tanah Bali. Usianya yang baru dua dasa warsa harus menuju ke tanah yang baru. Ia sendiri tak tahu entah di mana akan berlabuh. Ia pun naik truk menuju kota Surabaya. Di Surabaya, ia sempat berteduh beberapa hari. Ia juga tahu, Surabaya tidak terlalu jauh dari tanah kelahirannya. Sesuatu bisa saja terjadi. Malam itu, ia putuskan menuju Jakarta. Ia tak tahu akan menjadi apa di Jakarta. Hanya satu tekadnya selamat dari kematian.
Ia berlabuh di kota Jakarta. Ia awali kehidupannya dari pasar Senen. Setiap ada yang menanyakan asal-usulnya, selalu ia katakan dari daerah lain. Walaupun ada yang mengenali dialeknya, ia tak pedulikan. Ia kerja serabutan. Ia jadi kuli pasar. Tukang gendong hasil pertanian. Tubuhya mampu menyediakan tenaga untuk mengangkut dan memikul barang.
“Semoga Tuhan memberikan jalan bagi hidupku,” bisiknya. Ia nikmati pekerjaan itu demi menyambung hidupnya. Ia merasakan betapa susahnya hidup tanpa sanak saudara di dekatnya. Kerinduannya kadang membuncah lebih-lebih teringat saat odalan di desanya. Suara gamelan dan wargasari terngiang di telinganya. Kenangan itu membangunkan hatinya. Tapi saat ingat dirinya, kenangan itu hanya ada di relung hatinya saja. Tahun demi tahun ia lewati hidup dalam kesendirian. Ia tak kuat hidup dalam kesendirian. Ia beranikan hatinya berbicara pada seorang gadis. Farida menjadi sandaran hatinya. Ia sadar mesti meninggalkan keyakinannya, tapi demi keselamatan tidak salahnya mengikuti keyakinan pilihan hatinya.
Hidupnya mulai berubah, bersama Farida. Ia nikmati indahya hidup berumah tangga. Setiap istrinya ingin menanyakan asal-usulnya selalu saja dialihkan. “Tak perlu bagimu mengenal asal-usulku. Kesetiaan itulah tanah kelahiranku.”
Istrinya tersenyum. Ia yakin suaminya menyayangi dirinya. “Tugas kita merawat anak-anak kita. Ia mesti lebih baik dari kita. Ia tidak boleh bernasib seperti anak-anak itu. Hidup di bawah jembatan layang. Orang tuanya entah di mana. Anak adalah masa depan kita.”
Pelukan dan ciuman manja mendarat di pipinya. “Ayo kita ke Monas. Pasti sudah ada yang menunggu kita di sana.”
Anak-anak di bilangan Monas memanggilnya dengan Pak Kumis. Kumisnya yang lumayan tebal menjadi ciri khasnya. Anak-anak berebut ingin menikmati tahunya. Hidupnya semakin bersinar. Ia tatap rembulan malam itu di Monas. Rembulan mendekati purnama kesepuluh. Purnama menampilkan beragam keindahan. Kembali kenangan mengusik hatinya. Purnama kesepuluh adalah odalan di desanya. Tapi, ia sudah meninggalkan purnama di desanya. Ia jalani purnama di Monas.
Ia rapikan jualannya. Ia rasakan keindahan dan kenikmatan dalam keramaian dan kebisingan kota Jakarta. Ia kembali bersama Farida. Ia perlihatkan hasil jualannya. Senyum Farida meneduhkan hati dan kelelahannya.
“Yah, besok bulan penuh, lagi pula malam Minggu. Boleh aku ikut berjualan di Monas,” pinta anaknya.
Ia tersenyum. Ia usap rambut anaknya. “Bisa saja. Asal jangan sampai di sana main saja.”
“Tidak Ayah. Aku akan bantu ayah berjualan.”
“Terima kasih.”
Purnama tiba. Ia kembali melakoni kehidupannya. Keduanya mendorong gerobaknya. Bulan mulai memperlihatkan wajahnya. Malam itu, Jakarta kelihatan lebih terang. Malam terus mendekati hidupnya dan rembulan semakin meninggi. Jualannya pun semakin laris manis. Tiba-tiba, anaknya berteriak. “Ayaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Bulan ada di ujung Monas. Aku mau memetik rembulan itu. Aku harus bisa memetik rembulan itu akan kusumpangkan di hatiku. Aku ingin menjadi rembulan yang memberi sinar pada dunia.”
Anaknya memanjat tugu Monas terus meninggi dan meninggi lagi.








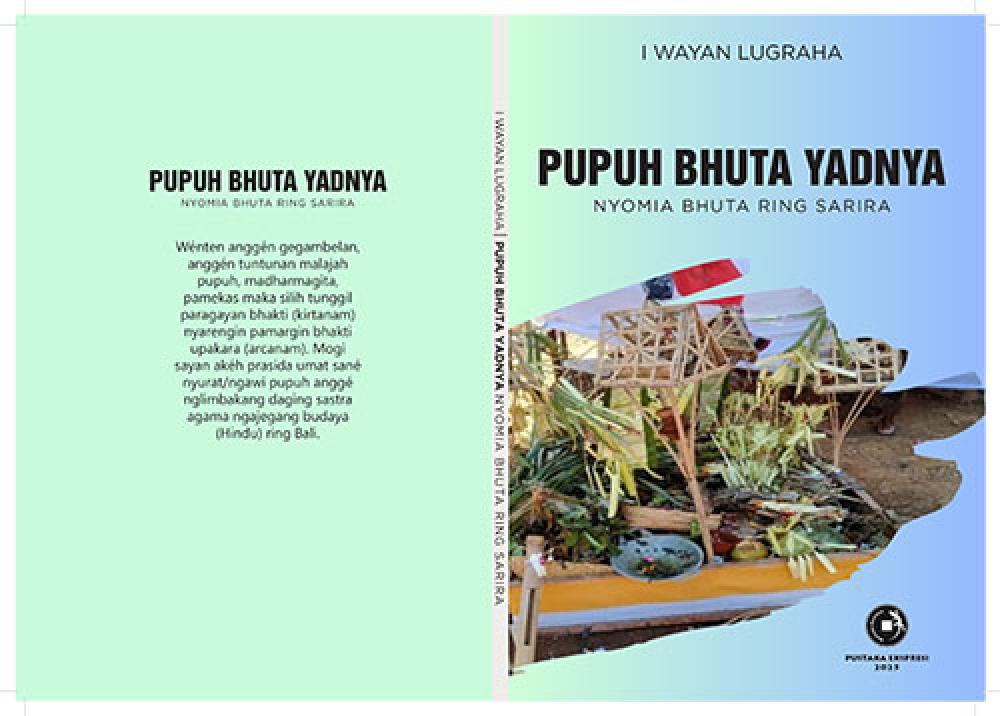


.jpg)


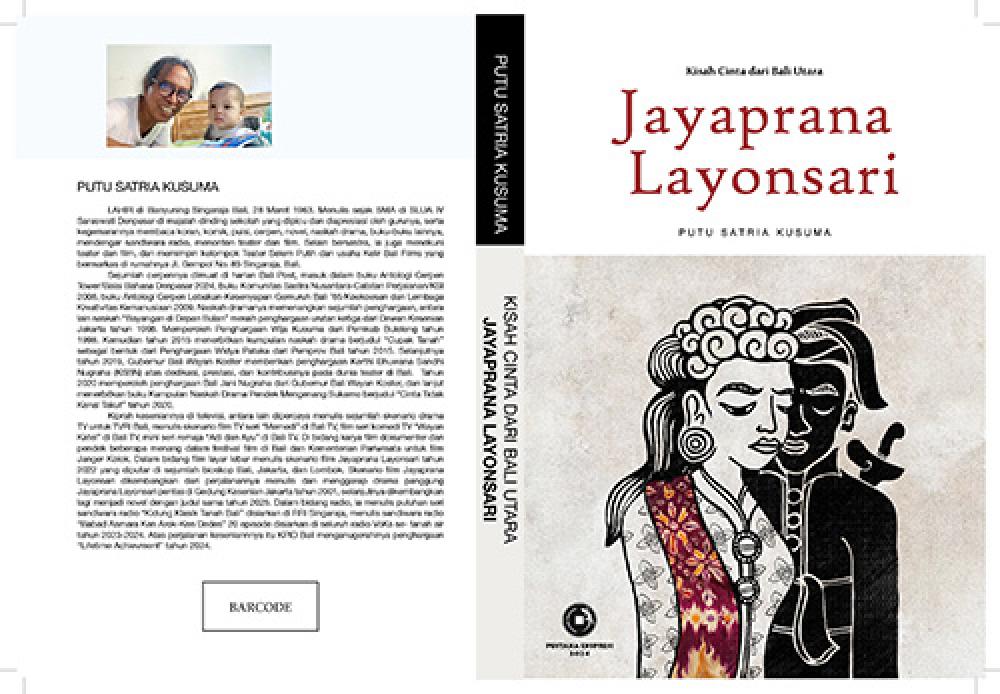


Komentar