PERTIWI
 By I NYOMAN AGUS SUDIPTA
By I NYOMAN AGUS SUDIPTA - 17 Februari 2021

Di hamparan bebatuan pantai Ujung. Tersapu sorot mata sayu yang memandang jauh hendak membelah tepian lautan. Di ujung timur pulau Bali, di sebelah Pura Linggayoni sebagai penyatuan purusa dan pradana. Muaranya dari konsep nyegara-gunung. Ketika itu, sinar mentari mulai menari di atas liukan ombak yang saling berkejaran. Jauh terlihat di tepi garis laut paling timur, wajah gunung Rinjani sedang dilukis dalam bentangan langit jingga. Terlihat bayangan gadis belia dirajah di atas pasir hitam yang legam, di Pantai Ujung pulau Bali.
“Ayah memberimu nama pertiwi bukan tanpa arti. Kelak, setelah engkau dewasa, maka akan engkau temukan arti dari namamu!” Pesan itu selalu diingat oleh Pertiwi. Pesan yang diucapkan Ayahnya ketika melepas kepergian Pertiwi mengejar mimpi. Pergi ke tempat yang jauh dari kampung halamannya. Kampung yang ikut membesarkan Pertiwi. Kampung kecil yang telah membaluri hidup pertiwi dengan berjuta pengalaman dan kebahagiaan. Bagaimana tidak, di kampung itu Pertiwi meruwat dirinya hingga tumbuh seperti sekarang ini. Kampung tempat melukis kenangan dan keceriaan bersama teman-temannya. Bermain, belajar dan menghabiskan waktu. Di kampung itulah Pertiwi hidup dan menetap bersama keluarga kecilnya. Keluarga yang hidup penuh kesederhanaan. Pertiwi tinggal di kampung tua bernama kampung Sindhu di Lombok. Walaupun terhimpit diantara tembok kokoh yang bernama Gria. Ayah dan Ibunya adalah parekan sayang di Gria. Tempat tinggal keluarga Pertiwi merupakan tanah milik keluarga Gria. Tetapi Panglingsir Gria memberikan dengan cuma-cuma tanah itu. Atas kebaikan keluarga Gria, maka Pertiwi dan keluarganya memiliki tempat berteduh. Pertiwi memang dibesarkan di lingkungan Gria, sehingga Pertiwi tahu tentang tata krama. Pertiwi juga dididik dan diruwat hampir sama dengan para Dayu. Hal ini terlihat dari aura yang ditampilkan Pertiwi berbeda dengan gadis Sudra lainnya. Jiwa keberanian, tegas, disiplin dan bertanggung jawab memang ditanamkan dalam diri Pertiwi. Etika berbicara juga diajarkan kepada Pertiwi. Begitu Pertiwi tamat SMA, maka Pertiwi dengan tegas menjatuhkan pilihannya untuk kuliah ke tempat lain. Tempat yang jauh. Tempat yang dibatasi oleh lautan. Tempat asing yang tidak pernah dikunjunginya, namun menurut cerita orang-orang di kampungnya, tempat itu adalah tanah leluhur hampir semua orang yang ada di kampungnya. Bahkan para keluarga Gria juga semua berasal dari tempat itu.
Pertiwi menginjakkan kakinya di tanah Bali. Tanah leluhur stana dari para Dewa. Tanah kedamaian. Surga yang terakhir, begitu para penikmat surga dunia mengatakan. Memang ada aura dan vibrasi luar biasa ketika Pertiwi baru menginjakkan kakinya pertama kali di Bali, tepatnya di pelabuhan Padang Bai. Pertiwi merasa seakan tanah Bali tidak asing lagi baginya. Pertiwi merasakan dirinya pernah hidup di tanah Bali. Entah, mungkin punarbhawa yang dulu. Namun udaranya, alamnya, langitnya yang biru dan tanah tempatnya berpijak, terasa menyambutnya dengan ramah.
Sambil menunggu jemputan, Pertiwi duduk santai di pinggir pantai setelah keluar dari pelabuhan. Pertiwi akan dijemput oleh keluarga Gria yang tinggal di Bali yang berasal dari desa Sidemen. Memang keluarga Gria yang ada di kampung leluhurnya berasal dari desa Sidemen Karangasem. Keluarga Gria itu berasal dari Gria Sindhu di Sidemen. Beberapa menit kemudian sebuah mobil sedan berhenti di parkiran pelabuhan. Dari dalam mobil itu keluar seorang lelaki tampan memakai kacamata hitam. Lelaki itu melayangkan pandangannya ke seluruh isi parkiran, seperti mencari sesuatu. Lalu dikeluarkan handphone-nya untuk menelpun. Benar sekali, ternyata dari kejauhan terlihat Pertiwi melambaikan tangan kepadanya.
“Ratu..., ampurayang tityang puniki (Ratu, maafkan saya ini).” Sambil berlari kecil Pertiwi menghampiri pemuda itu.
“Ohh.. kamu yang bernama Pertiwi seperti yang diceritakan Kakiang lewat telpun.” Sepintas pemuda itu memperhatikan Pertiwi yang menghampirinya. Sorot mata tajam di balik kaca mata hitam.
“Inggih nika Ratu, ampurayang tityang sampun ngarepotin Ratu (Ya Ratu, maafkan saya telah merepotkan Ratu).”
“Tidak kenapa. Lebih baik kita berbicara memakai bahasa Indonesia agar tidak terlalu kaku dan terlihat adanya sekat di antara kita.” Dengan suara tegas dan berwibawa, pemuda itu mengingatkan Pertiwi.
“Inggih nika, ooh.. ya Ratu.” Karena sudah terbiasa bergaul dengan para Dayu dan Ida Bagus, maka Pertiwi tidak merasa sulit untuk berkomunikasi dengan keluarga Gria.
Mereka akhirnya masuk ke mobil sedan dan meluncur menuju Jimbaran Badung, tempat nanti Pertiwi akan tinggal. Di dalam mobil, pemuda itu memperkenalkan diri bernama Ida Bagus Dharma Sindhu dari Gria Sindhu desa Sidemen. Dia masih kuliah semester enam Program Studi Antropologi Budaya di Universitas Udayana (Unud). Pertiwi juga akan kuliah di Unud mengambil Program Studi Ilmu Hukum sesuai dengan cita-citanya yang ingin menjadi pengacara. Entah apa yang membuat dirinya tertarik dan ingin belajar tentang hukum. Bahkan dirinya juga tertarik ingin mempelajari hukum Adat Bali.
Kurang dari dua jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah megah. Rumah itu milik keluarga Gria. Di sanalah nanti Pertiwi akan tinggal dengan beberapa mahasiswa lainnya yang berasal dari Karangasem. Mahasiswa itu kebanyakan dari keluarga Gria, walaupun juga ada beberapa dari kalangan Sudra yang masih ada hubungan dengan Gria. Sampai di rumah itu, Pertiwi menuju kamar tempatnya merebahkan lelah. Hari itu tampak seisi rumah sepi. Kata Ida Bagus Dharma Sindhu, para mahasiswa di sana sedang libur semesteran, jadinya mereka pada pulang kampung. Sambil menaruh tas dan merapikan beberapa pakaian yang dibawanya, Pertiwi memberanikan diri bertanya.
“Desa Sidemen itu di mana ya Ratu?”
“Ooo... desa itu berada di wilayah timur pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Karangasem, di sebelah selatan dari gunung Agung dan Pura Besakih. Kamu pernah sembahyang ke Pura Besakih?”
“Saya belum pernah kesana Ratu. Ini baru pertama kali saya menginjakkan kaki di Bali.”
“Ya, nanti saat ada upacara Ida Bhatara Turun Kabeh, aku akan mengajakmu sembahyang ke Pura Besakih, bagaimana kamu mau ikut?”
“Ya pasti mau Ratu, saya sangat ingin ke sana dan kalau boleh saya juga ingin ke desa Sidemen.” Dengan penuh semangat Pertiwi mengutarakan keinginannya. Ida Bagus Dharma Sindhu tersenyum melihat semangat Pertiwi, lalu dia pergi untuk membeli beberapa makanan persiapan makan malam nanti.
***
Di awal semesteran, Pertiwi berkenalan dengan semua penghuni rumah. Pertiwi mulai akrab dengan seluruh penghuni rumah, bahkan dengan keluarga Gria, Pertiwi dengan cepat beradaptasi. Mereka sering ngobrol dan menceritakan pengalaman waktu mereka kecil. Pertiwi yang tinggal di Lombok sering ditanya, seperti apa daerah itu yang bila dilihat dari peta hanya dipisahkan oleh lautan yang bernama Selat Lombok. Mereka pun berencana saat liburan semesteran akan jalan-jalan ke Lombok. Namun sebelum ke Lombok, Pertiwi meminta kepada teman-temanya untuk diajak ke pura Besakih dan ke desa Sidemen.
Janji tersebut akhirnya ditepati juga. Pertiwi dan beberapa temannya sembahyang bersama ke Pura Besakih. Setelah itu mereka berencana langsung ke desa Sidemen dan menginap di sana. Pagi buta mereka berkemas dan sudah bersiap untuk berangkat. Banten juga sudah dipersiapkan. Ketika Sang Surya mulai tersenyum di ufuk timur, mereka sudah sampai di Pura Besakih. Udara sejuk membelai kulit Pertiwi yang putih dan bersih. Suara daun cemara yang bergesekan ditiup angin terdengar bersenandung seperti menyanyikan lagu selamat datang. Pertiwi sangat takjub melihat pemandangan di Pura Besakih yang sangat megah dan indah. Di depan pintu masuk ke area Pura Penataran Agung Besakih terlihat wajah Gunung Agung yang begitu agung dan kokoh. Inilah hulunya pulau Bali. Di sinilah tempat bertemunya yang lokal dan global dalam wajah pariwisata. Dengan pasti Pertiwi melangkahkan kakinya menuju Mandala Utama Pura Besakih. Di depan Padma Tiga, Pertiwi sembahyang dengan khusuk. Setelah selesai sembahyang, Jro Mangku memercikkan tirtha. Pada percikan pertama yang mengenai kepala Pertiwi, seakan-akan Pertiwi dibangunkan dari sebuah mimpi. Pertiwi seperti melihat bayangan masa lalu hidupnya. Semua itu segera ditampiknya dengan raupan tirtha yang diminum dan dibasuhkan ke mukanya.
Pertiwi dan teman-temannya bersiap-siap akan menuju desa Sidemen. Ida Bagus Dharma Sindhu mengajak semua temannya nanti menginap di Gria. Kurang dari satu jam perjalan, mereka sudah sampai di desa Sidemen. Pemandangan di desa itu masih asri. Hamparan sawah dan perbukitan saling berpelukan. Jalan-jalan yang berliku menambah indah pemandangan yang ada. Mobil yang mereka tumpangi parkir di depan rumah yang temboknya menjulang tinggi terbuat dari batu bata merah. Itulah Gria Sindhu, rumah dari Ida Bagus Dharma Sindhu. Begitu menginjakkan kaki turun dari mobil, Pertiwi merasakan hawa dingin memeluk kakinya. Percikan tirtha yang tadi dipercikkan oleh Jro Mangku di Pura Besakih seakan kembali dirasakannya. Desa ini, tempat ini seperti tidak asing dalam hidupnya. Begitu Pertiwi memalingkan wajahnya menuju ke sebuah tempat yang jaraknya tiga rumah dari tempatnya berdiri, seperti ada yang memanggilnya. Sebuah suasana yang terasa akrab. Di tempat itu tumbuh sebuah pohon beringin besar. Di samping pohon itu terlihat dasar bangunan yang dulu pernah dihuni, tapi sekarang hanya terlihat dasarnya saja. Semuanya sudah hancur. Hanya batu-batu perigi sebagai dasar lantai saja yang terlihat. Melihat Pertiwi yang bengong sambil berdiri dan bergeming, Ida Bagus Dharma Sindhu menghampirinya.
“Hai… kenapa bengong di sini.” Ditariknya tangan Pertiwi dan diajaknya untuk masuk ke dalam Gria yang megah dan mewah itu. Begitu sampai di jaba tengah Gria, Pertiwi bertanya pada Ida Bagus Dharma Sindhu.
“Tempat yang tadi di depannya ditumbuhi pohon beringin dulunya tempat apa Ratu?”
Sambil memandang Pertiwi, Ida Bagus Dharma Sindhu berusaha menjelaskan. “Oo.. tempat itu dulunya rumah salah satu parekan di Gria ini. Tetapi sepasang suami istri yang hidup di sana mati dibakar oleh massa saat terjadi pemberontakan tahun 1965. Namun menurut cerita Ajik, anaknya yang masih kecil diselamatkan oleh Kakiang dibawa pergi ke Lombok.”
“Di mana sekarang anak kecil yang diselamatkan itu Ratu.”
“Entahlah, Atu tidak tahu keberadaannya.” Pertiwi hanya terdiam dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Malamnya Pertiwi tidak bisa tidur. Bayangan masa lalu singgah dipikirannya lagi. Banyak pertanyaan melintas yang mungkin hanya bisa dijawab oleh ayah dan ibunya yang ada di Lombok.
Paginya, Pertiwi dan teman-temanya diajak jalan-jalan mengelilingi desa Sidemen. Mereka jalan-jalan sampai di desa Tabola. Pemandangan hamparan sawah dan bukit menyejukkan mata. Pertiwi berjalan menelusuri pematang sawah yang di sampingnya ada saluran irigasi Subak. Tiba-tiba Pertiwi bertemu sosok laki-laki tua dengan pengikat kepala putih dan berjenggot putih panjang. Tatapan laki-laki tua itu tidak pernah lepas memperhatikan gerak-gerik Pertiwi. Di pinggang laki-laki itu terselip sebuah sabit yang terlihat tajam. Hal ini membuat Pertiwi ketakutan dan bergegas kembali berkumpul dengan teman-temannya. Pertiwi lalu bertanya dengan Ida Bagus Dharma Sindhu.
“Mohon maaf Ratu, siapakah laki-laki tua yang terus berdiri di samping saluran irigasi itu?”
“Oh..itu namanya Mangku Soma. Dia merupakan Pekaseh di sini.”
“Tiang takut melihat sorot matanya yang tajam, dari tadi dia terus memelototi tyang.”
“Tidak usah takut, memang dari dulu Mangku Soma seperti itu, terlihat bengis. Sudahlah jangan itu dipikirkan mari kita pulang.”
Pertiwi dengan teman-temannya bergegas pulang. Sorot mata Mangku Soma tidak pernah lepas memandangi Pertiwi. Seakan-akan dia mengenal Pertiwi. Entah di mana dan kapan. Mungkin dalam kisah punarbhawa yang silam. Atau mungkin wajah Pertiwi yang tidak asing bagi Mangku Soma. Entahlah.
Sudah hampir satu pekan mereka berlibur di desa Sidemen. Semenjak bertemu dengan Mangku Soma, Pertiwi merasakan dirinya terancam. Hal ini pula yang mungkin dirasakan oleh kedua orangtua Pertiwi yang secara tiba-tiba menelpun Pertiwi dan menyatakan bahwa besok akan ke Bali. Ida Bagus Dharma Sindhu menjemput orangtuanya di Pelabuhan Padang Bai bersamanya. Mereka lalu bergegas menuju desa Sidemen, karena teman-temannya masih liburan di sana. Mendengar bahwa mereka akan menuju desa Sidemen, ada perasaan berontak dan takut dalam hati ayahnya. Dirinya belum siap kembali ke desa itu. Namun karena keadaan, dilawannya perasaan yang muncul dalam hatinya. Begitu sampai di desa Sidemen, ayahnya seperti membuka sebuah lembaran sejarah yang usang. Tiba di depan Gria, sorot mata ayahnya tertuju pada sebuah tempat yang ditumbuhi pohon beringin. Tempat yang menyimpan kenangan dan akarnya masih kuat tertancap dalam pikiran. Pertiwi menghampiri ayahnya yang terdiam memandangi tempat yang juga menurutnya menyimpan kenangan dan pertanyaan.
“Mengapa Ayah juga memandang tempat itu dengan penuh kenangan yang membekas? Siapa yang memiliki tempat itu? Ada apa dengan tempat itu?” Ayahnya terdiam tidak menjawab, tetapi sorot matanya tidak pernah padam memandangi tempat itu. Pertiwi masih penasaran karena ayahnya tidak menjawab pertanyaannya. Diabaikannya pertanyaannya tersebut, karena tidak ingin membebani pikiran ayahnya.
“Mari Ayah, kita masuk ke Gria, di sana keluarga Ida Bagus Dharma Sindhu sudah menunggu.” Tanpa bicara sepatah kata ayahnya mengikuti perintah anaknya yang diikuti oleh istrinya. Di dalam Gria terjadi perbincangan yang sangat hangat dan akrab. Ayahnya disambut dengan penuh kegembiraan dan rasa kekeluargaan. Maklum keluarga di Gria Sindhu sudah tahu siapa ayahnya, karena ketika mereka ke Lombok, pasti ayahnya yang melayani keluarga Ida Bagus Dharma Sindhu dengan penuh pengabdian.
Malam itu, Pertiwi ingin tidur bersama kedua orangtuanya dalam satu kamar. Banyak kisah dan perasaan yang ingin dituangkan dan diluapkan bersama. Namun, begitu mereka berada dalam satu kamar, terlihat ada beban berat di wajah ayahnya. Padahal Pertiwi ingin sekali bercerita banyak tentang kisahnya ketika pertama kali tiba di Bali. Disimpannya semua kisah yang ingin diceritakannya, karena dia melihat suasana batin ayahnya yang memendam sesuatu. Benar saja, ternyata ayahnya yang memulai bercerita. Dengan suara yang agak berat, ayahnya mulai bicara.
“Mungkin ini waktunya Ayah menceritakan semuanya kepadamu Pertiwi.”
“Apa yang ingin Ayah bicarakan pada Pertiwi?” Seakan ada rasa penasaran di wajah Pertiwi.
“Kisah tentang keluarga kita, kisah tentang leluhur kita, kisah tentang tanah pertiwi kita.”
Pertiwi terdiam dan memandangi ayahnya yang mencoba membuka lembaran sejarah yang usang itu. Sorot mata ayahnya jauh menerobos waktu masa lalu. Ayahnya mulai bercerita tentang kisah tahun 1965. Bahwa leluhur mereka berasal dari desa yang sekarang mereka kunjungi. Sebuah desa yang membangun tanda tanya dari awal Pertiwi sampai di Bali. Desa yang terasa tidak asing untuk Pertiwi. Ayahnya menceritakan bahwa, dulu ketika masih berumur delapan tahun dirinya diselamatkan dan dilarikan ke Lombok oleh Kakiangnya Ida Bagus Dharma Sindhu yang menjadi Panglingsir di Gria Sindhu. Ayahnya yang waktu itu belum tahu apa-apa hanya bisa menyaksikan rumah tempat tinggalnya dibakar oleh massa. Tempat yang ada di sebelah Gria di depannya tumbuh pohon beringin besar, itulah tanah leluhur mereka. Kakek dan neneknya yang sedang tidur lelap juga terbakar di sana. Terdengar berita bahwa keluarga kakek dan neneknya disebut ikut partai yang berlambangkan palu dan arit. Padahal, kakeknya hanya bekerja sebagai petani di sawah dan tidak pernah tahu apa yang dimaksud dengan partai. Kakeknya hanya tahu kapan sawahnya perlu air, kapan dipupuk dan kapan dipanen, hanya itu saja. Waktu itu kakeknya pernah cekcok dengan Pekaseh masalah pembagian air. Permusuhan itu lumayan panjang. Menurut cerita, Pekaseh itu memang dari dulu benci dengan kakeknya yang disebut telah merebut wanita pujaannya yaitu neneknya. Memang, neneknya cantik dan di pipi kanannya berisi tahi lalat yang semakin membuat manis. Tahi lalat itu persis dengan yang dimiliki Pertiwi, sehingga ayahnya menamainya sama dengan nama neneknya. Dendam inilah yang menjadi dasar kebencian itu. Bahkan karena dendam dan kebencian itu pula yang menyebabkan Pekaseh itu memfitnah kakeknya sebagai antek-antek komunis. Maklum Pekaseh itu orang berpengaruh dan juga menjadi Jro Mangku di Pura Ulunsuwi. Di sinilah sentimen dan dendam pribadi dijalankan. Kakek dan Nenek Pertiwi menjadi korban. Kalau tidak ada Kakiangnya Ida Bagus Dharma Sindhu yang menyelamatkan ayahnya dan membawanya ke Lombok, mungkin ayahnya tidak pernah ada sampai sekarang.
“Ayah mohon maaf Pertiwi, karena menyembunyikan semua itu. Keluarga Gria yang sangat baik telah membantu Ayah dan mengetahui semua tentang kejadian itu.” Pertiwi terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Tanpa disadari ada bulir bening menetes membasahi pipinya.
“Mengapa Ayah tidak mengadakan perlawanan sekarang dengan mengambil kembali tanah pertiwi milik ayah dan mengembalikan nama baik leluhur kita?” Dengan nada yang seakan tidak terima dengan kejadian itu, Pertiwi terlihat emosi.
“Ayah belum mampu. Ayah masih lemah. Ayah memerlukan bantuan dari pihak keluarga Gria yang memang tahu kebenaran tersebut. Keluarga kita tidak salah, keluarga kita bukan komunis.” Sambil dipeluknya Pertiwi. Dalam dekapan hangat ayahnya Pertiwi menangis terisak. Batinnya berontak, namun ayahnya memeluknya semakin erat dan hangat. Begitu juga ibunya sambil mengelus kepala Pertiwi. Malam menenggelamkan kepedihan batin mereka yang semakin larut.
Keesokan harinya, ayahnya jalan-jalan sendiri menikmati udara pagi yang sejuk dan berusaha mengenang kembali masa kecilnya dulu yang terampas. Langkahnya pelan menelusuri desa yang di sebelah baratnya terbentang lukisan alam dengan panorama persawahan dan bukit. Ayahnya masih ingat saat terakhir kali menelusuri pematang sawah itu. Tiba-tiba dilihatnya sesosok laki-laki tua yang sedang sibuk membersihkan saluran irigasi Subak. Orang itu tidak asing dalam pikiran ayahnya.
“Orang ini ternyata masih hidup.” Sambil menghela nafas hendak didatangi orang itu dan ingin dibunuhnya. Tetapi goncangan dalam dirinya dilawan dengan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Di jaba Gria, Ayah Pertiwi duduk sejenak sambil mengatur nafasnya. Dari kejauhan Pertiwi melihat ayahnya duduk sendiri sambil termenung. Pertiwi menghampiri ayahnya sambil membawakan segelas kopi pahit kesukaan ayahnya.
“Ini Ayah, tyang bawakan kopi pahit kesukaan Ayah. Kopi di sini pasti rasanya berbeda karena ini merupakan kopi asli hasil panen warga di sini.” Melihat kopi itu, ayahnya teringat kebiasaan Kakek Pertiwi menyeruput kopi pahit yang masih hangat buatan istrinya. Terlihat mata ayahnya berkaca-kaca. Dipeluknya Pertiwi dengan erat tanpa berbicara apa-apa. Pertiwi merasa heran melihat tingkah ayahnya seperti itu.
Setelah merasa tenang, ayahnya berkata, “Harus Ayah selesaikan semua permasalahan ini. Sekaranglah waktunya semua kisah masa lalu diluruskan.” Sambil menghela nafas ayahnya mulai meminum kopi yang dibuat Pertiwi. Memang aroma dan rasa kopi itu tidak pernah berbeda dari dulu, tetap sama. Lalu ayahnya meninggalkan tempat itu untuk bertemu dan membicarakan hal penting dengan keluarga Gria.
Beberapa hari kemudian terdengar kabar Mangku Soma hanyut di saluran irigasi. Matanya yang selalu melotot tajam hilang bersama derasnya aliran air irigasi. Tanah yang ditumbuhi pohon beringin tempat dulu leluhurnya Pertiwi tinggal telah kembali menjadi milik ayahnya berkat bantuan dan perjuangan dari keluarga Gria. Pandangan tentang keluarga Pertiwi di masyarakat sudah mulai diluruskan, karena semua itu adalah rekayasa dari Mangku Soma. Matinya Mangku Soma disebutkan akibat karmaphalanya yang dulu. Pertiwi merasa sangat senang, karena tanah pertiwi leluhurnya telah kembali. Lalu Ida Bagus Dharma Sindhu datang menghampiri Pertiwi dan berbisik.
“Atu lakukan semua ini demi kamu Pertiwi. Kamu telah mengisi kekosongan hati Atu. Begitu juga tentang Mangku Soma, sudah Atu bereskan. Atu mendengar semua pembicaraan ayahmu.” Pertiwi terkejut dan terdiam mendengar bisikan lembut Ida Bagus Dharma Sindhu. Pertiwi tidak mengira Ida Bagus Dharma Sindhu sampai sejauh itu bertindak demi dirinya dan keluarganya. Peristiwa itu terus diingat Pertiwi. Sosok Ida Bagus Darma Sindhu telah menancapkan rasa dihatinya. Namun, mungkinkah parekan seperti dirinya bisa bersanding dengan Ida Bagus Darma Sindhu. Di tepi pantai Ujung, Pertiwi berbicara pada ombak. “Gemuruh ombak apa yang sedang menghempas hatiku? Apa rasa ini bisa disatukan? Ataukah seperti Lombok dan Bali yang selamanya dipisahkan selat Bali? Perbedaan ini mampukah diterjang ombak cinta yang menderu di hati kami?”
Catatan:
Purusa : Laki-laki
Pradana : Perempuan
Nyegara-Gunung : Laut-Gunung
Gria : Rumah tinggal warna Brahmana
Dayu : Gelar untuk perempuan warna Brahmana
Kakiang : Sebutan Kakek untuk warna Brahmana
Ratu : Panggilan kehormatan untuk warna Brahmana
Banten : Sesajen
Tirtha : Air suci
Tyang : Saya
Punarbhawa : Penjelmaan / kelahiran Kembali
Panglingsir : Dituakan dan dihormati
Pekaseh : Ketua organisasi Subak
Subak : Organisasi irigasi di Bali
Karmaphala : Hukum sebab-akibat
Atu : Nama panggilan kehormatan bagi warna Brahmana






.jpg)
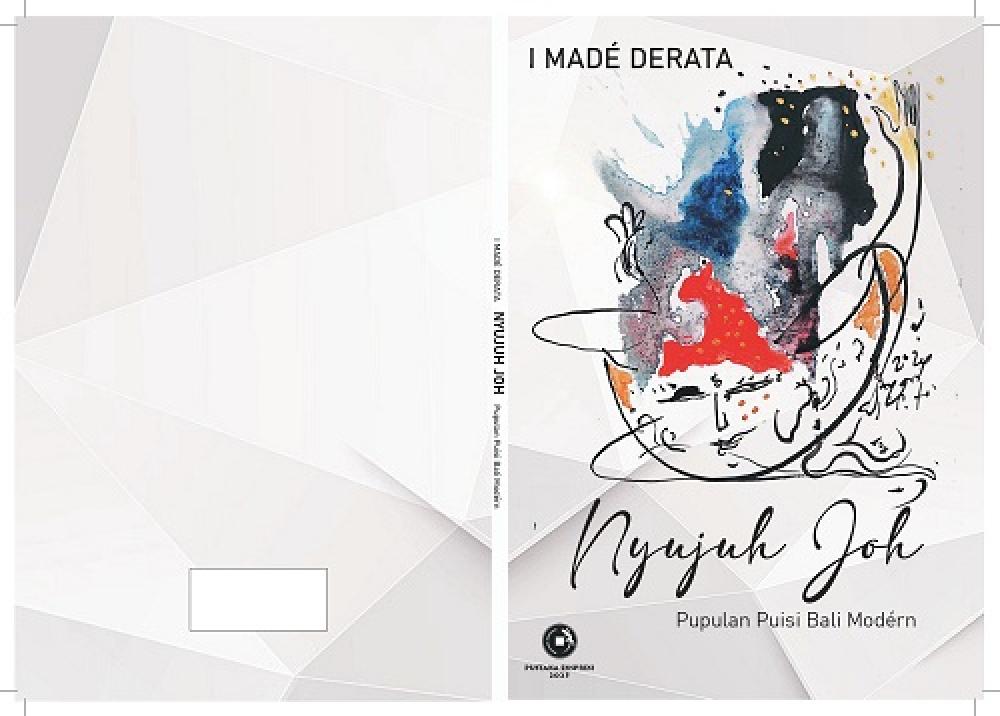

.jpg)
.jpg)
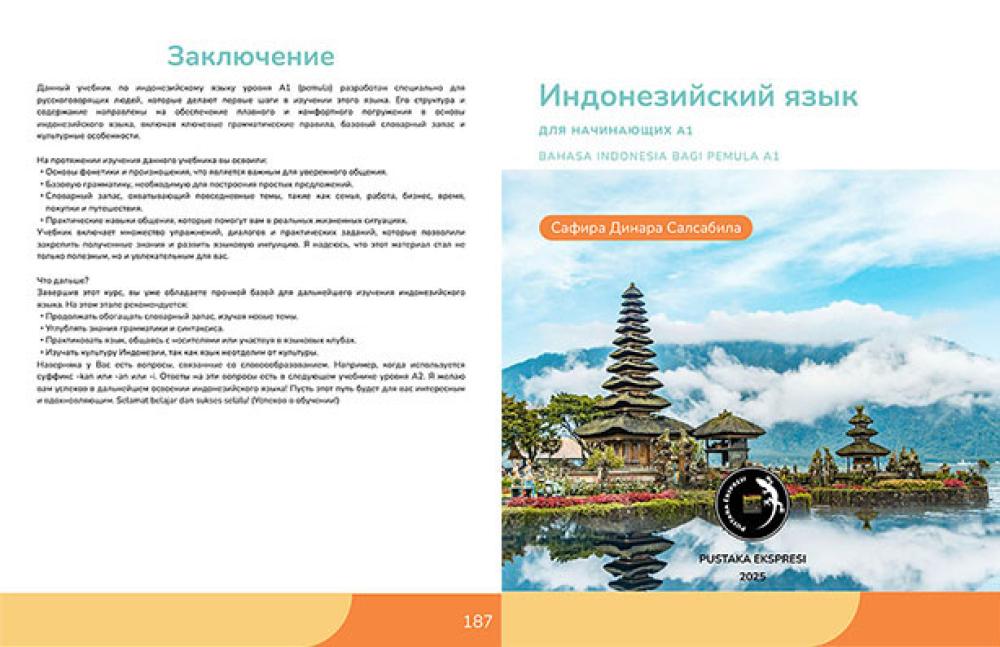
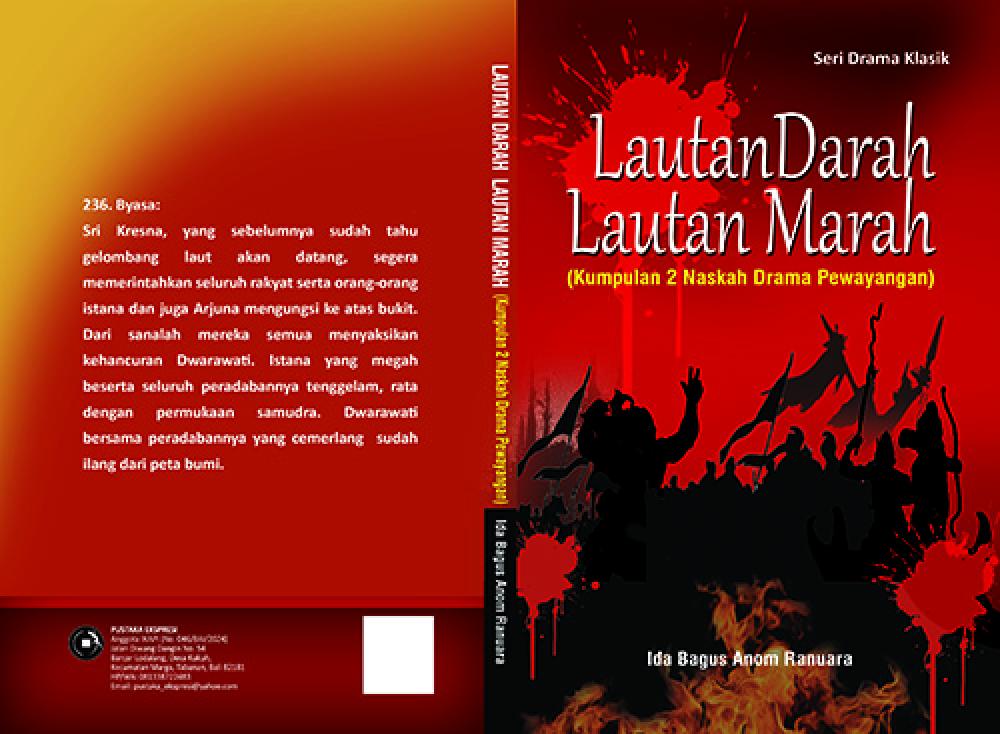
.jpg)
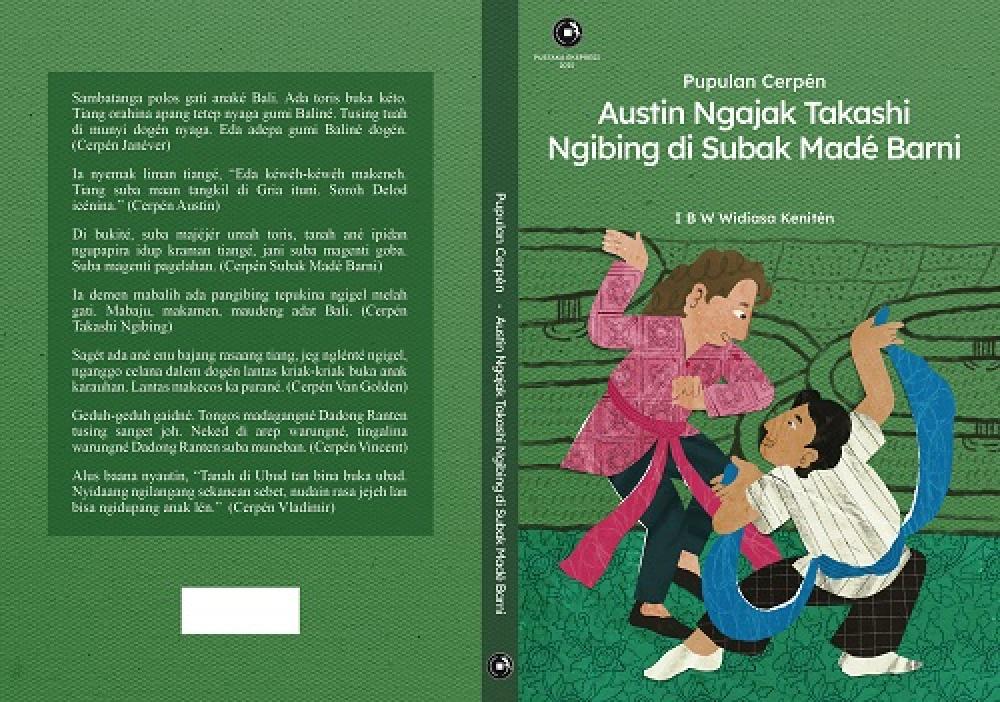



Komentar