IBU - Cerpen IBW Widiasa Keniten
By IBW Widiasa Keniten
- 22 Desember 2020

“Ibu, mendekatlah dalam hatiku akan kedendangkan sebuah lagu cinta untukmu. Ibu, tersenyumlah sepanjang waktu. Aku rindu padamu. Lihatlah aku bersimpuh di hatimu. Berikanlah aku memanggilmu sepanjang musim. Datanglah! Datanglah! Bawakan aku setangkai cinta.”
Beli Made, laki-laki pemuja lamunan itu menggoreskan isi hatinya pada selembar kertas hatinya. Ia telah diberhentikan dari tempatnya bekerja. Segala usaha telah dilakoninya demi melanjutkan hidupnya. Ia kembali ke tanah kawitannya. Ia bersahabat dengan bau lumpur. Ia belajar mendengarkan suara air di parit. Ia belajar menghirup napas bumi. Tanah yang masih diwarisinya selalu dipujanya seperti seorang laki-laki sedang jatuh cinta. Cinta pada ibu bumi.
Sawah orang tuanya digemburkannya dengan cinta. Ia siangi setiap rumput yang mengganggu tanaman hatinya. Ia taburi pupuk buatan yang dikemas dengan cinta. Ia langkahi setiap pematang sawahnya dengan kasih. “Setiap langkah adalah kemajuan, aku tak boleh menyerah pada hidup. Hidup mesti dimenangkan. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda.” Ia tatap cabai yang sudah menampakkan bunganya. “Agustus adalah sasih Karo, semoga harganya lebih baik.” Ia tahu, Agustus umumnya upacara ngaben digelar. Momen itu ia perhitungkan. Perputaran ekonomi akan terus bergerak jika yadnya tetap digelar. Hatinya bergetar setiap menatap pematang sawahnya yang telah lama ditinggalkannya. Ia merasa jauh di tanahnya sendiri.
“Apa tak ingin kembali lagi bekerja di hotel?” tanyaku saat bersemuka dengannya.
Ia tersenyum. “Sudah cukup sampai di sini. Beli ingin merawat sawah warisan ini walau tak seberapa luasnya. Beli bersyukur bisa menikmati sari bumi dari bumi kawitan. Tanah ini adalah kekasihku. Akan kurawat sepanjang ruh ini masih bersemayan.”
Aku tak berani lagi melanjutkan perbincangan. Aku kembali melihat-lihat tanamanku. Aku memang hidup dari tanah ini. Dulu, juga sempat mengadu nasib ke luar kota. Toh, aku kembali lagi. Seperti bangau, kembali ke lumpur. Sepanjang hari aku bergumul dengan bau tanah. Kesehatan tubuhku sebagai salah satu alasannya. Di samping ada tugas-tugas yang mesti kulanjutkan karena pesan dari leluhur agar jangan meninggalkan jalan kawitan.
Panas mentari tak ia perhitungkan. Tubuhnya tampak menghitam. Wajahnya tak sehalus dulu, kerut-kerut ketuaan mulai menguat. Di dangaunya, ia membuat tempat menjerang air. Terkadang, ia rebus ubi hasil panennya.
Lamat-lamat kudengar, ia memanggil. “Ke sini. Ini aku lagi merebus ubi.”
Kudatangi dangaunya. Ia tampak ceria. “Ini panen pertamaku di tanah ini.” Ia persembahkan ubi yang telah direbusnya itu. “Kita nikmati bersama.”
“Terima kasih. Tiang belum panen. Semoga minggu ini bisa panen.” Ia perlihatkan tangannya yang mulai menebal. Bibirnya tersenyum. “Tangan ini telah merasakan karunia kawitan. Akan kujaga tanah ini seperti menjaga tubuhku. Tanah ini ibuku yang menyusui hidupku.”
“Ternyata hidup berakhir di ibu bumi juga.” Ia berkata sambil menatap beberapa bangunan yang sudah mulai mengejar tanah-tanah di sebelahnya. “Tapi tanah kita juga dikepung dengan beragam keinginan.”
“Inilah perubahan. Ternyata harus ada yang dikorbankan. Beragam kepentingan ada di dalamnya. Jalur hijau saja sudah berubah fungsi. Tanahnya berubah menjadi beton-beton. Apalagi tanah kita. Tapi, sebelum rata menjadi bangunan, kita olah dan puja tanah ini.”
“Jika di hulu dibendung. Matilah kita. Air subak tak akan bisa ke tanah kita. Lihatlah di hulu sana. Para pekerja sedang meratakannya.” Ia mengelus-elus dadanya. Perih terasa di dalam. “Kudengar sebentar lagi akan ada perubahan status tanah ini. Tidak lagi sebagai persawahan. Itu jalan yang membaginya menjadikannya berubah. Padi menguning, rumput hijau tak akan bisa kita lihat lagi. Lihatlah di atas sana! Sudah habis dikapling-kapling. Lantas kita membicarakan subak. Lantas kita membicarakan budaya sawah. Ah, untuk apa?” Aku terbawa perasaan.
Ia geleng-geleng desanya telah dikepung dengan beragam kepentingan. “Jangan-jangan aku akan menjadi asing di desaku sendiri,” bisiknya. “Ah, aku tidak boleh berdiam. Akan kulawan setiap yang mau meniadakan tanah ini. Besok saat sangkepan di banjar akan kusampaikan masalah ini.”
“Gimana?” tanyaku singkat.
“Besok saat sangkepan di banjar akan kusampaikan semua ini. Ini pencaplokan secara pelan-pelan. Kita terlalu silau dengan kepingan-kepingan uang. Kita terlalu mabuk saat dipuja-puja. Nyatanya seperti ini.”
“Sudahlah tak usah dibesar-besarkan. Lama-lama juga akan menjadi biasa.”
“Tidak! Pokoknya tidak! Akan kubela tanah ini!”
Sangkepan banjar tiba, Made ikut serta. Ia memakai busana adat. Ia sengaja duduk dekat dengan kelihan banjar. Ia sampaikan unek-unek hatinya. Matanya sedikit mendelik saat ada yang mengatakan bahwa apa salahnya menjual tanahnya sendiri?
Ia merasa ada yang berubah di banjarnya. Tak lagi setia pada tanahnya. Tak lagi punya rasa memiliki. Kepentinagn sesaat lebih dirasakan baginya. “Begini saja, siapa yang setuju tanahnya dijual dan diratakan menjadi pemukiman?”
Betapa kagetnya Made, ternyata sebagian besar mengangkat tangannya. “Tiang sudah lelah dengan menjadi petani. Selama hidup, terus saja bergulat dengan tanah. Sekali waktu, apa salahnya tiang menikmati hidup?”
“Terus setelah uang habis, mau makan apa? Beton?”
Krama banjar itu saling tatap. Satupun tak ada yang berani menjawab.
Catatan
Banjar: wadah organisasi di Bali
Beli: kakak
Karo: bulan kedua kelender Bali
Kawitan: leluhur
Ngaben: upacara kematian di Bali
Kelihan: ketua banjar
Sangkepan: pertemuan
Yadnya: kurban suci dengan tulus ikhlas






.jpg)
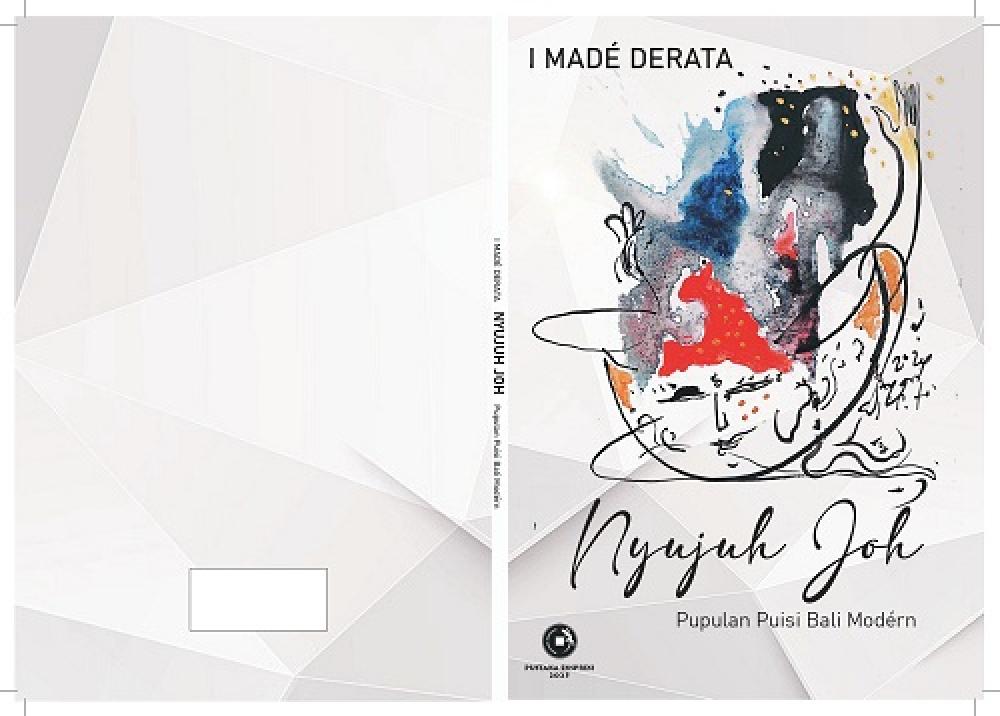

.jpg)
.jpg)
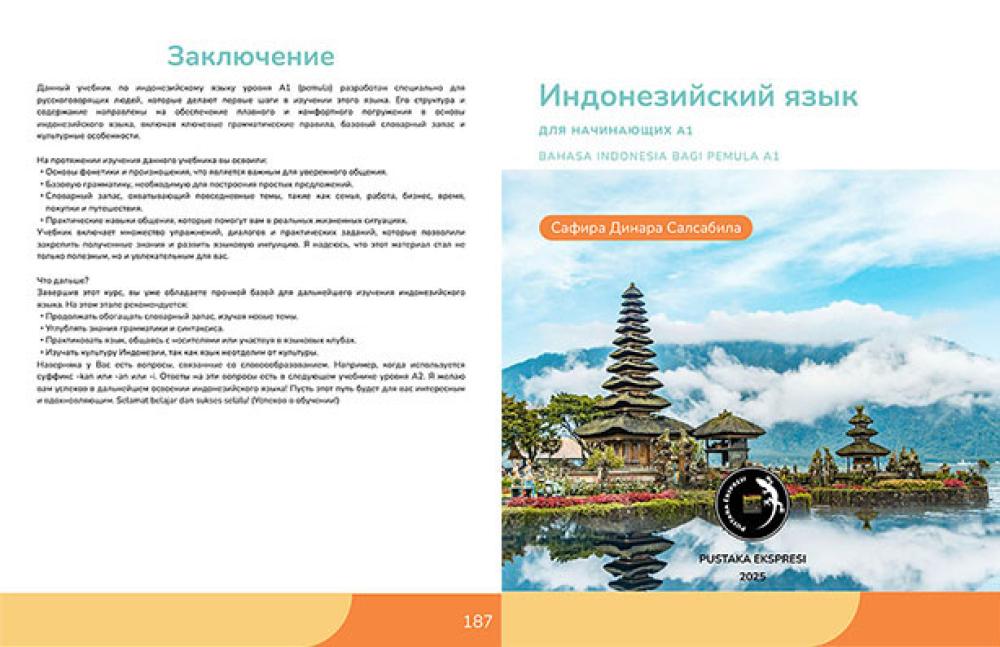
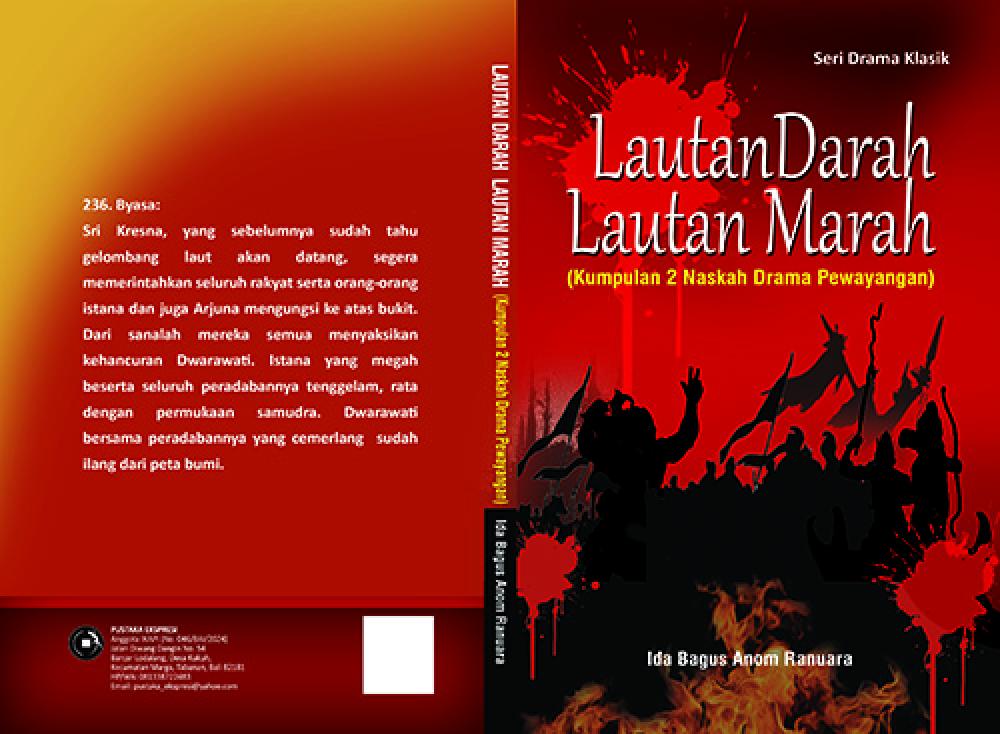
.jpg)

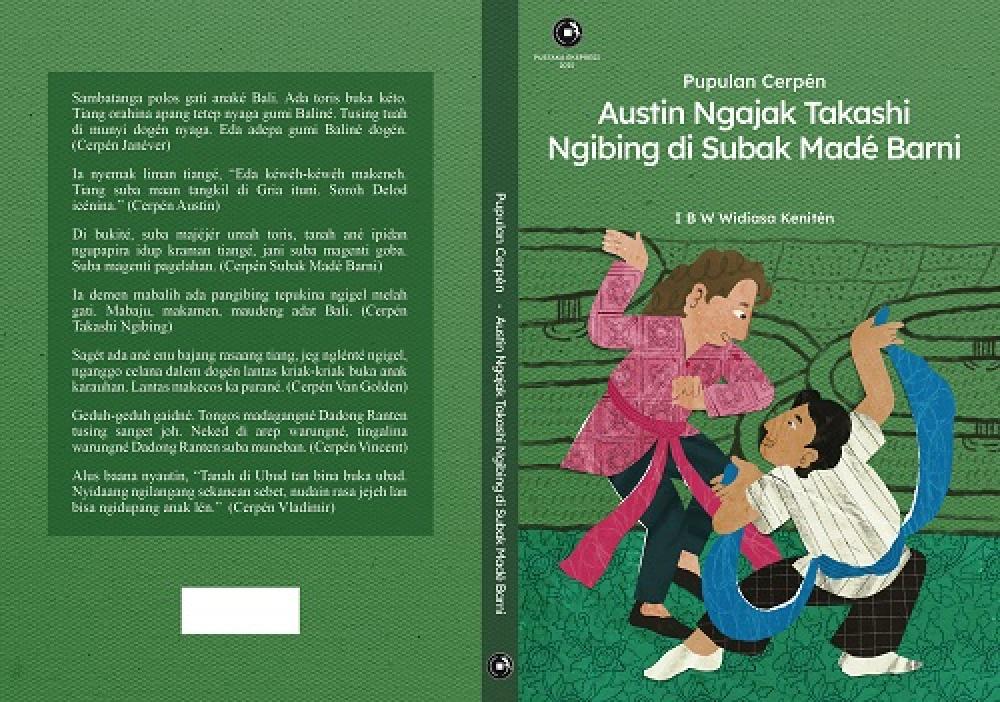


Komentar