NELAYAN KECIL
 By Agus Buchori
By Agus Buchori- 24 Juni 2020

Pukul dua belas malam saat semua anak masih di dalam pelukan ibunya, Fian sudah dibangunkan ayahnya. Ia harus bangun lebih awal karena kerambah rajungan yang ia pasang letaknya sangat jauh. Sekitar empat jam perjalanan ke tengah laut. Untuk alasan itulah ia harus bangun lebih awal agar tak kesiangan sampai di tempat tujuan.
Masih terlihat jelas sisa-sisa bangun tidur di raut mukanya. Aku menggodanya sambil berujar, "tak doakan dapat tangkapan yang banyak, ya"
Alfian hanya menjawab singkat sambil mengucek matanya, "terima kasih.."
Saat itu ia melintas bersama ayahnya di depan rumahku. Kebetulan sekali malam itu purnama, wajahnya terlihat jelas di bawah temaram cahaya bulan malam itu. Berdua mereka berjalan beriringan sambil menjinjing bekal masing masing.
Sudah menjadi kebiasaan di kampung kami ketika waktu dini hari, suasana pantai terlihat sibuk lalu lalang para nelayan yang hendak mengambil keranda rajungan setelah seharian diberi umpan kini adalah waktunya untuk mengambil tangkapan. Saat itu akan berisik suara mesin perahu yang hendak melaut. Saling berkejaran menjemput rejekinya.
Sudah setahun ini Fian diajak bapaknya melaut. Bapaknya tak ingin anaknya melanjutkan sekolah ke SMP. Bapaknya menganggap hanya dengan bisa membaca dan menulis sudah cukup untuk menjalani hidup. Melaut tak usah berijazah tinggi-tinggi cukup hanya lulus SD pun sudah mampu menjadi pelaut asal tekun dan punya nyali.
Ajakan ayahnya merupakan anugerah besar bagi Alfian. Ia yang sudah bercita-cita berhenti sekolah karena logikanya yang tak mampu lagi antusias untuk memikirkan matematika, dan aneka pelajaran berhitung lainnya. Apalagi yang berbau hafalan ia malah sangat membencinya. Melaut adalah jalan yang membuatnya bebas dari sekolah.
Kini ia harus rela dibangunkan ayahnya menjelang dini hari setiap musim air laut surut menjelang pagi. Ia harus cepat membawa perahunya menjauh dari bibir pantai jika tak ingin perahunya terdampar dan tak bisa melaut karena air keburu surut.
Alfian pun sangat menikmati aktivitasnya ini. Ia memang lebih menyukai bergumul dengan ombak dan angin malam yang dingin daripada harus berjibaku dengan pekerjaan rumah yang diberikan guru dari sekolah. Baginya menceburkan diri ke air laut adalah bermain yang mengasikkan.
Pernah suatu ketika istriku bertanya padanya, "kamu kok nggak melanjutkan sekolah, Alfian?"
"Enak melaut. nggak usah mikir pelajaran,"
"Apa kamu nggak ingin punya ijazah yang lebih tinggi lagi?"
"Aku ingin jadi nelayan saja, bekerja kan bisa jadi apa saja. Toh semua sama yaitu untuk mencari uang."
Aku kaget mendengar jawabannya. ia benar, bekerja jadi apapun, tujuannya sama: cari uang.
Setiap dini hari ia selalu melintas di depan rumahku sambil menjinjing bekal melautnya. Tak lupa ia akan selau menyapaku dengan senyumannya. "Berangkat dulu, pak," begitu selalu sapanya.
Hidup yang keras lebih disukainya. Di saat anak-anak seusianya menikmati suasana belajar di sekolah, Afian lebih menghayati kerasnya hidup di tengah lautan.
Fian memang pekerja keras. Ia tak pernah malas setiap ada kegiatan kerja bakti di kampung, ia hampir tak pernah absen. Di antara teman-teman sebayanya ia terlihat lebih dewasa. Badanya lebih sedikit kekar dan agak hitam karena sering diterpa sinar matahari.
Kedewasaan seseorang memang akan cepat terbentuk jika orang tersebut banyak menjalani kehidupan yang keras, Tingkat berpikir yang dipacu begitu tinggi membuat garis wajah seseorang menjadi lebih tegas dan dewasa penampakannya. Tak terkecuali wajah Alfian.
Di usia yang semuda itu, Fian sudah jeli membaca arah angin. Ia pun hafal tanda tanda di langit kapan angin datang dan ke mana arah untuk pulang. Ia sering menjadi pemegang kemudi perahu saat pulang. Saat itu ayahnya kan beristirahat di perahu dengan tiduran dan menyerahkan kemudi perahu untuk dikendalikan oleh alfian.
"Di tengah laut kamu seperti di dalam mangkok terbalik karena ke manapun arah mata kita memandang yang nampak adalah ufuk atau cakrawala. Yang terlihat hanyalah lautan dan langit yang saling bertemu," katanya pada Irham temanya yang saat itu penasaran tentang suasana di lautan. Alfian pun melanjutkan, "makanya kamu harus pintar membaca arah angin dan juga posisi bintang agar tak mudah tersesat."
Biasanya, Jika habis musim Angin Muson Barat biasanya banyak tangkapan rajungan dan harganya pun melambung tinggi. Inilah saat yang dinantikan para nelayan kampung kami. Tak terkecuali Fian dan ayahnya. Setelah hampir dua bulan tak melaut karena Muson, membuat hutang para nelayan menumpuk. Ketika Muson mereda saat itulah musim untuk membayar hutang dan mengumpulkan uang. Mereka akan berlomba-lomba mencari daerah tangkapan yang menjadi tempat rajungan bersarang. Meski jauh bermil-mil mereka akan tetap melakukannya demi bisa melunasi hutang.
"Uangmu kamu buat apa, Ian?" tanyaku padanya ketika aku dengar harga rajungan sedang melambung tinggi.
"Itu urusan, bapak dan ibu, saya hanya membantu dan tiap hari hanya diberi uang jajan saja.
"Uang jajanmu banyak pastinya," tanyaku kembali padanya dan ia hanya tersemyum kecil.
Bapaknya hanya melaut berdua dengan Alfian. Dengan cara demikian bapaknya tak usah berbagi pendapatan karena melaut dengan anaknya sendiri. Jika harga jual rajungan sedang melambung tinggi, sehari ia bisa mendapatkan sebanyak satu juta rupiah. Tentunya pendapatan ini akan berkurang sepertiganya jika ia melaut dengan orang lain.
Dibagi tiga adalah cara pembagian pendapatan nelayan di kampung kami. Masing-masing Sepertiga untuk, pemilik perahu, perbekalan, dan pembatunya alias belah.
Ian pun menganggap bahwa aktifitas yang dilakukannya bukanlah pekerjaan karena ia membantu orang tuanya. Dalam hal ini Alfian hanya ingin lepas dari kesibukannya bersekolah. Itu saja.
Karena sering bergumul dengan para nelayan yang lebih tua, Fian pun secara tidak langsung terpengaruh. Ia jadi sering misuh dan mulai merokok meski masih sembunyi-sembunyi.
Kehidupan yang keras di lautan telah menempa fisik dan jiwanya menjadi lebih cepat dewasa daripada umur yang sesungguhnya. Masa bermainnya telah ia isi dengan debur ombak lautan. Impiannya hanya satu, ia ingin punya perahu.






.jpg)
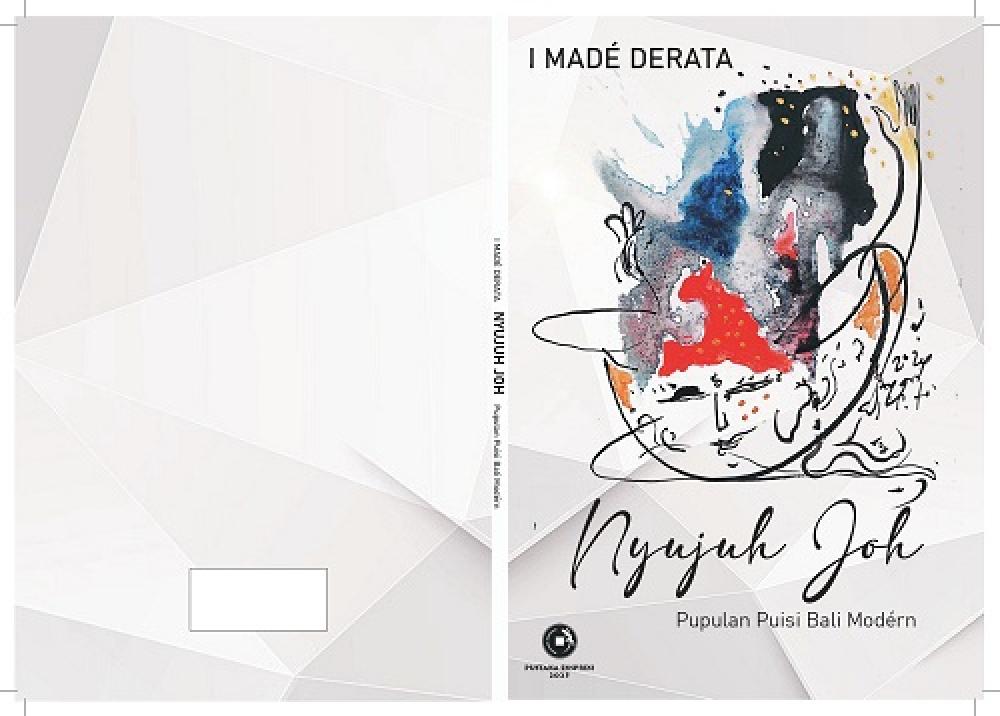

.jpg)
.jpg)
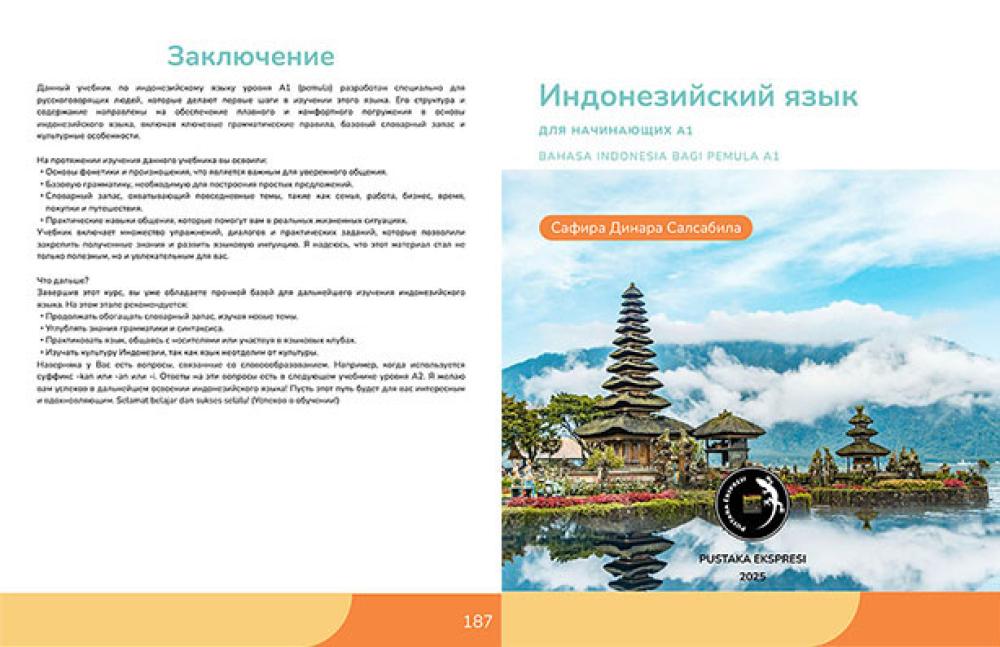
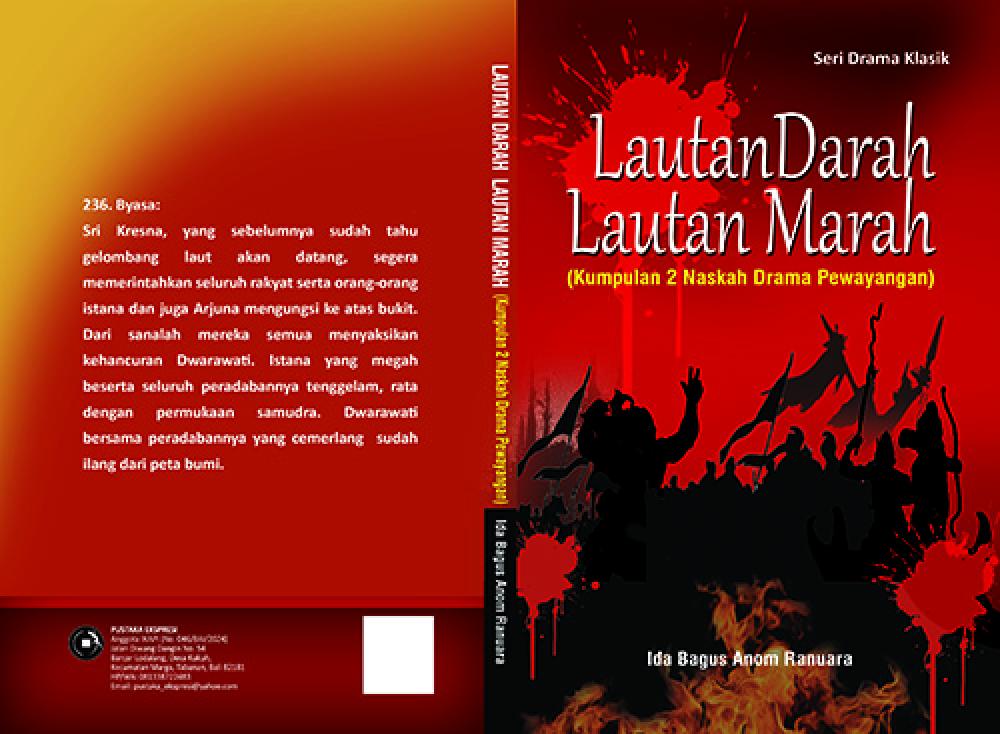
.jpg)

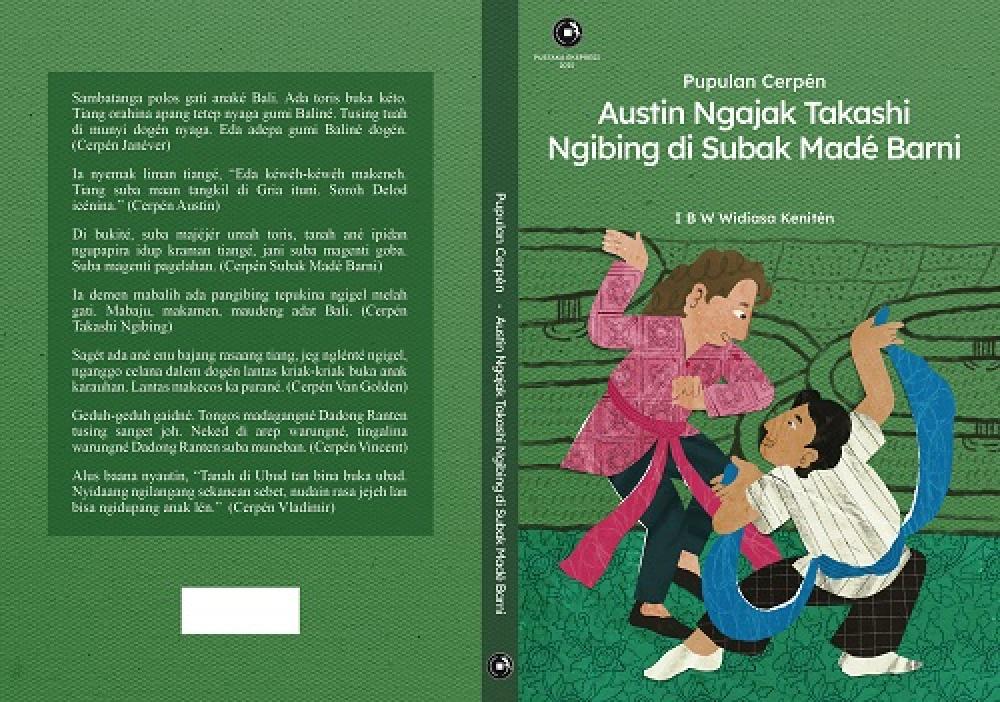


Komentar