Cinta Dalam Secangkir Kopi Pahit
By IBW Widiasa Keniten
- 08 Februari 2020

Teguk demi teguk mengaliri kerongkongan lelaki itu. Sebatang rokoknya menemani kesendiriannya. Ia isap dalam-dalam. Ia hembuskan perlahan-lahan. Beban di hatinya terasa pergi bersama kepulan-kepulan asap rokoknya. Nikotin baginya bukan barang menakutkan lagi. Ia tahu nikotin mengotori paru-parunya. Tapi, hanya itu yang bisa dilakukannya. Di sampingnya segelas kopi pahit mendampinginya. Ia teguk kopi itu setelah beberapa kali hembusan rokoknya.
Tiba-tiba, laki-laki tu mendesah pelan. “Kenapa aku harus memilih jalan sunyi?” Ia menanyai dirinya sendiri. Kulihat ia tersenyum sambil menghirup udara yang dirasakannya mendekatinya. “Sudah tak usah menyesal. Hidup tidak selalu bersama.” Ia ingat saat bersama istri tercintanya. Setiap pagi, istrinya dengan setia menyuguhkan secangkir kopi pahit. Ia lihat bayang-bayang istrinya di sana.
“Ratih. Masih kau setia padaku? Maaf kuhirup baumu dalam kopi ini. Aku tahu kau sudah damai bersama-Nya. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan selain hanya sebuah kenangan bersamamu.”
Ia ambil kopi pahitnya. Ia nikmati kopinya. Kesukaannya pada kopi pahit tak bisa ditinggalkannya. Ada kenikmatan mengalir saat ia nikmati pahitnya. Mungkin sama pahitnya dengan jalan hidupnya. Tahun demi tahun ia menyendiri. Tak ada keinginannya untuk mencari pengganti pendamping hidupnya. Hanya satu perempuan dalam hidupnya, Ratih.
Ratih, perempuan yang ia kenalnya saat menikmati indahnya pantai Amed. Ia kenal saat itu. Entah keberanian dari mana datangnya saat ia menyatakan cintanya. Ia puji kecantikan Ratih, ia sanjung-sanjung hingga ke langit ke tujuh. Di mana langit ketujuh itu? Ia sendiri tidak tahu. Ratih, perempuan itu bekerja di sebuah penginapan. Ia nyatakan cintanya tanpa tedeng aling-aling lagi. Tak ada kata menolak. Jika senja mendatangi, ia jalan-jalan ke timur pantai Amed. Ia lihat indahnya taman laut di Jemeluk. Ikan-ikan menikmati kebebasannya. Sesekali ia lemparkan batu kecil yang diinjaknya seperti melemparkan kerikil-kerikil kecil dalam hidupnya. “Matahari di sana akan menyaksikan kisah hidup kita, Ratih. Pantai Amed ini tempat kita menambatkan hidup. Percayalah pada Beli.” Keduanya memacu cinta dalam rangkaian rumah tangga. Hidup ia susuri bersama. Suka-duka ia jalani bersama hingga maut memanggil istrinya.
“Jika tiang mati nanti, silakan Beli menikah lagi. Tiang tidak marah. Apalagi ada dendam. Tidak sama sekali. Tapi, ingat jangan Beli menyakiti perempuan yang mencintai Beli.”
“Tidak ada kata berpisah buat kita. Kematian bukan perpisahan. Nanti beli juga ikut bersama Ratih.”
“Beli, biarkan tiang pergi. Tiang sudah teramat banyak meninggalkan kesetiaan tiang sebagai seorang pendamping hidup. ”
“Tidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak!” laki-laki itu tiba-tiba menjerit keras. Tetangganya mendatanginya.
“Ada apa?”
“Oh, tidak. Tumben tiang ingin berteriak seperti itu.”
Tetangga sebelahnya geleng-geleng. Ia tinggalkan laki-laki penyendiri itu. Dalam kesehariannya memang tak tampak ia memendam perasaannya. Ia lihat biasa-biasa saja. Pagi-pagi ia sudah bangun merapikan jalan hidupnya. Ia ke sanggar pemujaannya. Ia ucapkan syukur terhadap pemilik ruh. Ia tatap matahari pagi. Ia sampaikan segala isi hatinya pada mentari pagi. Ia ingin ada secercah sinar menerangi gundah hatinya. Ia berharap sinar pagi merasuk dalam hidupnya.
“Dewa Surya, tak ada yang bisa kupersembahkan. Hanya sehelai kembang yang bisa kupersembahkan. Tak ada lebihnya. Maafkan diri hamba yang banyak memohon, tapi tak pernah menghaturkan apapun pada-Mu. Berikanlah jalan terang bagi istri hamba. Ia adalah penerang hidup hamba. Walau ia telah pergi, ia tetap penerang hidup hamba.”
“Dewa Surya, tak ada yang melebihi cinta-Mu pada semesta. Kau tak pernah membeda-bedakan. Engkaulah Surya dalam hidup hamba. Engkaulah Bhaskara dalam hati hamba. Engkaulah Sawitri dalam jiwa hamba. Engkaulah Rawi dalam jalan hidup hamba. Engkau Arka dalam detak jantung hamba. Engkau Raditia dalam tarikan nafas hamba.”
Ia puja Dewa Surya dalam setiap harinya. Tak ada yang bisa mengalihkan hatinya. Ia tinggalkan tempat pemujaannya. Ia kembali ke meja duduknya yang tak pernah berubah semenjak istrinya pergi selamanya. “Tidak boleh ada yang berubah dalam hatiku. Ini sudah ditata oleh istriku. Istriku belahan jiwaku.” Ia kelihatan romantis sekali saat itu. Ia tatap foto istrinya yang terpampang di tembok rumahnya. Ia tersenyum saat melihat foto pernikahannya yang semakin tampak kusam. Ia dekati, ia bersihkan. Debu-debu yang menempel di kaca fotonya, ia lap dengan sebuah tisu.
“Foto ini bukti kita pernah bersama. Tak ada yang boleh memisahkan kita. Penyatuan jiwa ada dalam foto ini. Kita telah berjanji setia selamanya. Meninggalkan sebuah janji adalah penghianatan dalam hidup. Beli tak mau seperti itu, Ratih. Percayalah sampai detak jantung terakhir hanya Ratih di hatiku.”
Ia sengaja dekatkan foto itu di sampingnya. Sesekali ia rasakan istrinya hadir dan menyuguhkan secangkir kopi pahit. Kenikmatan mengalir saat-saat seperti itu. Ia bayangkan suguhan kopi dari istri tercintanya.
“Ini kopinya Beli. Silakan diminum. Maaf tak ada pisang goreng hari ini. Pisang kita sudah habis kemarin. Tiang lupa membelinya.”
“Tak apa-apa. Duduklah dekat sini.”
“Tumben?” Istrinya bertanya.
“Ada yang ingin beli sampaikan.”
“Pasti ada yang amat penting?”
“Tidak. Sudah beberapa tahun kita menikah sampai detik ini tak ada suara tangis bayi di rumah ini.”
Istrinya melelehkan air matanya. Ia ingat saat muda dulu pernah diangkat rahimnya. Tapi, tak pernah diceritakan sama suaminya. Kasihnya teramat dalam yang seakan-akan menghalanginya untuk menyampaikan kisah hidupnya saat remaja dulu. Rahasia itu akan tetap menjadi rahasi. Tak akan pernah ia sampaikan kepada laki-laki yang setia mendapingi hidupnya.
“Jila Beli mau menikah lagi. Silakan saja. Tiang tidak marah.”
Suaminya tersenyum. “ Bukan itu maksud Beli. Ratih adalah hidup beli selamanya. “
Ia angkat kopi pahitnya dalam tegukan terakhir. Api rokoknya semakin mengecil hingga hembusan terakhir.






.jpg)
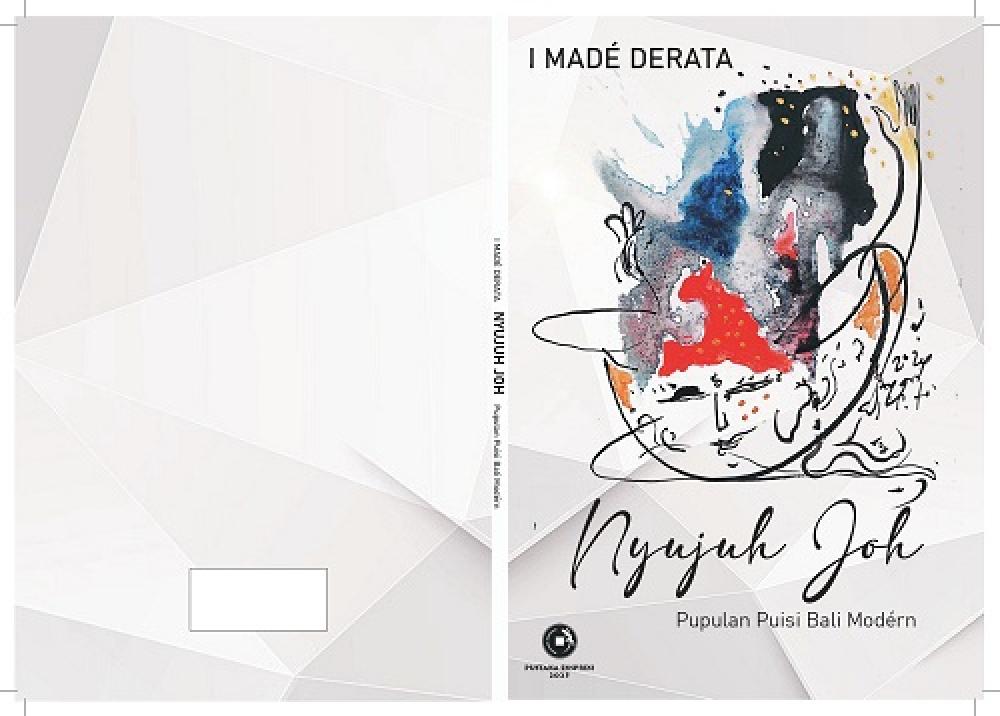

.jpg)
.jpg)
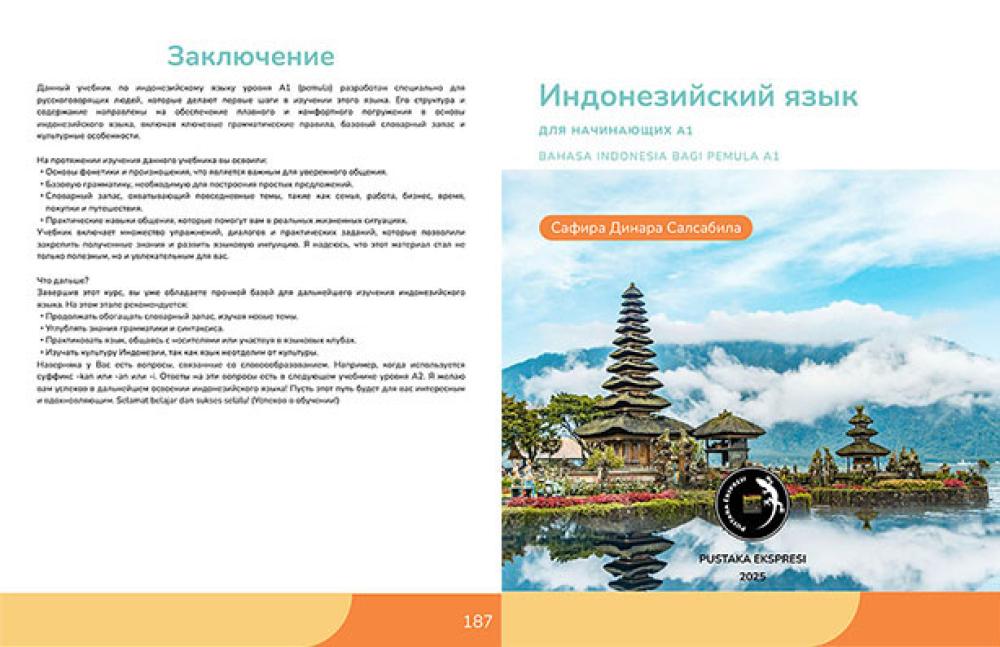
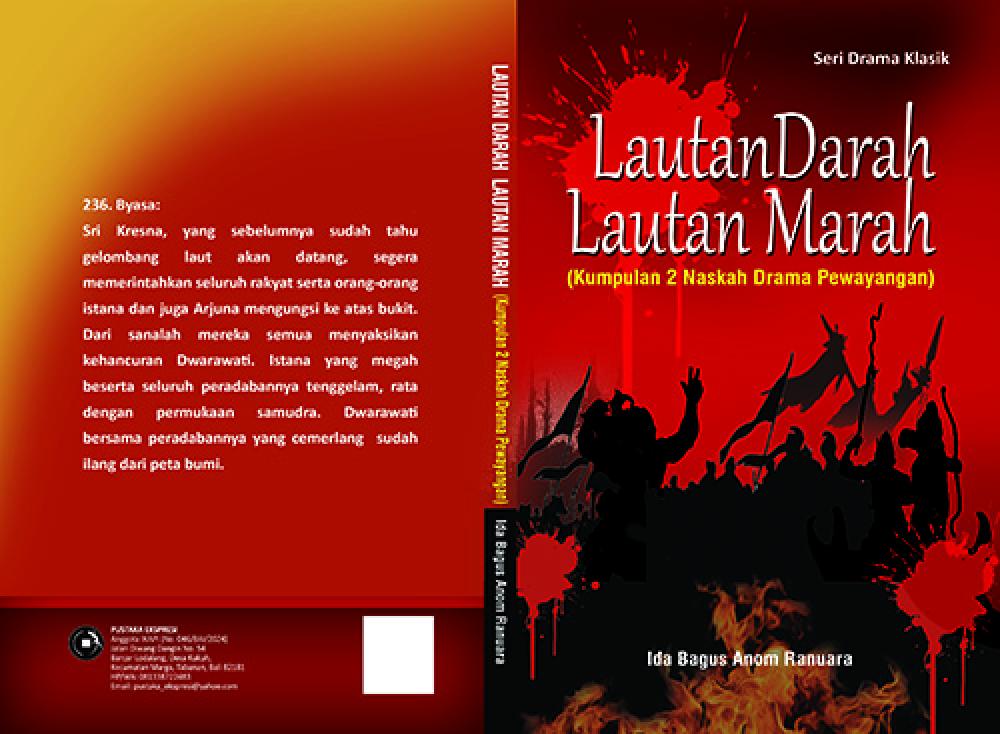
.jpg)

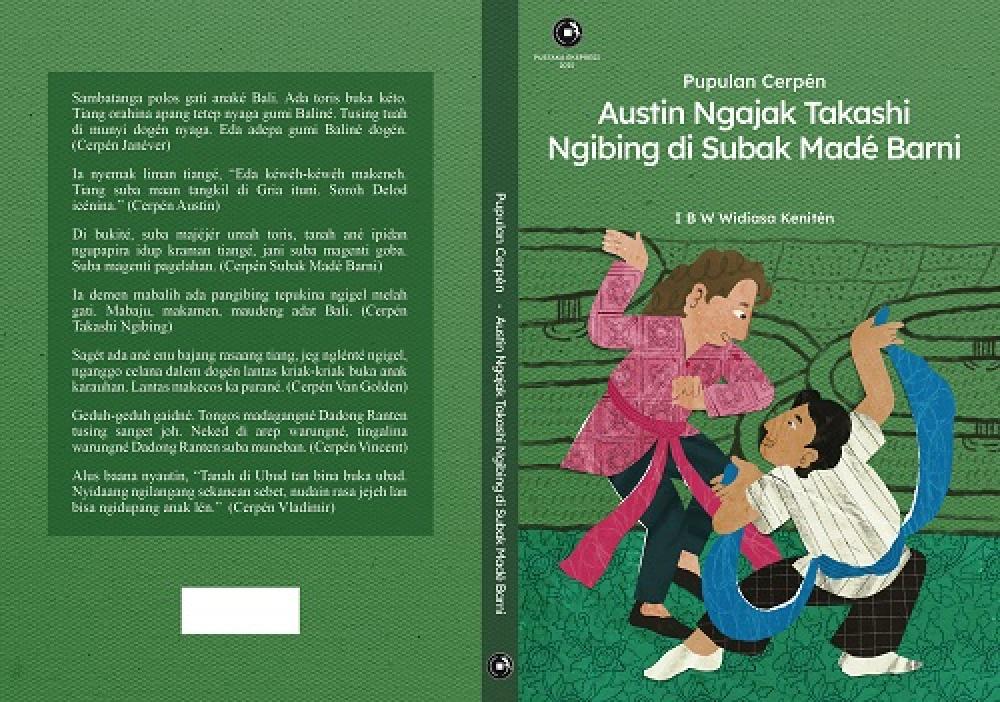


Komentar