Toko Tua
 By Geg Ary Suharsani
By Geg Ary Suharsani- 01 Februari 2020

Melewati pintu toko tua, aku berhadapan dengannya. Tangan keriput, sekeriput kelopak mata. Bola mata abu-abu, katarak menyelimuti sebagian. Seperti dua puluh tahun yang lalu, tidak ada gula-gula merah di atas mejanya. Hanya ada sempoa, pensil dan kertas yang berfungsi sebagai kwitansi.
***
Setelah merantau dua puluh tahun lebih, aku kembali ke Kota Pedagang, kota kelahiranku. Tidak ada perubahan berarti. Rumah-rumah di kota ini berjejer lurus berhadapan satu sama lain, dipisahkan oleh jalan aspal hitam yang memanjang. Jika dibayangkan, maka bentuk kota ini adalah persegi panjang, serupa bentuk biskuit coklat yang renyah dengan lelehan krim coklat di dalamnya.
Luas kota ini masih sama, tiga ribu meter kali enam puluh meter. Terdiri atas dua ratus rumah, seratus rumah di timur jalan dan seratus rumah di barat jalan. Rumah-rumah di cat dengan warna yang hampir senada. Kadang krem, kadang hijau muda, kadang biru. Terdapat pengumuman yang khusus diedarkan oleh pemerintah kota, tiap kali akan ada perubahan warna rumah. Kini, rumah-rumah itu bercat merah muda. Meskipun warna merah mudanya tidak persis sama satu sama lain, tetap terlihat romantis apalagi jika matahari akan terbenam.
Sinar matahari yang oranye kemerahan akan menimbulkan bayangan indah pohon perindang yang tumbuh di setiap halaman rumah. Pohon perindang itu besar dan berdaun rimbun. Mereka ditanam pada waktu yang bersamaan, sehingga tinggi mereka kini sama rata. Posisi tanamnya pun sama di tiap rumah: disebelah kiri pintu masuk. Mereka serupa tentara yang sedang berbaris, rapi dan lurus.
Seperti halnya rumah-rumah di pinggir jalan pada umumnya, maka seluruh rumah di Kota Pedagang dilengkapi dengan tempat usaha di sebelah kanan pintu gerbang. Tidak ada yang ingin menyia-nyiakan peluang yang bisa diperoleh dari hasil berjualan melalui tempat usaha yang terletak di pinggir jalan.
Hari ini Rabu pagi, pukul sembilan. Matahari mulai meninggi. Panas yang terik terasa di kulit. Kota Pedagang hanya hangat di pagi hari sebelum pukul delapan dan sore hari setelah pukul empat. Aku berdiri di depan rumah nomor dua. Mataku memandang lurus. Kali ini adalah kedua kalinya aku mengamati toko di rumah itu.
Toko itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Bercat putih susu, masih sama seperti dua puluh tahun yang lalu. Dulu aku diajak oleh ibuku berbelanja di sana, membeli beberapa alat tulis. Ibu memilih alat tulis yang diperlukan. Pulpen, pensil dan penggaris. Oleh pemilik toko pulpen dan pensil masing-masing diletakkan di dalam kaleng gula-gula berwarna merah. Beberapa kali ibu mencoba pulpen di kertas lusuh yang disediakan untuk membuat coretan. Sedangkan aku memandang kaleng gula-gula berwarna merah itu dengan takjub. Air liurku terbit saat membayangkan manis gula-gula itu tercecap di lidah. Aku yakin betapa nikmatnya mengulum gula-gula itu.
Ibu berjalan ke meja kasir untuk membayar. Di sana telah menanti seorang wanita yang sepertinya seusia dengan ibuku. Dia duduk di belakang sebuah meja kayu berwarna coklat berbentuk bujursangkar. Di atas meja berjejer rapi dalam satu garis lurus, sempoa, pensil dan potongan kertas yang berasal dari kalender kedaluwarsa. Rambut wanita itu telah memutih di beberapa bagian. Kulitnya kuning gading, matanya tidak sipit tidak besar, namun sorotnya tegas. Ketika itu, aku memandangnya takut-takut. Intuisi bocahku mengatakan bahwa wanita ini galak, tegas dan sedikit toleran.
Wanita itu menghitung belanjaan ibu. Dia menyebutkan sejumlah angka. Ibu menyerahkan sejumlah uang. Sedangkan aku masih memandang gula-gula merah segar pada kaleng pulpen dan pensil.
“Berikan permen saja,” ujar ibu pada wanita itu, ketika mengetahui masih ada kembalian untuknya.
“Aku tidak berjualan permen,” sahut wanita itu pendek.
“Aku pikir ada, karena kaleng-kaleng tempat pensil dan pulpen ini, semuanya berasal dari kaleng permen.” Ibu beralasan.
“Tidak. Aku tidak menjual permen. Gula-gula hanya membuat sakit gigi. Pembodohan rasa,” cetus wanita itu, sambil menyerahkan sejumlah uang kepada ibu. Ibu menerima uang itu, kemudian menghitung dan jumlahnya memang pas, hingga nominal terkecil. Sedangkan aku hanya mampu meneguk liur saat keluar dari toko itu. Gula-gula merah itu melambai-lambai di depan mataku.
Di luar toko, aku melihat dua orang bocah laki-laki, badan mereka lebih tinggi dari badanku. Mereka menyeringai sambil memperlihatkan giginya yang berbalur merah. Aku tahu, balur merah itu adalah baluran permen. Saat mereka melintas kemudian menghilang ditelan pintu toko, aku mencium wangi yang segar dan manis.
“Kalian makan permen?” Aku mendengar suara wanita itu, bertanya dengan nada tinggi.
“Tidak, Bu. Tidak.” Salah satu dari mereka menjawab.
“Jangan bohong!” Terdengar suara bentakan, lalu bunyi keteplak yang keras disusul jerit tangis. Ibu memandangku, aku memandang ibu, kemudian ibu menarik tanganku menjauh.
Hari ini, di bawah terik matahari yang meninggi, aku menatap toko itu. Benar-benar masih sama seperti dua puluh tahun yang lalu. Cat putih susu. Sungguh berbeda dengan tempat usaha lain yang kini berwarna pastel yang genit. Dua jendela dengan kusen tipis kecil-kecil dengan lintangan palang serupa salib di tengah-tengah jendela dan satu jendela polos tanpa palang. Dari jendela polos itu, aku bisa melihat keseluruhan isi toko itu.
Aku menyeberangi jalan aspal dengan tergesa. Panas yang diserap oleh aspal membuat kakiku, yang hanya beralaskan sandal jepit tipis, kepanasan. Aku mempercepat langkah, sesegera mungkin mencapai emper toko.
Setibanya di emper toko, aku menyentuh pintu toko, membukanya dengan perlahan. Tidak ada pembeli lain. Hanya aku. Begitu hening, dingin dan sepi. Aku telah mendengar cerita orang-orang, bahwa tidak ada lagi yang berbelanja ke toko ini. Penjualnya semakin tua dan lamban, barang-barang yang dijual tidak banyak mengalami perubahan. Meskipun demikian, wanita itu tetap membuka tokonya dari jam delapan pagi hingga lima sore, setiap hari tanpa libur.
Aku melihat rak yang memajang alat tulis. Kulihat beberapa pulpen dan beberapa pensil masih diletakkan di dalam kaleng dengan gambar gula-gula merah yang segar. Kali ini aku tahu itu adalah merah buah ceri. Aku memandang kaleng itu dengan takjub. Kali ini bukan pandangan yang menerbitkan air liur melainkan pandangan penuh pertanyaan, betapa tabahnya wanita itu hidup selama puluhan tahun bersama kaleng-kaleng itu.
Aku mengambil sebuah pulpen, sebenarnya tidak begitu perlu. Saat mengembalikan sisa pulpen lain ke dalam kaleng, aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku. Aku menoleh, dan kulihat wanita itu sedang duduk di belakang meja bujursangkanya,
Wanita itu kini telah memutih seluruh rambutnya. Tubuhnya kurus, lebih kurus dari tubuhku ketika masih SD. Sekilas dia terlihat seperti sedang ditelan oleh meja itu. Aku menghampirinya, hendak membayar dan jika memungkinkan akan berbincang sebentar.
Di atas meja, masih sama seperti dulu. Hanya ada sempoa, pensil dan potongan kertas yang berasal dari kalender kedaluwarsa. Tidak ada perubahan. Aku melirik wanita di hadapanku, tua dan kesepian. Sesepi rumah yang berdiri kaku di belakang toko. Menanti entah apa dalam diamnya.
Aku menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Wanita ini menghitung dengan seksama. Dia mencari beberapa kembalian.
“Ganti permen saja, Bu” ujarku, karena melihat wanita itu mengorek lacinya demi menemukan beberapa uang kecil. Mendengar ucapanku, wanita itu memandangku tajam.
“Apakah mesti aku ulangi kata-kataku, gula-gula hanya membuat sakit gigi. Pembodohan rasa.” Suaranya parau. Aku terdiam, kata-katanya persis sama dengan kata-katanya dulu ketika aku mengintip takut-takut dari balik punggung ibu. Wanita itu memberiku sejumlah uang, dan ketika uang itu aku hitung, jumlahnya sesuai hingga nominal terkecil.
Aku pamit. Setibanya di luar toko, aku memandang ke dalam. Wanita itu masih duduk di belakang meja. Pandangannya jauh ke depan, seolah menanti.
“Anak-anaknya menjauh. Tidak ada yang ingin tinggal satu rumah dengan ibunya.” Ujar ibuku, ketika aku bercerita tentang sepinya rumah nomor dua.
***
Keesokan harinya, aku kembali berkunjung ke toko itu. Aku buka pintu toko dan segera menuju meja kasir. Wanita itu ada di sana, menatapku heran karena datang kembali.
Aku menghampirinya kemudian aku letakkan sebuah kaleng di atas meja bujursangkarnya. Kaleng bergambarkan gula-gula berwarna merah yang benar-benar berisikan gula-gula beraroma ceri, persis sama dengan kaleng penampung pulpen dan pensil di toko itu.
“Letakkan ini di atas meja dan mereka akan pulang.” Ujarku lirih kepada wanita itu. Aku teringat pada gigi anak-anaknya yang berbalur merah serta suara keteplak yang keras disusul teriak kesakitan.
Kaleng permen itu aku letakkan berjejer di antara sempoa, pensil dan kertas kalender. Kini di atas meja terdapat empat benda. Kaleng gula-gula ceri dariku menjadi pemanis.
Aku memandangnya. Namun wanita itu terdiam dengan bibir yang mengkerut. Dia memandang kaleng permen itu selama beberapa saat. Tanpa sadar napasku tertahan. Perlahan pandangannya beralih, tepat menatap mataku. Aku melihat kilat amarah bercampur sepi mendung kelabu pada bola matanya yang dihampiri katarak.
“Dengar. Aku akan menanti dengan caraku. Bawalah kembali kaleng permenmu. Pembodohan rasa.” Dia menyorongkan kaleng permen itu ke tanganku. Kaleng itu berpindah. Di atas meja bujursangkar kembali hanya ada sempoa, pensil dan kertas kalender kedaluwarsa.
Aku mengganguk sopan, kemudian beranjak. Di toko tua itu, waktu tak pernah menua meski dua puluh tahun telah berlalu. Sama halnya dengan keteguhan hati yang berteman sepi. ***
(Denpasar, Oktober 2019)






.jpg)
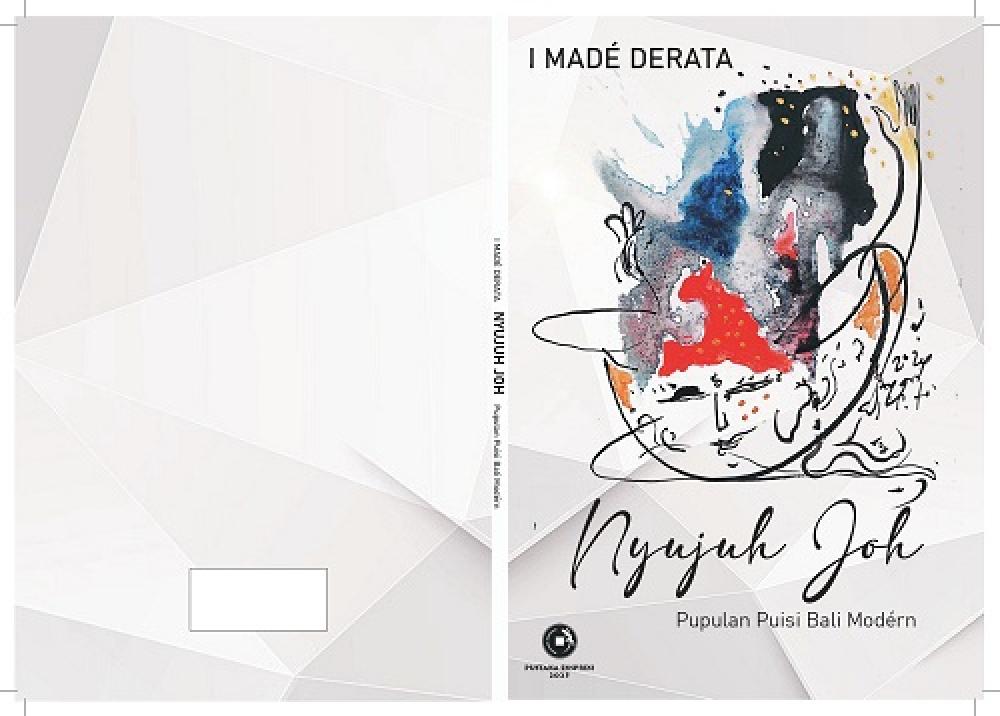

.jpg)
.jpg)
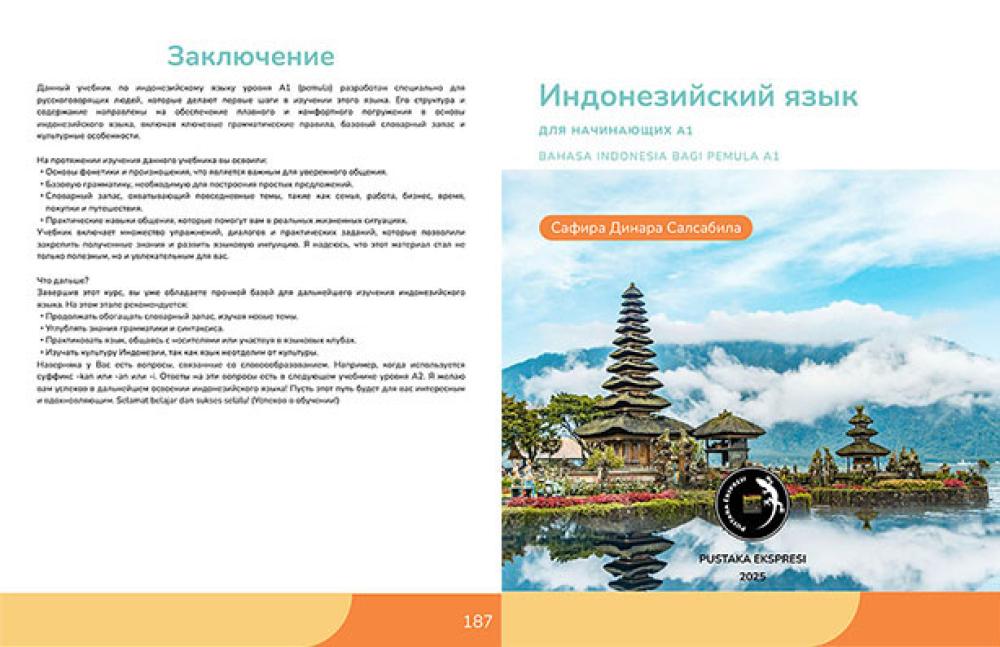
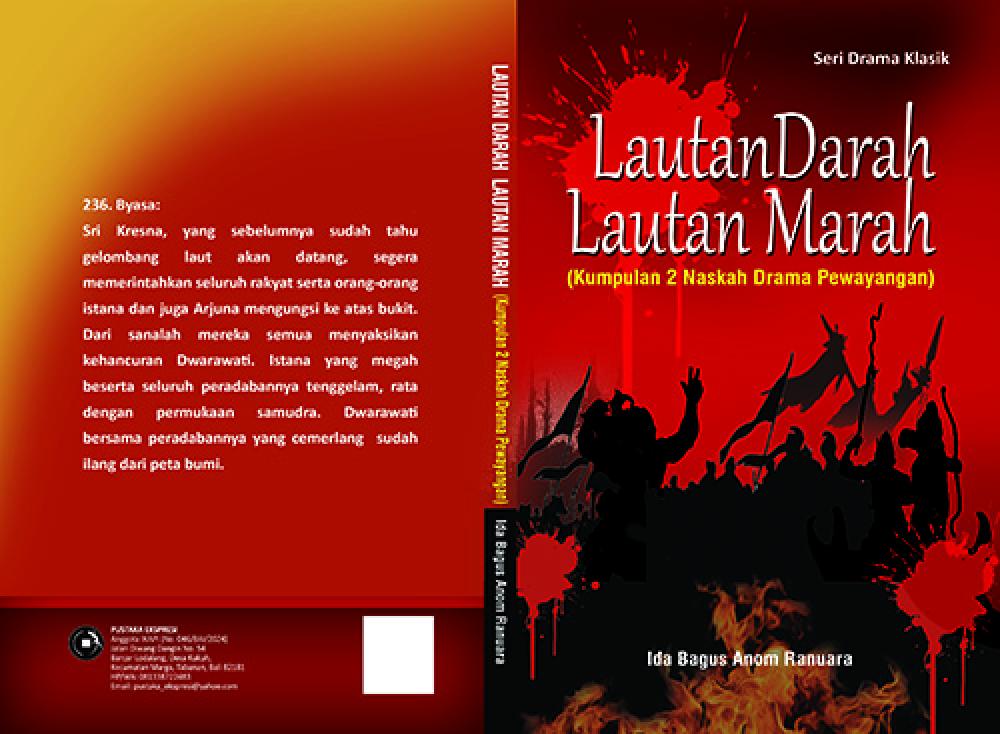
.jpg)

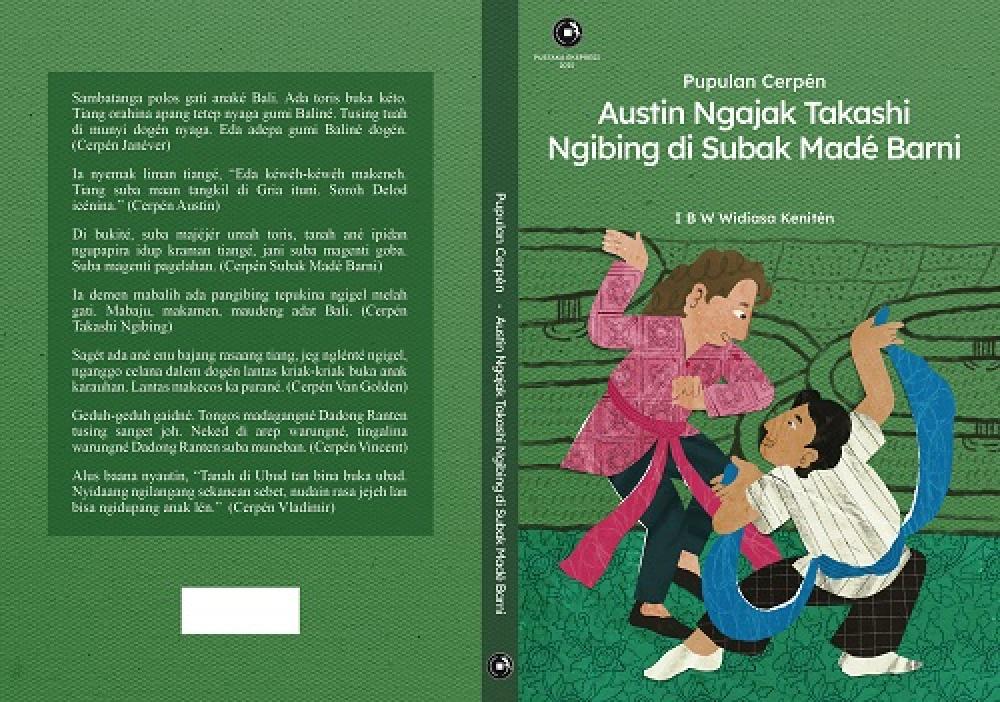


Komentar