Debur Ombak Kusamba
By IBW Widiasa Keniten
- 07 Januari 2020

Deburan ombak Kusamba memecah keheningan hari itu. Para pecinta laut mendayungkan jukungnya menuju rumah ikan. Tangannya terus mendayung mencari penghidupan. Nelayan pengadu nasib itu melabuhkan harapannya pada laut. Laut sebagai ibu bagi kehidupannya. Ibu laut memberi kasih dan cinta demi sebuah hidup.
Deburan demi deburan datang bergantian. Dewa Aruna mulai merangkak. Perlahan, namun pasti. Perjalanan yang tiada pernah berhenti. Berputar dan terus berputar karena cintanya pada semesta. Semburat kemerahan ibarat seorang gadis yang sedang bersedih membuka pantai Kusamba. Orang-orang yang mau menuju Nusa Penida berlomba menaiki boat. Transportasi yang mengantikan jukung. Ukurannya lebih besar dengan mesin yang PK-nya besar juga. Nusa Penida, pulau yang menjaga keseimbangan tanah Bali. Pulau karang menghalangi deburan samudera. Bersyukurlah Bali memiliki Nusa Penida. Mutiara gumi serombotan. Beberapa pemangku beserta rombongannya bersiap menuju Nusa Penida. Ada kepulan dupa harum di atas pasir hitam. Aku yakin orang-orang yang akan menuju Nusa Penida melakukan pemujaan pada laut di pagi hari. Pemujaan pada laut tidaklah berhenti sampai di sana. Ia mesti dirawat dan dijaga keindahannya.
Pasir hitam yang kulewati sengaja kutekan semakin keras. Aku merasakan getaran Puputan di dalamnya. Darah segar terbayang di mataku. Aku teringat betapa Ida I Dewa Istri Kania mempertaruhkan harga diri demi negerinya. Seorang perempuan yang menjalani jalan sunyi dengan sebuah pengrupak di tangannya. “Raja yang rakawi,” bisikku. Kakiku terus merangkak sambil sesekali melintasi beberapa penjual pindang. Ada yang sedang memanggang pepes ikan laut beserta satenya. “Sate dan pepes Pak. Masih hangat,” sapanya. Aku menjawabnya dengan senyum.
Aku memang suka laut. Aku suka mengail seperti kesukaan ayahku dulu. Kail yang telah terisi umpan kulempar ke laut. Temanku yang memiliki kegemaran sama denganku berada di kejauhan. Katanya agar lebih cepat dapat ikan. Aku setuju saja. Kurang bagus kalau memancing terlalu berdekatan.
Kususuri pantai Kusamba. Panas mulai menyengat. Awan tak menyelimutinya lagi. Ia leluasa menampakkan kegagahannya. Deburan demi deburan ombak menggodaku. Kubasuh tanganku. Kurasakan asinnya air laut. Air laut asin, tapi ikan laut tak terikat pada keasinannya. Tempat tidak mengikat kehidupan ikan-ikan itu. “Luar biasa,” bisikku. Buih-buih putih terpapar di laut. Angin laut terasa segar mengaliri tubuhku. Kulewati petani garam tradisional. Pondoknya yang sederhana itu sebagai tempat berteduh. Kulihat tubuhnya kuat dan perkasa. Ia angkut air laut. Ia tuangkan di ladang tempat pembuat garam.
“Gimana harganya, Pa?” Aku memberanikan diri menanyakan hal-hal kecil seperti itu.
Ia pun tersenyum. Aku mengerti makna senyumnya. Ia pandang laut yang luas. “Hanya karena cinta saja Bapa masih setia pada pekerjaan ini. Jika tidak mungkin sudah beralih profesi.” Dari kata-kata itu, terselip keragu-raguan melanjutkan mata pencahariannya. “Dulu banyak yang hidup dari bertani garam. Tapi sekarang, yaaaaaaaaaaaaa hanya segini saja.”
Cintanya pada laut yang mengikatnya. Cintanya pada tanah Kusamba yang menguatkan hatinya bertahan sebagai petani garam. Walau sepi pelanjut, petani garam itu masih setia pada warisan leluhurnya. Ia sadari penjualan garam tak seberapa. Ia tahu bahwa hidup semakin keras. Hidup sebagai petani garam tak akan bisa memenangkan persaingan. Karena cintalah yang mengikat hatinya.
Beberapa turis mendekati ladang garam. Ia mengabadikan kehidupan petani garam. Kekagumannya terlihat di wajahnya. Mungkin ia berpikir bahwa dalam dunia modern masih ada yang setia sebagai petani garam. Gaid-gaid merasa bersyukur. Bersyukur karena turis yang diajaknya terpuaskan hatinya.
Bibirnya tersenyum. “Bersyukur masih ada petani garam seperti ini di Bali. Sisa-sisanya masih bisa dilihat. Dulu, bibir pantai di Bali rata-rata ada petani garamnya hingga tak lagi kekurangan garam. Negeri yang lautnya lebih luas dibandingkan daratannya ternyata masih menginpor garam. Kan aneh?”
Aku tidak menyahut. Aku hanya bisa melihat sebuah kenyataan bahwa petani garam perlu dihidupkan lagi. Tapi ini tentu susah. Anak-anak sekarang jarang yang melanjutkan profesi orang tuanya. Ia lebih berbangga jika bisa meraup dolar dari mancanegara. Bekerja di hotel berbintang atau berlayar di kapal-kapal pesiar. Perubahan hidup menjalari Bali.
“Ke sini!” Panggil temanku. Umpannya telah berhasil mendapatkan satu ekor ikan laut. Ia memperlihatkan padaku. “Di sini masih ada ikan. Tak terlalu lama kailku sudah ditelan ikan. Aku suka Kusamba.” Ia lepaskan kait kailnya dari mulut ikan. Ikan itu menggelepar-gelepar seperti tak terima dirinya disangkut dengan kail. Umpan yang mengenakkan ternyata mematikan juga.
“Kusamba memberi semangat baru bagiku,” Ia memulai ceritanya. “Kail-kail ini telah beberapa kali kugunakan. Tapi baru sekarang kudapatkan ikan sesuai harapanku. Pantaslah dulu Belanda berupaya menghancukan Kusamba dengan segala tipu dayanya. Ternyata salah satunya ini sebabnya. Ikan-ikan kesukaannya ada di Kusamba.” Ia medesah. “Kata tetuaku, ada keluargaku yang ikut membela pertiwi ini. Ia pertaruhkan jiwanya demi harga diri bangsanya.”
Denyut pergolakan memang masih kurasakan saat ia menceritakan jejak kepahlawanan leluhurnya. Seperti ada teriakan-teriakan yang menandakan bahwa masih ada yang sutindah pada Kusamba. Darah merah seakan mengalir di sela-sela tempat kami duduk. Dentingan tombak. Desingan peluru seakan silih berganti menembus bumi Kusamba. Aku berbisik pada temanku. “Apa yang kau rasakan tadi?”
“Jeritan pejuang Kusamba. Bau amis seperti mengejarku.”
Aku berusaha mendekatkan telingaku. Jerit tangis dan pekik merdeka membuka bumi Kusamba. Gerak jiwa memburu. “Tanah Kusamba tak boleh hilang! Tanah Kusamba bukan milik penjajah! Lawan! Ayo lawan!”
Aku bergidik. Peluh merembes. Suara-suara itu merindingkan hati kecilku. Aku menjauh agar suara-suara itu tidak memburuku lagi.






.jpg)
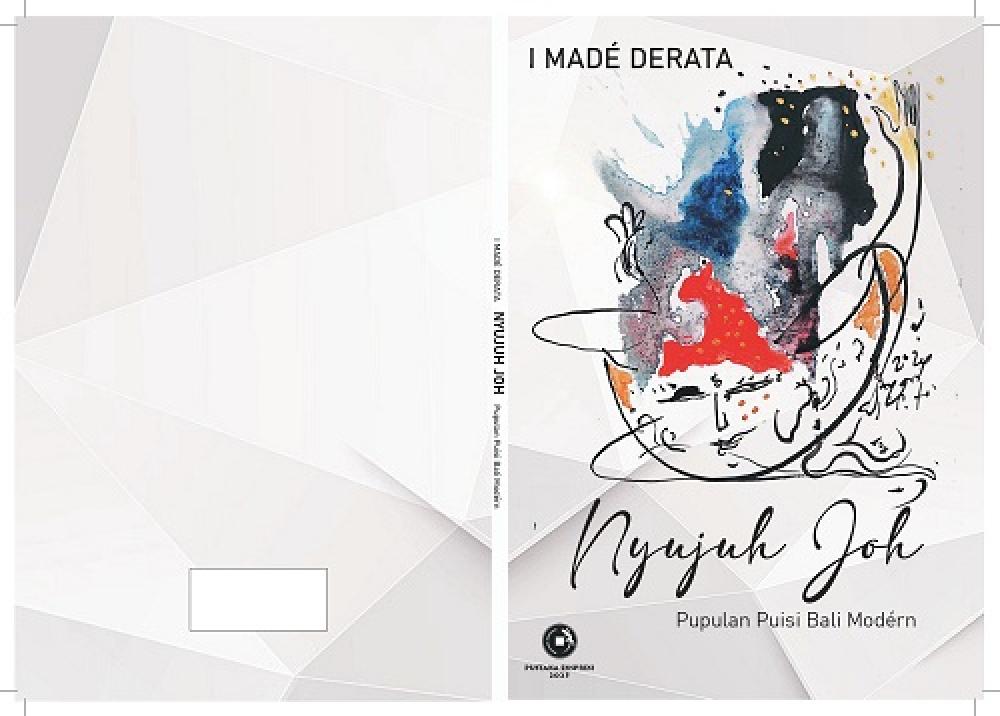

.jpg)
.jpg)
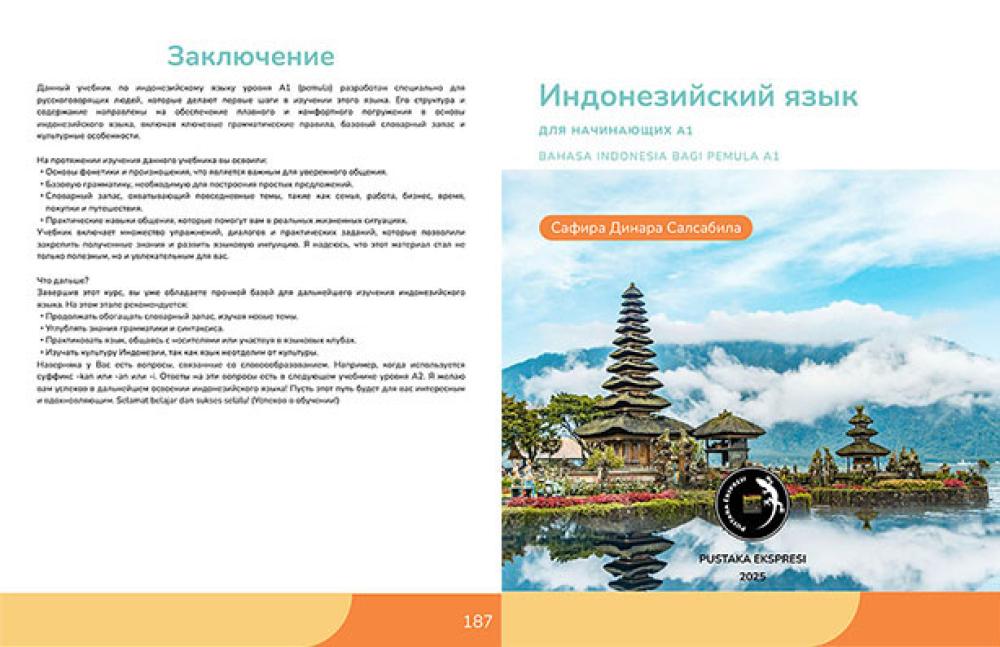
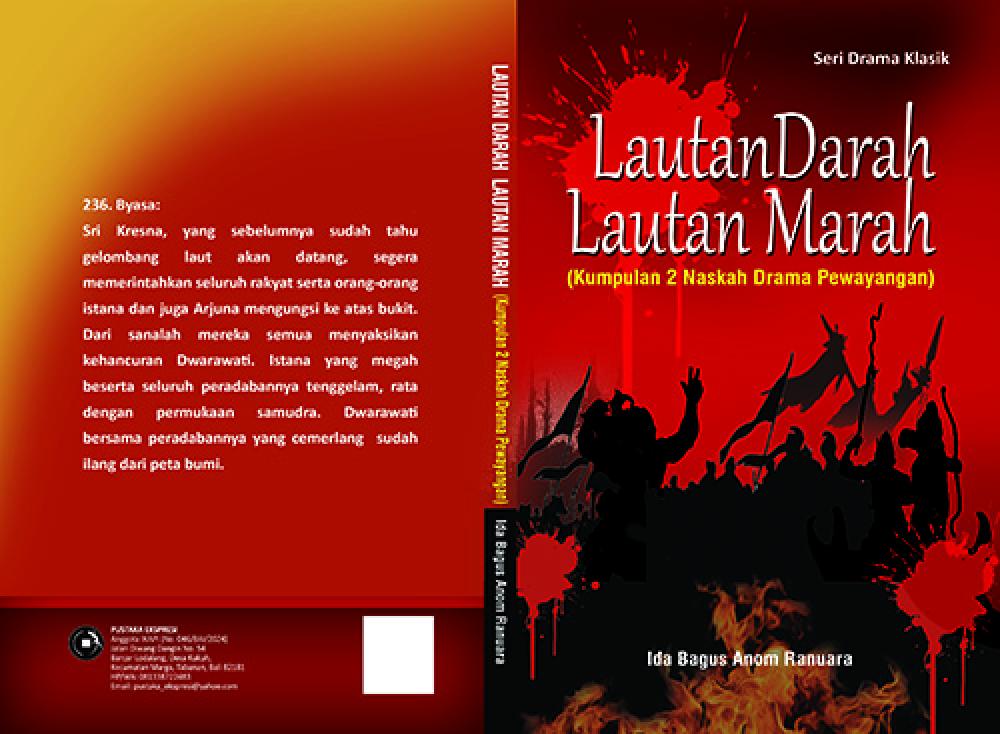
.jpg)

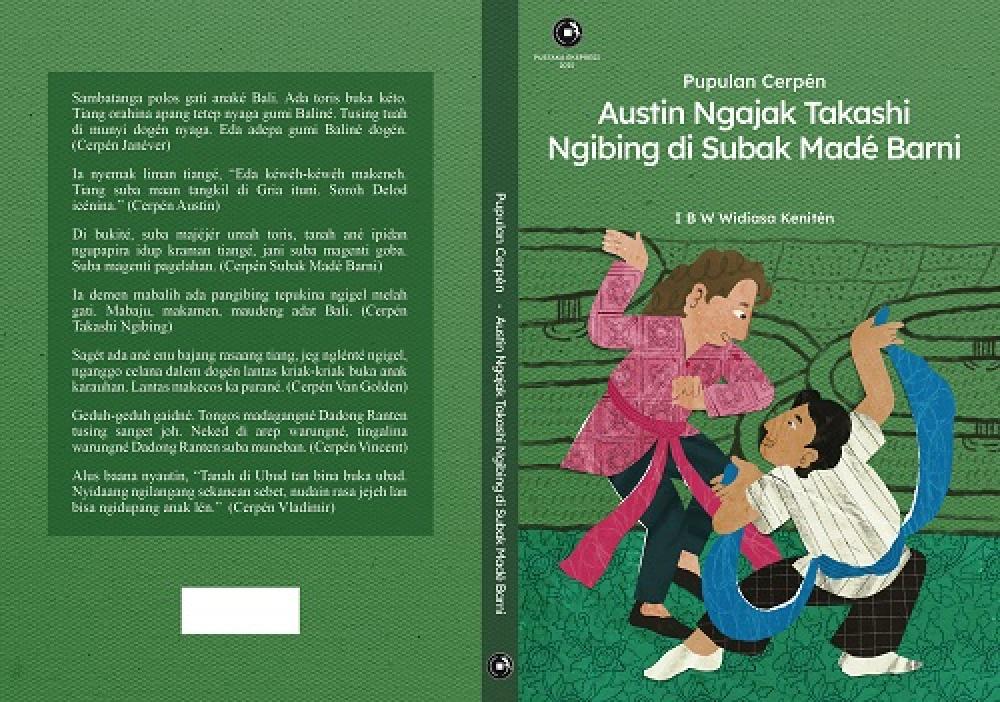


Komentar