Ketika Rindu Sewarna Mentari
By IBW Widiasa Keniten
- 26 Desember 2022

“AYAH kenapa membagi cinta? Apa cinta ibu tidak cukup buat ayah? Apa yang ayah kejar di kehidupan ini? Jangan salahkan ibu meninggalkan kami. Mana ada perempuan hatinya berebut cinta dalam sebuah rumah tangga?” Gadis manis itu menuliskan isi hatinya dalam buku hariannya. Ia merasa tak punya cinta yang sempurna dalam kehidupannya. Setelah mengetahui ayahnya berbagi kasih, ibunya tanpa babibu, langsung kembali ke rumah orang tuanya. Kabar terakhir, ibunya juga menikah dengan laki-laki yang baru dikenalnya lewat media sosial.
Ia mendesah saat menuliskan kata-kata itu. “Kenapa kelahiranku mesti menghadapi persoalan seperti ini? Apa ia lupa saat pertama saling memuji, saling merayu, yang pada akhirnya mau hidup bersama. Setelah sekian waktu, kenapa harus berpisah? Kenapa tidak saat berpacaran saja langsung pisah? Kan tidak lahir aku ini dalam keluarga berantakan?” Candra bergulat dengan hatinya. Ia tak bisa terima kenyataan yang dihadapi. Setiap ada laki-laki yang memuji dirinya jawabannya hanya satu. “Jangan merayuku, aku sudah muak dengan kata-kata memoles diri. Itu lihat orang tuaku. Dulu, saling mencintai sekarang bubar tak karoan, akulah yang dikorbankan. Apa salahku lahir? Tak usah jatuh cinta padaku. Aku sudah tak percaya sama cinta. Aku benci dengan kata cinta. Itu cari gadis lain yang bisa kau perlakukan seperti ayahku.”
“Tidak semua laki-laki seperti itu.”
“Ah, dasar kau ada maunya. Itu hanya alasan saja agar aku jatuh cinta padamu. Tak usah, biar aku sendirian. Cinta itu sudah menghancurkan harapan-harapan hidupku. Sana pulang saja!”
Laki-laki yang mendekatinya tak bisa menaklukkan hatinya. Ia merasa heran dengan Candra yang teramat benci kepada laki-laki. “Yah, sudah kalau tak bersedia. Aku pamit.”
“Sudah tak usah banyak rayuan di sini.”
Ibu tirinya berusaha mendekati hatinya. Tapi, lukanya teramat mendalam, ia tak bisa menerima dengan kenyataan itu.
“Ibu yang salah karena memisahkan orang tuamu, Candra. Tolong terima ibu sebagai ibu kandungmu juga.”
Candra terdiam. Di hatinya, bergeluncak beragam rupa kemarahan. “Baiklah demi masa depanku. Aku terima ibu sebagai pengganti ibu kandungku. Tapi, di tubuh ini, tak ada aliran darah dari ibuku. Sembilan bulan ibuku mengandungku, berapa susu yang sudah mengalir dalam tubuh ini, sedangkan dari ibu tak ada. Mana mungkin bisa sama dengan ibu kandungku. Walau ia menikah lagi, ia tetap ibu kandungku. Jika ibu tidak sebagai pelakor, pastilah keluarga ini akan bahagia.”
“Maafkan kesalahan ibu, Candra.”
“Sudah jangan banyak cerita. Candra mau tidur.” Candra ke kamarnya menikmati kesedihannya. Ia peluk bantal gulingnya. Ia pukul-pukul. Air matanya menempel di pipinya. “Hyang Widhi kenapa harus aku yang seperti ini? Apa tak ada yang lainnya yang kena karma ini?”
Ia tatap foto kedua orang tuanya saat awal-awal pernikahan. Berdampingan dan selalu menyatu, tapi sekarang, pudar. Ego mempermainkan jalinan yang terajut saat awal-awal saling mencinta. “Foto itu hanya kamuflase saja. Orang tua kayak apa ini?” Air matanya terus mengalir. Ia ambil foto orang tuanya yang berdampingan saat upacara pernikahan. Bayangan puja-puja sulinggih berkelebat di pikirannya. Puja-puja kepada Dewa Smara-Ratih agar bisa menyatu dalam rumah tangga. Gender dan kidung terasa terngiang-ngiang di telinganya. Orang-orang hadir dalam keriangan dan keceriaan. Wajah-wajah bahagia tersirat di raut wajah para undangan.
“Ratu Hyang Widhi kenapa tidak ingat saat diupacari sesuci itu?” Ia baca bulan pernikahan orang tuanya. “Desember, sasih Kapitu, berarti akhir tahun. Bulan yang dibasahi dengan hujan semestinya selalu sejuk. Sudahlah biarkan saja mau apa orang tuaku. Aku tak mau peduli padanya.” Candra menggantung kembali foto pernikahan orang tuanya. Ia berusaha melelapkan matanya walau teramat susah. Kantuknya seakan tak mau mendatangi dirinya hingga menjelang subuh, baru sempat terkatup.
“Candra bangun! Bangun Candra! Ini ibu sudah buatkan susu.” Ibu tirinya mengetuk pintu kamarnya. “Candra Bangun! Bangun Nak!”
“Ah, ibu mengganggu saja.” Ia buka pintu kamarnya. “Candra masih ngantuk. Taruh saja di sana!”
“Maafkan ibu, sudah merebut ayahmu.”
Candra tak mendengarkan ibu tirinya. Ia memeluk bantal gulingnya. Matanya masih merah menahan tangis kemarahan.
“Apa tidak sekolah?”
Candra bergegas. Ia bangun. Susu yang dibuatkan oleh ibu tirinya diseruputnya cepat-cepat. Ia membersihkan tubuhya. Suara airnya sengaja dikeraskan.
“Ini sudah ibu buatkan nasi goreng. Nasi kesukaan Candra. Makan dulu baru berangkat ke sekolah. Ibu yang ngantar ke sekolah.”
“Tak usah Bu. Candra bisa bawa sepeda motor.”
“Kebetulan ibu mau keluar juga. Kita sama-sama.”
Candra tak bisa menolak permintaan ibu tirinya. Ia berbocengan. Teman-teman sekelasnya sudah menunggunya sedari tadi. Jika Candra belum datang, kelas kurang seru. Tapi, semenjak orang tuanya mencari jalan masing-masing, ia berubah. Jarang bicara. Sering murung dan terkadang uring-uringan. “Sedari tadi kami menunggumu, Candra. Nah, itu baru ibu yang baik mau ngantar Candra ke sekolah. Memangnya sepedamu ke mana?”
Candra tak menjawab. Ia menuju tempat duduknya. Ia berusaha mengikuti pelajaran hari itu, tapi satu pun tak ada yang nyantol di otaknya. “Dasar orang tua tak suka melihat anaknya bahagia”. Ia tatap papan tulis dengan tatapan kosong.
“Coba jawab ini, Candra,” Guru itu memperhatikan anak didiknya.
Keringatnya membasahi tubuhnya. Tak ada jawaban yang keluar dari bibirnya yang manis itu. “Hidup penuh misteri, anak-anakku. Terkadang yang kita pikirkan, yang kita rasakan tak seindah yang kita lihat. Kita harus bisa berdamai dengan hati. Setiap hidup ada jalannya masing-masing. Ikuti jalan hidupmu yang seirama dengan hatimu. Jangan bertindak bodoh dalam hidup. Isi hidup dengan keindahan walau jalannya teramat terjal. Bapak sedari kecil sudah hidup menyendiri. Hidup di panti asuhan, tapi tak mau menyerah. Anak-anak yang masih punya orang tua hormati ia walau mungkin jalannya tak benar menurutmu. Tapi, itu pilihan orang tuamu. Tataplah mentari itu. Ia tak pernah berhenti memberi terang pada semesta, walau terkadang tersaput awan hitam, ia akan muncul lagi terangnya, begitu juga hati kita. Cita-cita lebih utama daripada kesedihan yang membelenggu hati. Jangan sia-siakan waktumu. Hidup memang pilihan. Pilihlah yang terbaik buat dirimu. ”
Candra terdiam. Ia menahan tangis. Hatinya terasa hampa. Ia merunduk lesu. “Ayah, maafkan sikapku selama ini. Aku rindu kasihmu,” bisiknya dalam hati.
Catatan:
Hyang Widhi: sebutan Tuhan dalam agama Hindu
Sulinggih: orang suci
Sasih Kapitu: bulan ketujuh kalender Bali, satu sasih 35 hari






.jpg)
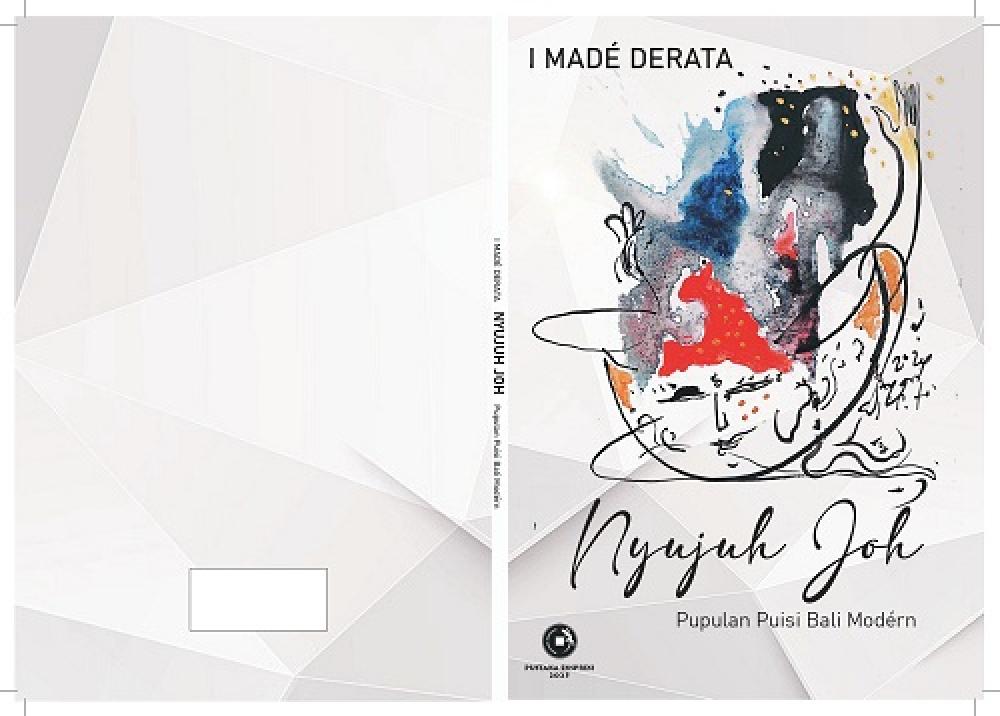

.jpg)
.jpg)
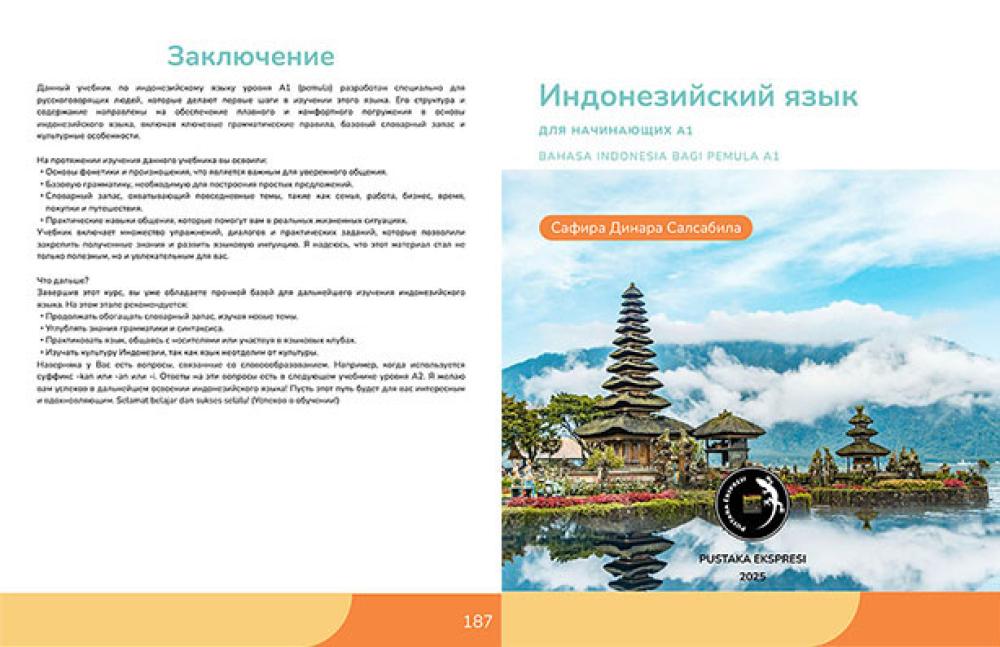
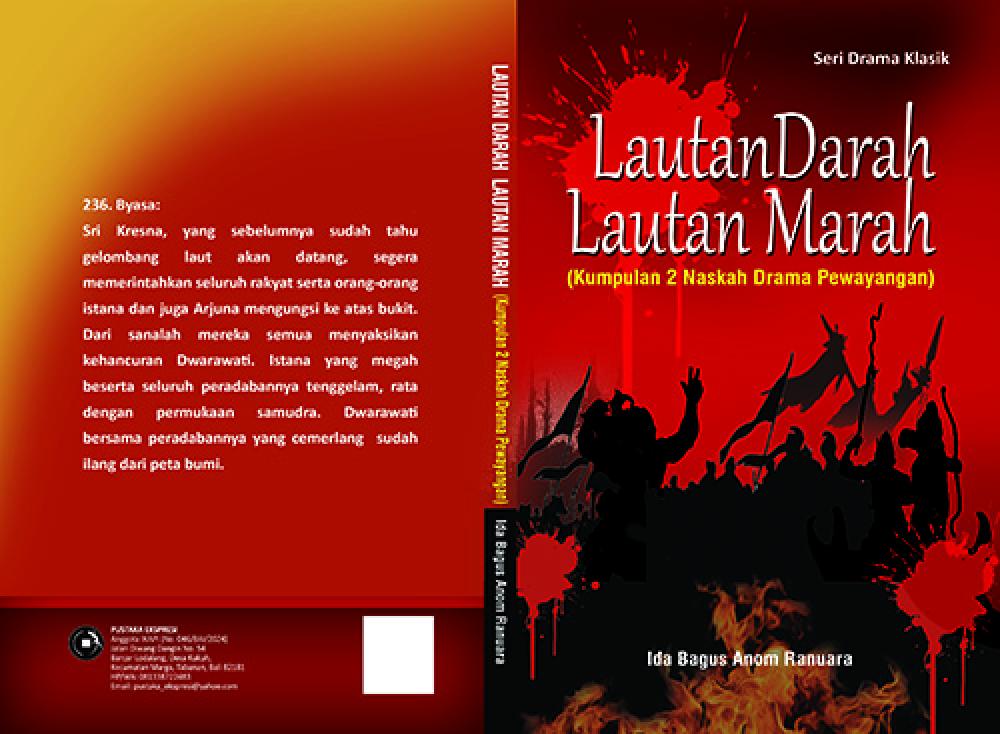
.jpg)

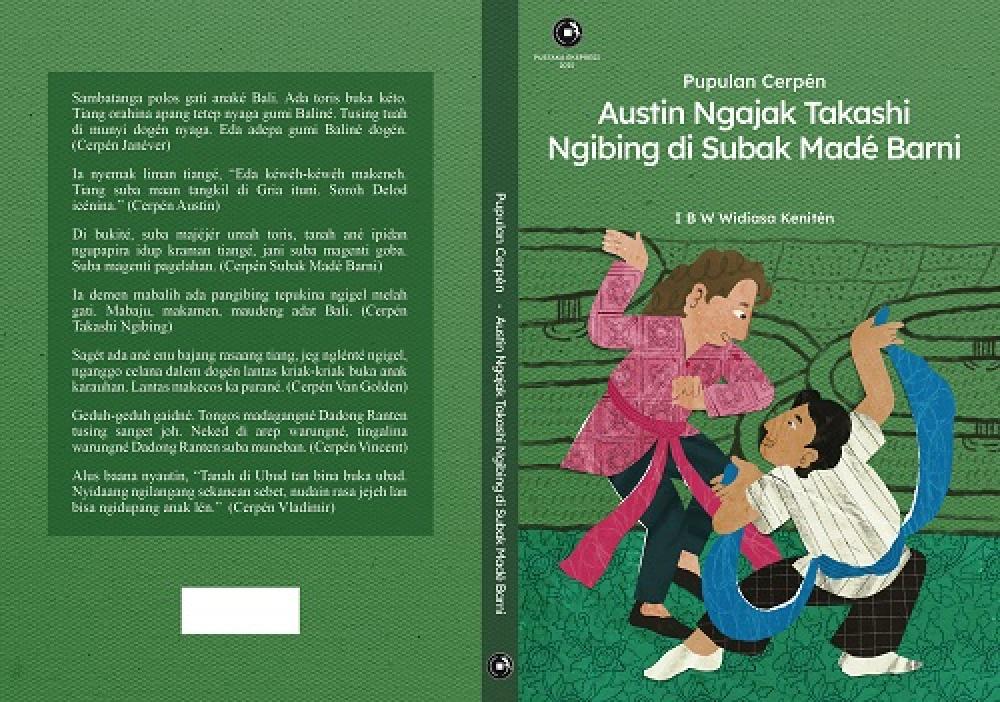


Komentar