Jalan Sastra Made Edy Arudi, Catatan Pengantar untuk buku kumpulan puisi: Sukasada, Tanah dan Daun-d
 By Wayan Artika
By Wayan Artika- 01 Oktober 2023

Dari judulnya, antologi puisi ini dapat dipilah jadu dua. Puisi-puisi yang diberi judul nama-nama tempat dan puisi yang judulnya abstrak. Sejalan dengan itu, Made Edy Arudi memberi masing-masing tanda subbab “I” untuk yang pertama dan tanda “II” untuk kategori kedua. Praktis buku kumpulan puisi ini terdiri atas dua bagian. Hal ini menunjukkan arah jalan sastra yang dilewatinya.
Walaupun judul karya dibuat paling akhir dalam proses kreatif menulis namun setelah suatu karya seni, semisal puisi, dipublikasikan, maka akan jadi unsur yang pertama. Semua puisi diberi judul. Hal yang paling singkat dari puisi tetapi ditempatkan paling awal atau pada bagian atas dari karya tersebut. Perlu pula ditulis dengan cetak tebal dan menggunakan ukuran huruf yang lebih besar. Artinya tidak hanya secara visual tetapi secara tematik atau isi, judul itu sangat penting dan sangat terhormat. Ia kelak akan mewakili seluruh karya itu, seberapa pun tebal dan panjangnya.
Dengan demikian, judul karya (juga puisi) adalah fokus pembaca. Judul menjadi nama suatu puisi. Tidak hanya sebatas nama untuk tujuan menamai! Judul pada karya sastra adalah seperti sepotong hipotesis bagi pembaca. Tetapi sebagai simpulan atau elaborasi bagi penulis yang tengah menyelenggarakan penalaran atas dirinya saat simpulan mesti diambil secara dekduktif.
Di antara pembaca dan penyair, judul adalah jembatan yang berfungsi terbalik atau bertentangan. Bagi pembaca judul adalah induksi dan bagi penyair judul adalah deduksi. Judul dicercap paling pertama. Pembaca telah memiliki mungkin setengah isi puisi dari judulnya. Pada saat membaca, ia bermaksud menemukan setengah lagi. Jika pembacaan dan pemahaman ini sukses, maka pembaca akan mendapatkan pengertian yang pas. Walaupun ukuran pas dalam hal ini terlampau subjektif. Namun demikian sudah menjadi sukses besar bagi seorang pembaca.
Apa tujuan membaca puisi? Bagi teori-teori sastra besar, adalah untuk mendapatkan kepuasan batin, kontemplasi, ekstase, dan katarsis. Atau bisa juga ke pandangan yang sangat sulit diterima yakni meditasi atau yoga. Tapi dengan demikian, apakah lantas Anthony de Mello berlebihan ketika ia menggunakan cerita rakyat sebagai khazanah kebudayaan yang paling agung di dunia, alat meditasi?
Sejatinya tidak demikian! Seorang membaca puisi adalah hanya untuk mengetahui hubungan judul dan uraian (isi). Jika pembaca dapat menemukan judul di dalam suatu puisi maka ia berhasil mengerti tentang apa. Tetapi kalau sebaliknya, maka pembaca bersangkutan amat gagal membaca puisi. Lantas, puisi yang katanya agung, ditinggalkan. Puisi ini hanya menjelma menjadi kesulitan besar. Tidak ada yang membaca lagi lantaran “sulit” karena tidak menyampaikan realitas sebagai makna atau pengetahuan.
Yang tidak pernah selesai dipertanyakan dalam puiai adalah mengapa puisi itu harus sulit? Maknanya atau isi sejatinya puisi itu disembunyikan dengan sengaja. Makin sulit puisi diartikan oleh pembaca maka makin baguslah puisi itu.
Kondisi ini mungkin hanya menjadi standar bagi penyair yang gila. Tapi bagi pembaca, puisi adalah seperti kamus. Setiap lema dalam kamus mendapat penjelasan yang cukup. Penjelasan lema dengan contoh nyata penggunaan dalam kehidupan manusia, adalah arti kata. Maka arti kata adalah makna dan pengetahuan tentang kata, pengetahuan tentang realitas. Puisi kontras dengan kamus! Jika puisi membuat para pembaca bingung atas pengertian-pengertian atau pengetahuan-pengetahuan yang sengaja disamarkan; maka kamus membuat para pembaca paham dan mengerti!
Tapi dalam puisi, justru prinsip uraian arti kata-kata dikhianati. Para penulis puisi dengan sengaja menyembunyikan pengertian atau maksud di dalam puisi yang dibuat. Jadinya, puisi tiada lebih dari kebebasan belaka atau teks yang dibuat-buat.
Puisi yang dibuat-buat atau sastra yang dibuat-buat mungkin mendapat tempat tersendiri dalam dunia sastra tetapi ini sebuah pengasingan. Karya-karya yang seperti ini hanya sebuah masturbasi besar para penyair. Hanya memberi nikmat atau ekstase bagi yang melakukan. Itu semua untuk dirinya sendiri. Tapi sastra adalah pengertian sosial atau pengalaman bersama.
Prinsip ini tiada terwujud dan puisi-puisi yang menyembunyikan dengan sengaja pengetahuan, dunia atau realitas makna atau keberadaan kandungan pengetahuan sosial, sains, dan filsafat; akan jadi sampah. Jangan harap akan dibaca. Pilihan terbaik bagi karya semacam ini adalah hanya menambah tumpukan sampah teks yang mengapung.
Karena sikap penyair sengaja menulis puisi yang sangat sulit, puisi sebagai dunia sendiri penyairnya maka puisi tidak pernah menjadi barang populer di masyarakat. Puisi selalu terasing dan termarginalkan. Hal ini bukan karena kebodohan pembaca tetapi sudah jelas ini terjadi karena kesombongan penyairnya.
Kalau puisi-puisi itu adalah kebebasan mutlak yang mana tampak dalam hukum bebas menggunakan kata dan mencipta makna dimana hanya menjadi pengertian penyairnya seorang diri; maka untuk apa puisi disebar dalam kehidupan. Penyair memberi tugas berat masyarakat agar membaca dan menerima puisinya. Tapi urusan masyarakat tentu bukan hanya memahami puisi yang sulit karena hanya dibuat-buat sedemikian susah dimengerti. Urusan pembaca jauh lebih banyak ketimbang urusan dan hidup para penyair.
Jika puisi demikian sulit karena dengan sengaja sebagai suatu cara untuk membedakan diri penyair dan diri sosial para pembaca; lalu mengapa puisi harus disebarkan dalam buku, koran, majalah, internet dan lain-lain? Buat saja puisi sendiri dan berhentilah menjadi penyair karena puisi tidak menjelaskan dan memberi pengertian atas realitas tetapi justru menciptakan kebingungan dan hendak mengasingkan pembaca ke dalam diksi.
Karena itu, definisi puisi yang mengarah kepada kontemplasi dan keagungan tidak pernah diterima oleh masyrakat pembaca sebagai kebenaran. Masyarakat telah menolak puisi dengan cara tidak peduli. Masyarakat tidak mendapat faedah atau kemaslahatan apa-apa atas puisi-puisi.
Pada sisi lain, dunia selalu melahirkan para penyair. Mereka akan tetap bekerja pada penciptaan puisi untuk mengasingkan diri dan menyerap pembacanya. Namun demikian pembacanya tidak mudah dipengaruhi. Puisi yang gelap makna dan kosong pengetahuan, ditinggalkan dan dunia dipenuhi oleh sampah puisi.
Puisi jadi sampah karena dengan sengaja ditulis untuk menyembunyikan realitas. Puisi hanya diksi yang kacau balau. Puisi hanya teks menggunakan kata yang justru saat kata-kata digunakan menjadi tidak bermakna atau sulit dimaknai. Para leksikograf dengan setia bekerja keras menjelaskan pengetahuan dalam setiap kata di dalam kamus sehingga semua pengguna bahasa mendapat uraian-uraian yang lerngkap dan tepat dari sepotong kata. Tapi para penyair justru menggunakan kata dengan melakukan pengkhianatan leksikal. Makna-makna kata di dalam kamus ditolak dan hanya dipinjam bentuk wadagnya saja untuk diisi makna baru.
Referensi makna pembaca atau masyarakat adalah kamus. Tapi dalam puisi kata-kata kamus tidak mau digunakan secara utuh: kata dan pengertiannya. Jelas ini sudah jalan sesat yang diambil oleh para penyair. Bukannya tiada perlawanan atau penolakan. Masyarakat pembaca menolaknya dengan cara tidak pernah menjadikan puisi sebagai teks dalam hidup sehari-hari.
Puisi adalah barang langka yang hanya dikenal oleh sedikit orang dalam suatu komunitas dan bahkan ada masyarakat atau komunitas yang tidak mengenal puisi. Berbahagialah mereka! Karena tidak memiliki sampah teks atau rongsokan kata-kata. Mereka tidak dibebani oleh sikap penyair yang mengubah pengertian atau uraian-uraian di dalam kamus untuk mereka gunakan di dalam puisi-puisinya.
Kata pengantar singkat dalam buku kumpulan puisi ini untuk menyatakan suatu penolakan bahwa puisi itu sulit. Namun demikian sebagai jebakan antara puisi dengan “I” dan “II”, tampak sekali ada tarik ulur antara jujur dan bersembunyi.
Puisi adalah barang yang sulit karena ulah penyairnya yang sengaja mempersulit, tidak hanya pembaca tetapi dirinya. Kesulitan ini tampak dari diksi yang aneh dan mengundang kerja keras untuk mendapat uraian-uraian yang masuk akal. Pembaca toh hanya mendapat teks yang mengkhianati makna kata dalam bahasa. Mana ada teks tidak bermakna; selain/kecuali dalam puisi. Puisi adalah teks yang semua pengertian leksikalnya disabotase!
Puisi adalah keindahan yang tinggi karena seluruh pengertian kata-kata atau diksinya bersahabat buat para pembaca. Puisi adalah teks yang tidak jadi sampah karena tiada pengertian dan arti. Puisi yang sedikit yang dapat merebut tempat di hati para pembaca adalah puisi-puisi yang mengandung pengetian yang lengkap dan utuh.
Sumbangan puisi pada kehidupan sosial adalah karena puisi ini dipahami dan dapat memberi pengertian. Karena itu harus disyukuri kalau ada puisi jujur, sebagaimana puisi-puisi berjudul diksi “geografi” yang ditemukana di dalam buku kumpulan puisi ini.
Puisi yang sejati adalah puisi yang jujur. Puisi yang jujur dan sejati itu dilahirkan oleh alam atau yang mahahidup. Para penyair hanya cerdas dalam menemukan dan memetiknya dari kehidupan.
Terlalu besar kepercayaan yang menyesatkan jika puisi itu diciptakan oleh para penyair. Tidak! Puisi itu dilahirkan oleh alam, seperti tunas-tunas lumut kebun raya dan desiran angin di sawah atau debur gelombang berbuih di lautan lepas yang ganas. Para penyair hanya pengelana dan berpotensi untuk memetik puisi-puisi dalam sepanjang hidup dan perjalannya.
Itulah jasa penyair kepada manusia dan masyarakat. Penyair memetik puisi-puisi yang sudah disiapkan oleh alam atau oleh gerimis yang membahasi batu candi. Jadi penyair bukan menciptakan teks sampah lewat bersembunyi di dalam infrastruktur bahasa dengan memporak-porandakan uraian-uraian yang dibangun susah payah oleh para leksikograf.
Penyair adalah para petualang dalam kehidupan dengan caranya sendiri. Karya yang dihadirkan kepada masyarakat adalah puisi dari kesejatian hidup. Jadi tidak ada lapis-lapis pembacaan seperti teori barat yang sangat tidak relevan bagi kehidupan manusia yang lebih utuh dan kompleks. Cara pembacaan puisi yang bertingkat atau lewat fase-fase yang asing hanya cocok bagi para pelamun. Itu pun bagi puisi-puisi yang dibuat-buat sehingga sangat sulit dimengerti.
Belum lagi ada usaha sadar para penyair untuk menyesatkan pembaca. Katanya, makin sulit puisi makin bagus! Tidak! Hal ini bohong! Hanyalah bohong besar bagi para penyair yang karya-karya akan jadi sampah. Yang masuk akal adalah makin sulit puisi dimengerti, makin buruk!
Dengan adanya dua tipe puisi (perhatikan pada judulnya) dalam buku antologi ini, menjadi bantuan penting bagi pembaca untuk memilih dua jalan puisi: antara yang jujur dan sejati dengan yang kontras atas yang dibuat-buat. Puisi-puisi pada tanda subab “I” adalah keberhasilan Made Edy Arudi dalam perjalanan sastranya untuk menapaki kesejatian puisi.
Ia sepertinya lewat puisi yang ada dalam payung pembaban (pembagian bab) “I” pada buku puisinya ini telah memilih jalan yang sejati dan jujur. Puisi telah ada di semesta dan ia datang ke Sukasada, Silangjana, Pura Dukuh Pajenengan, Kayu Putih, Padang Bulia, Tegal Linggah, Pegadungan, Pegayaman, Panji Anom, Wanagiri, Panji, Ambengan, Sambangan, Pancasari, dan Gitgit.
Ia telah kembali pada kesetiaan hidup bahwa puisi itulah kelahiran kembar buncing di Desa Padang Bulia. Dengan demikian dihadirkan satu penegasan bahwa tempat-tempat yang dikunjunginya dan dihadirkan dengan jujur di dalam buku puisinya ini adalah puisi-puisi yang telah ditulis atau diciptakan oleh semesta pada konteksnya masing-masing, entah itu petani cengkeh atau percintaan-percintaan di masa lalu di Desa Panji yang kelak melahirkan dinasti raja-raja di Den Bukit.
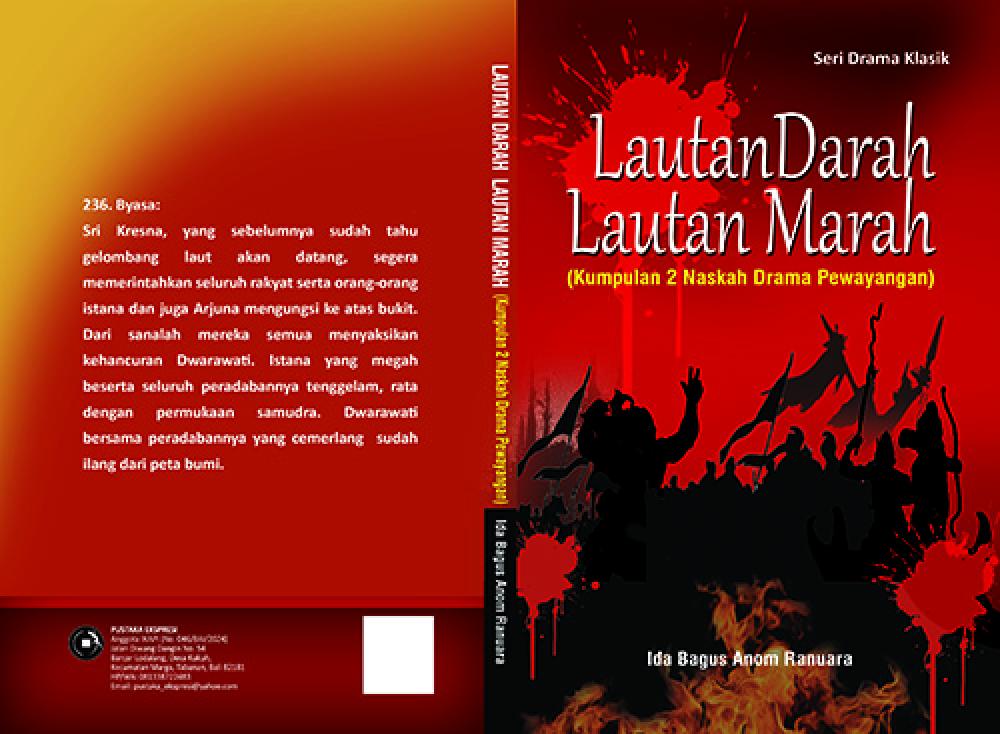
.jpg)
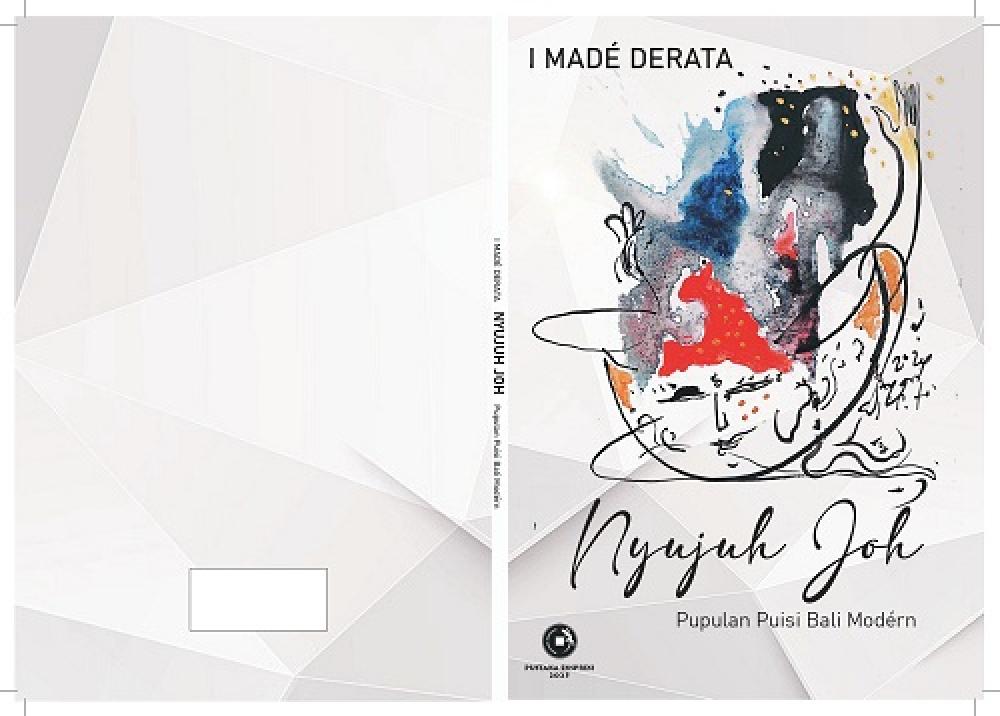
.jpg)
.jpg)
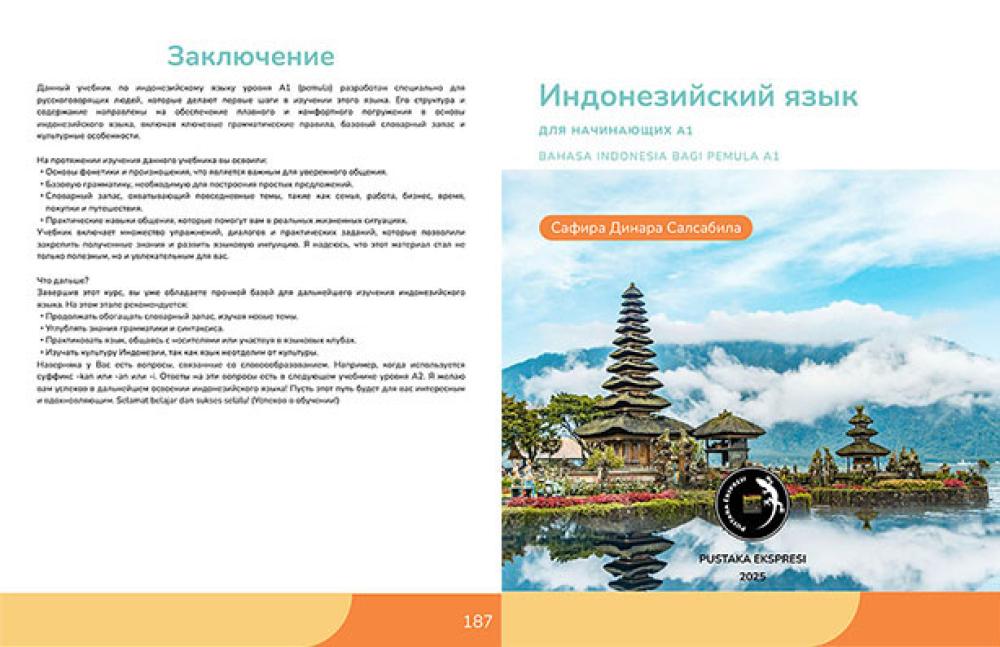
.jpg)
.jpg)




Komentar