Menyimak “Patah Tumbuh Tak Berganti”
 By Ketut Sugiartha
By Ketut Sugiartha- 25 April 2021

I Wayan Suardika termasuk salah satu pegarang Bali yang rajin menerbitkan buku sastra. Awal tahun ini ia menerbitkan Patah Tumbuh Tak Berganti, sebuah novel mungil dengan tema lumrah: menyangkut urusan pertautan hati. Kendati persoalan yang diangkat berangkat dari kejadian yang biasa terjadi di masyarakat tetapi pergolakan yang ada di dalamnya mampu menggelitik emosi. Konflik-konfliknya tidak memberi kesan banal, beda dari yang biasa dipertontonkan pada kebanyakan sinetron Indonesia yang dibuat berlarat-larat itu.
Menggunakan Bali sebagai latar tentu tak lengkap kalau tidak menyinggung sektor parwisata. Semula timbul kesan pengarang akan bertutur mengenai terguncangnya dunia pariwisata Bali gegara merebaknya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Bali menjadi minus. Namun, perkembangan usaha di sektor parwisata digambarkan demikian moncer di mana pelaku bisnis luar pun ikut bersaing untuk mendapatkan peluang menjaring rezeki. Jelas itu potret momen sebelum munculnya bencana besar yang sampai saat ini masih membuat kita cemas.
Dewi Embundaun, pelaku utama wanita novel ini, adalah putri tunggal Hartana, seorang wirausaha pariwisata kaya raya yang bisnisnya sudah menggurita. Dan Dewi adalah segalanya bagi Hartana. Selain cantik ia juga cerdas dan visioner. Dibantu olehnya, perusahaan Hartana berkembang pesat. Ketika Hartana berancang-ancang menyerahkan sepenuhnya urusan bisnis padanya, Dewi mulai akrab dengan seorang laki-laki bernama Don Dulang, seorang duda yang memberikan kursus privat menulis pada Dewi. Hartana keki. Ia tidak sudi putrinya menjalin hubungan pribadi dengan Don. Ia khawatir putrinya dimanfaatkan untuk tujuan tersembunyi oleh laki-laki yang dinilainya kere. Oleh sebab itu ia minta Adil, bodyguard-nya, untuk memisahkan mereka lewat cara apa pun asal tidak dengan kekerasan. Maka Adil menemui Rista untuk mengeksekusi tugas itu. Gadis cantik bertubuh sintal tetapi tak punya pekerjaan tetap itu berhasil memisahkan Dewi dan Don. Akan tetapi, ia sendiri, yang awalnya menjalankan misi hanya karena dijanjikan imbalan yang membuat matanya terbelalak, ternyata jatuh cinta pada Don. Padahal, Don bukanlah tipe laki-laki idaman. Ia tidak ganteng dan juga tidak kaya tetapi ada sesuatu pada diri dosen yang penulis itu. Kearifan, keterbukaan dan kehangatannya tak mungkin Rista dapatkan pada laki-laki mana pun.
Ceritanya filmis, memang. Kesan melodrama muncul pada beberapa bagian dari novel ini. Bergaya realisme pengarang menyajikan novelnya dengan bahasa yang indah. Coba simak kutipan berikut:
Jika kemudian Dara Wangi memberinya luka, itu adalah ‘luka yang manis’. Tak pernah ada demdam kepada perempuan itu sekalipun perempuan itu memberinya khianat. Benarkah cinta ialah kekuatan kasih di mana perasaan paling keji sekalipun tak akan pernah memunculkan dendam? Ataukah dirinya tak lebih dari seorang lelaki berhati lembek? (hal. 8).
Selain itu rangkaian dialog-dialognya pun bernas dan mengalir sehingga asyik untuk dinikmati. Coba perhatikan yang satu ini:
“Rista,” potong Don Dulang. “Aku sudah pernah menikah, sudah pernah dikhianati, sudah pernah kembali sendiri, sudah pernah pula mengkhianati orang lain. Aku tahu semuanya, Ris. Aku belajar dari semua peristiwa. Tak ada yang benar-benar bisa kita gang, Ris. Percayalah. Hati bagai daun talas, mudah goyah, mudah terombang-ambing, mudah jatuh. Betul bahwa tiap pribadi tak sama, tapi hati sering kali memperlihatkan kecenderungan yang sama.” (hal. 156).
Kepiawaian bertutur pengarang yang telah menerbitkan banyak buku dan meraih berbagai penghargaan ini sangat terasa. Lebih dari itu, buku mungil dengan format 11 x 18 cm ini juga berisi banyak kebijaksanaan hidup, mengandung pesan moral yang menarik. Selain itu beberapa nama pelaku yang pengarang gunakan menyiratkan kedekatannya pada tradisi. Pengarang seakan mengabaikan fenomena yang sedang menjadi tren di Bali di mana nama-nama beraroma impor sedang digandrungi. Boleh jadi pengarang ingin memberi citra yang berbeda.
Adapun tokoh utama wanita yang diangkat pengarang kali ini berbeda dengan pelaku yang ia tampilkan pada novel sebelumnya: Ni Meri. Ia bukanlah figur wanita Bali pedesaan yang dikungkung oleh nilai adat atau tradisi yang kaku melainkan wanita urban dengan segala keglamorannya. Sayangnya, dalam hal jodoh, ia masih mengalami kesulitan untuk menegakkan emansipasinya. Ini terasa sedikit ganjil. Tetapi, mengingat karya fiksi adalah pengungkapan kehidupan yang bertumpu pada realitas, kiranya tak perlu diragukan jika ini merupakan gambaran fakta sesungguhnya walaupun langka adanya.
Novel yang dibangun menggunakan sudut pandang orang ketiga ini diakhiri dengan ending menggantung. Sebuah pilihan penutup yang pas mengingat Patah Tumbuh Tak Berganti yang terdiri dari dua puluh bab ini merupakan bagian kedua dari trilogi.
Judul buku: Patah Tumbuh Tak Berganti
Penulis: I Wayan Suardika
Penerbit: Pustaka Bali Seni
Cetakan: Pertama, Januari 2021
Tebal: viii + 172
ISBN: 978-602-61144-6-4




.jpg)


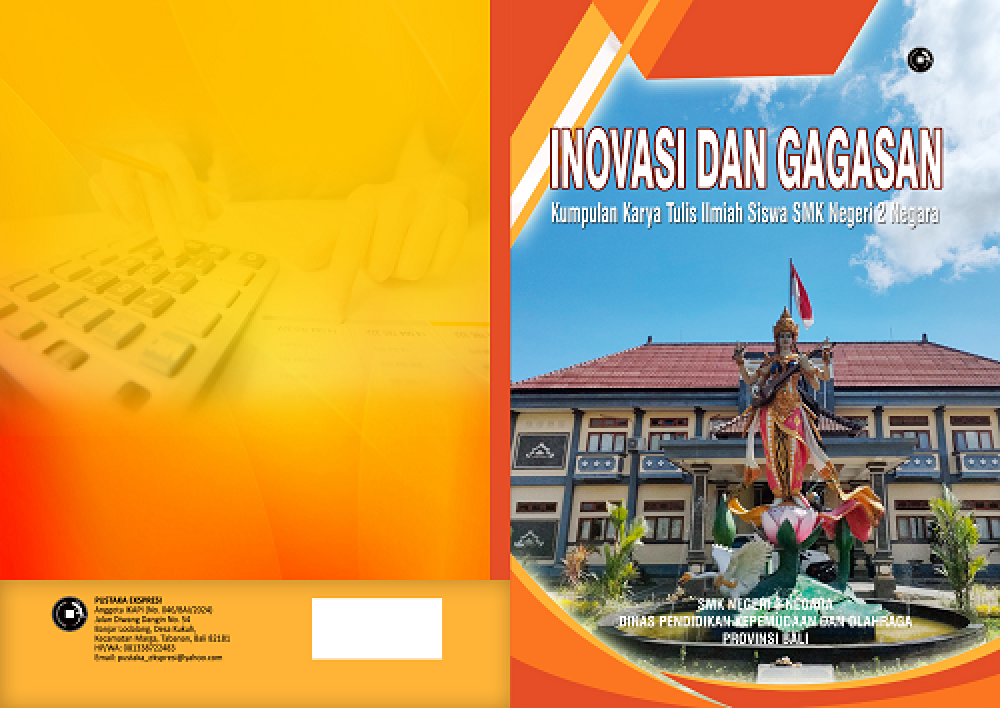
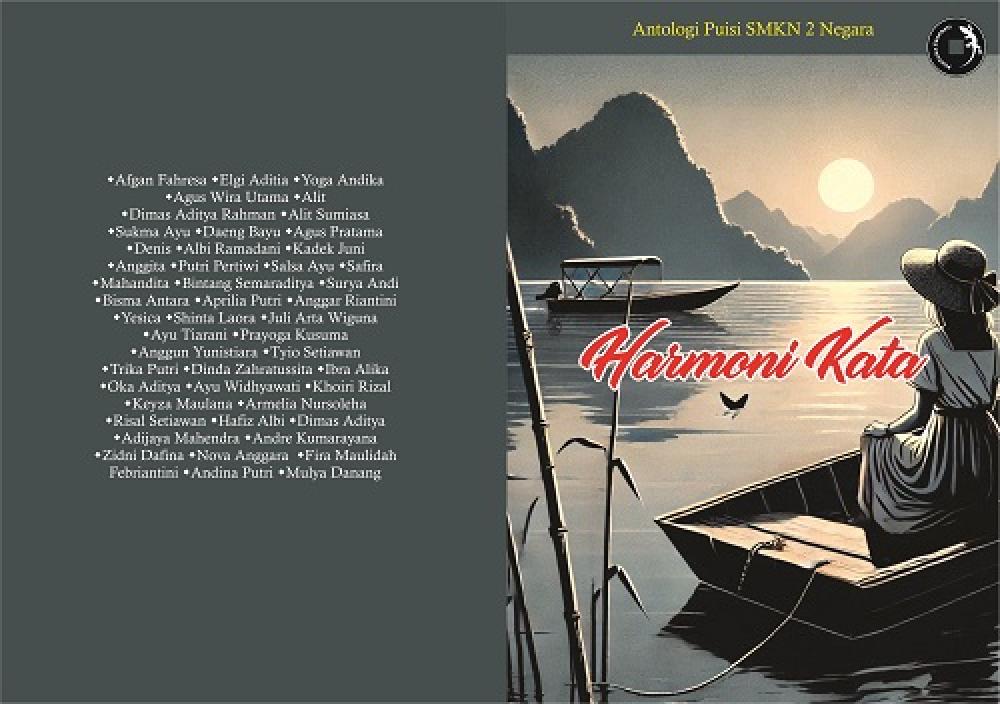
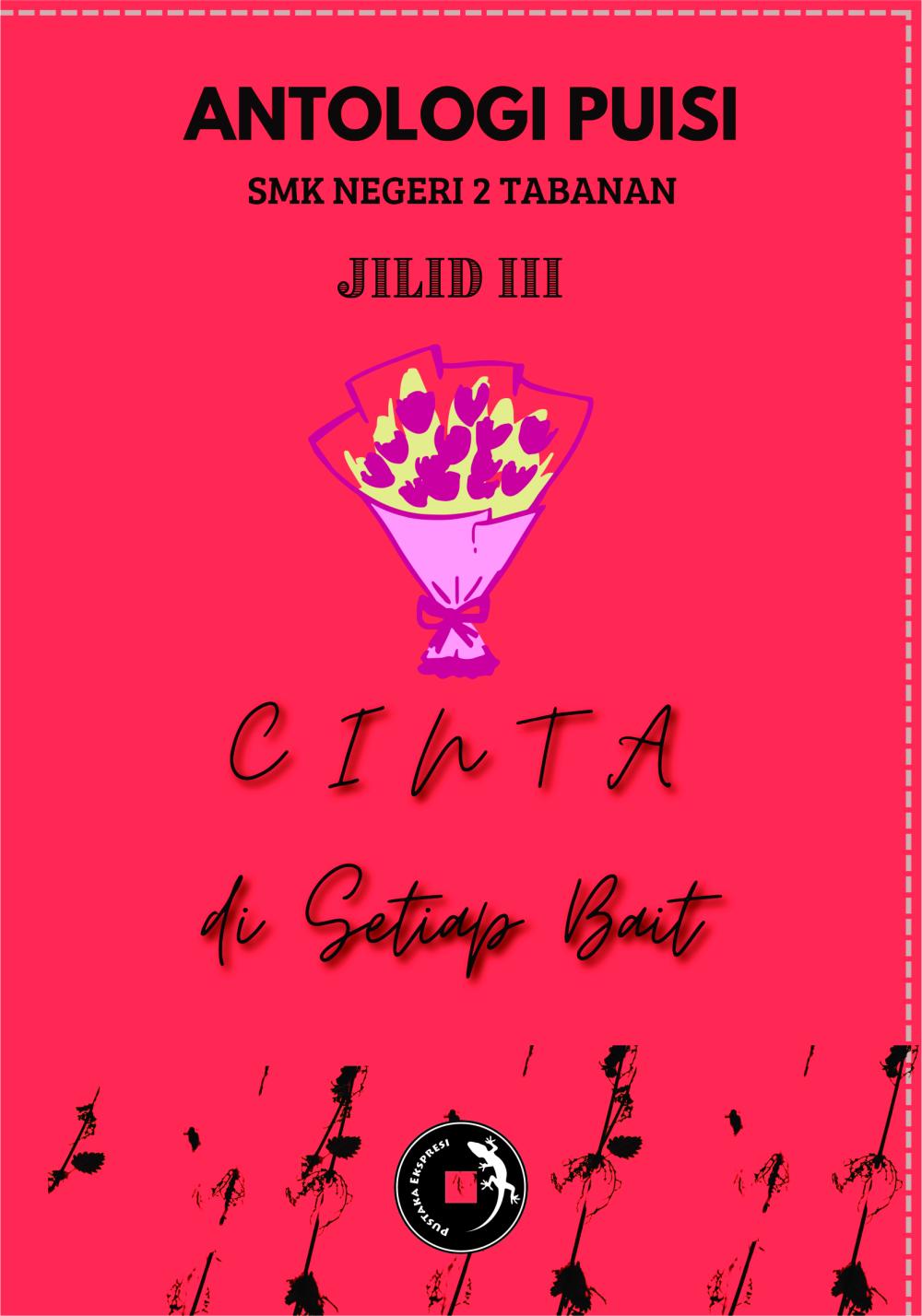



Komentar